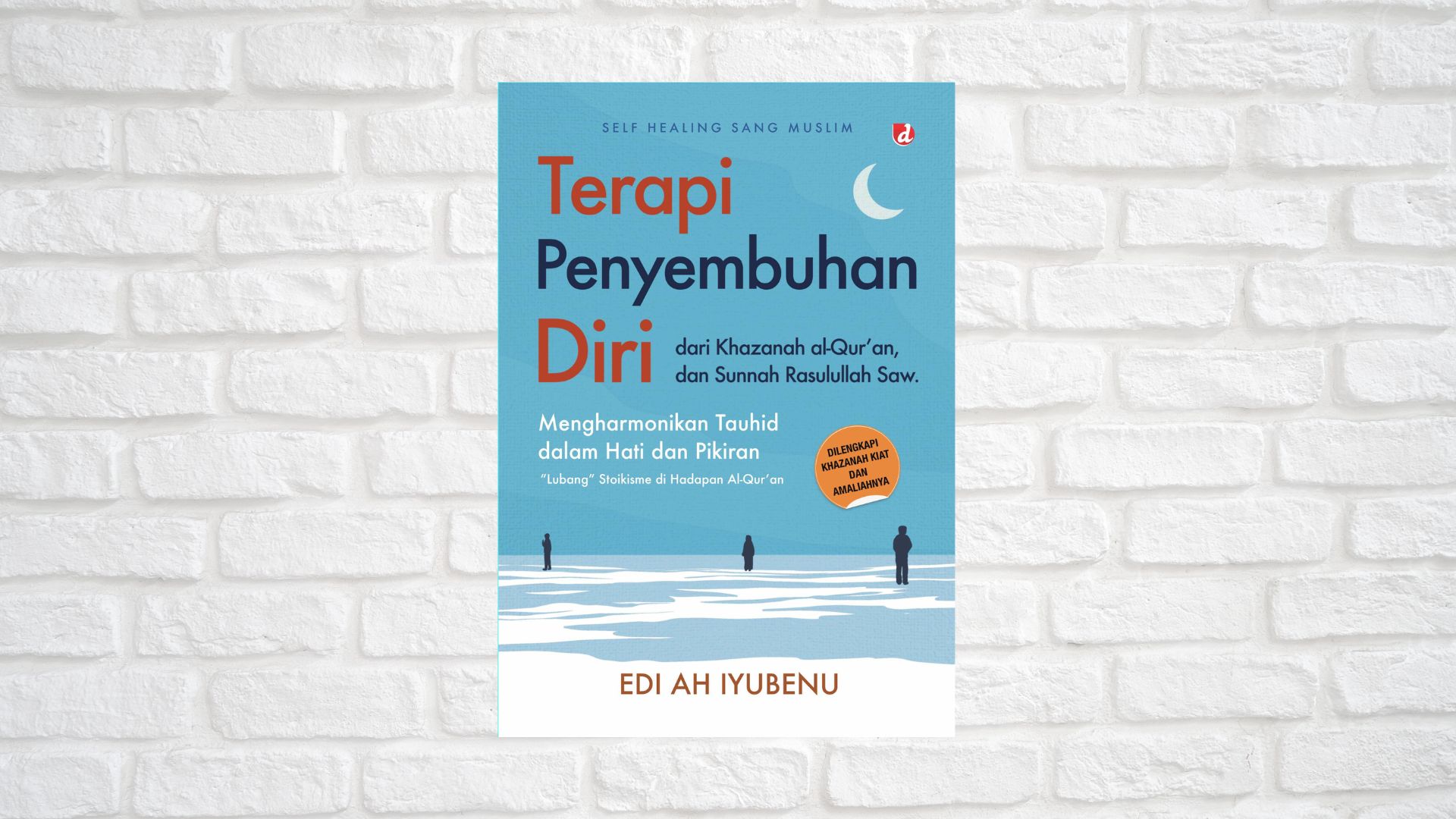Menjangkau Kebahagiaan Hidup
Judul: Terapi Penyembuhan Diri | Penulis: Edi Ah Iyubenu | Penerbit: DivaPress | Terbit: Januari, 2023 | Tebal: 380 halaman | ISBN:978-623-293-773-4
Seorang teman mengadukan keresahannya kepada saya. Kegamangan yang setiap hari menyerang kepalanya menjelang pengumaman kelulusan tes masuk Perguruan Tinggi. Selang beberapa minggu, pasca diumumkan lulus tes masuk, ia kemudian mengajukan keresahan lain. Bagaimana kalau ternyata ia tidak mendapat beasiswa, mengingat ekonominya yang pas-pasan? Kalau ternyata lolos seleksi, lalu bagaimana kalau nilainya tidak sampai pada batas minimum, bukankah nanti akan dicabut kembali beasiswa yang diberikan oleh negara?
Pada 18 Desember 2022, penggemar sepak bola di muka bumi tertuju pada titik yang sama. Di Lusail, Qatar, pendukung timnas Argentina menyimpan kecemasan yang tidak kalah besarnya. Pertanyaan-pertanyaan muskil muncul, bagaimana kalau kali ini Argentina kalah di final untuk kedua kalinya? Atau bagaimana kalau ternyata seorang Messi tidak bisa menutup kariernya dengan paripurna?
Dua cerita (persoalan) di atas sepintas memang tidak berkorelasi. Jauh panggang dari api antara seorang calon mahasiswa dan suporter sepak bola. Tetapi, dua-duanya bertemu di satu titik yang sama, kendati dengan latar belakang yang berbeda. Saya menyebutnya titik kecemasan. Sepintas teringat buku Puthut EA, Ketika Kita Punya Kecemasan yang Sama (2022). Di hadapan kecemasan, manusia hanyalah manusia. Demikian juga dihadapan kekecewaan, manusia tidak ada apa-apanya.
Persoalan terbesarnya tidak lain perihal dunia yang penuh dengan kekecewaan. Kengerian-kangerian yang tidak sanggup dipikirankan. Pernahkan Anda seminggu mengosongkan pikiran dari kecemasaan dan kekhawatiran? Sulit untuk mengatakan pernah. Adalah perkara yang teramat sukar tatkala kita hendak menghindar dari serbuan semacam itu. Itulah mengapa seruan-seruan motivasi kerap mendapat atensi yang serius. Musabab secara alamiah manusia senantiasa mencari cara berbahagia, sereceh apa pun caranya.
Tempo hari, saya dikepung kecemasan-kecemasan yang sudah tidak beraturan. Lagi-lagi seorang teman—kali ini sedikit lebih bijak—menyarankan saya untuk membaca buku Filosofi Teras: Filsafat Yunani-Romawi Kuno untuk Mental Tangguh Masa Kini (2018).
Konon, buah tangan Hanry Manampiring tersebut mampu membabat perasaan tidak bahagia hingga ke akarnya. Kemudian menabur benih lain yang kelak menumbuhkan bibit kebahagiaan anyar. Sayang, sayang hanya melihat beberapa halaman dan kurang tertarik. Waktu itu pikiran saya mengarah pada pemakluman yang filosofis, biarlah kecemasan terus beranak-pinak. Pada akhirnya ia akan pergi dengan sendirinya, kendati berganti kecemasan yang lain.
Mafhum betapa larisnya buku Filosofi Teras. Ia menjadi semacam panduan manejemen perasaan dari hal-hal yang mengecewakan. Berpijak pada kearifan ala kaum Stoa di Yunani kuno. Secara praktis, ia membedakan dua hal dalam diri manusia. Pertama, hal-hal internal dalam diri manusia yang bisa dikontrol dengan presisi. Kedua, hal-hal eksternal yang tidak dapat dikontrol oleh manusia. Ingat, saya hanya membolak-balik beberapa halaman buku Filosofi Teras. Perihal dua klasifikasi ini saya menyimak teman itu tadi.
Sampai di titik ini sungguh benderang. Segala cara yang mengantarkan manusia menuju bahagia mendapat tempat tersendiri. Buku semacam Filosofi Teras dan sebangsanya itu adalah salah satu bukti. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa ternyata ada satu kearifan lain yang kerap kita lupakan. Maksudnya, sebuah sistem manajeman perasaan untuk dapat menjangkau kebahagiaan. Tepat di titik tersebut, buku Terapi Penyembuhan Diri hadir ke sidang pembaca. Uniknya, secara khusus penulis melangkah lebih jauh dengan melihat lubang Stoikisme dihadapan Al-Qur’an. Seketika tampak tidak apple to apple, namun demikianlah yang tersaji di sini.
Penulis mencoba mengelaborasi panduan bahagia yang berjangkar pada ajaran Islam. Tentu, panduan semacam ini hanya seleras dengan orang yang sekeyakinan dengan penulis. Karena memang kepada para pembaca yang demikian buku ini dihaturkan. Tanpa canggung buku ini dimulai dengan prolog yang menyentak. Sebuah pertanyaan yang sedikit retoris, mengapa seseorang mudah menjadi sedih dan takut? Penulisnya sejak awal memang mengakui ini bukan buku dengan analisis medis, melainkan islamis.
Karenanya fondasi pokok dalam membangun manajemen perasaan berpijak pada khazanah keislaman. Di beberapa bagian, penulis mengalaborasi dengan gamblang dua entitas penting dari diskursus keislaman, yakni antara ikhtiar dan tawakal. Dalam khazanah keislaman, dua hal ini menjadi penting. Seseorang yang kehilangan salah satunya akan mengalami ketidakseimbangan. Keduanya tidak kurang dan tidak lebih seperti rel yang terus beriringan.
Jika seseorang mengandalkan sepenuhnya usaha yang dilakukan, maka kemungkinan besar akan didera kecewa tatkala tidak sesuai ekspektasi. Dalam iman sang muslim, segalanya pada akhirnya berada di tangan Tuhan. Terlihat sangat fatalis, bukan? Kenyataannya memang seperti itu ajaran dasar yang mengakar di kalangan umat Islam. Atas dasar ini, penulis mencari celah Stoikisme yang kunci pokoknya berada pada kemampuan personal dalam mengelola keinginan agar tidak terjebak kecewa.
Ringkasnya, dapat dimafhum bahwa penulis hendak mengatakan langkah ala Stoikisme sepintas menafikan andil Tuhan. Padahal, sebagaimana ia yakini, segalanya tidak mutlak dapat dikelola dengan baik tangan manusia. Artinya, ketika Anda sudah berhasil memanjemen hasrat dan keinginan, bukan berarti segalanya mengalir lancar sebagaimana pandangan Stoikisme. Ada hal di luar kemampuan mengelola hasrat tersebut dalam menentukan kebahagiaan. Tepat pada titik inilah penulis menghadirkan Dzat yang Maha di atas segalanya.
Seolah-olah memang mengerdilkan peran manusia dalam mengatasi persoalan mentalnya. Usaha yang dilakukan oleh manusia di sini, tidak lebih hanya sekadar usaha. Sementara penyelesaian akhirnya (finishing) berada di tangan Tuhan sepenuhnya.
Dengan kata lain, segala urusan dilarikan dan bermuara kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menguasai jagat ini, dengan mudah dapat menjadikan apa pun. Bahasanya vulgarnya, Tuhan bisa menjadikan segalanya hal yang tampak mustahil. Apalagi hanya untuk menyingkirkan segala macam takut, kecewa, serta kengerian dipikiran manusia.
Untuk sampai di titik Tuhan ikut andil di segala kerunyaman masalah kita, maka diperlukan kiat (amaliah). Penulis di antaranya menyebutkan beberapa amaliah yang jika tekun diamalkan bukan mustahil akan mengangkat segala kepelikan dalam pikiran.
Apakah amaliah yang disodorkannya di sini merupakan hal yang baru? Tentu tidak, bahkan sebagian besar kita sudah mengetahuinya. Hanya saja penulis di sini mencoba untuk menggali kembali khazanah yang sepertinya terpendam. Kemudian diaplikasikan untuk menanggulangi apa yang kita sebut sebagai mental disorder.
Terlihat sangat normatif, sebab sumbernya berasal dari ajaran normatif. Menariknya, penulis tidak hendak mencampakkan konsep bahagai ala kaum Stoa itu. Tidak. Melainkan memberikan sebuah alternatif yang relatif lebih selaras dengan khazanah keislaman. Ia juga tidak mengatakan bahwa apa yang diajarkan kaum Stoa bertentangan sepenuhnya dengan norma Islam. Melainkan hanya sedikit bolong yang kemudian dikoreksi. Saya memafhumi ini sebagai usaha tambal sulam bagi Stoikisme agar senapas dengan apa yang diserukan Islam.
Saya tidak ragu menyebutnya sebagai Stoikisme baru ala muslim. Kendati tentu banyak yang tidak sepakat dan merasa ganjil. Titik temunya, baik Stoikisme ini dan Stoikisme Yunani itu, berada pada satu hal yang sama dan senapas. Tidak lain hanya untuk mengusir segala macam kepelikan, kecemasan, hingga kekecewaan. Hal ini yang belakangan memang marak menimpa umat manusia, umat Islam juga. Jangan-jangan memang ada yang harus diperbaiki dari cara kita berislam dan beriman selama ini. Jangan-jangan!
Category : resensi
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan
- Buku Ngaji Pascakolonial