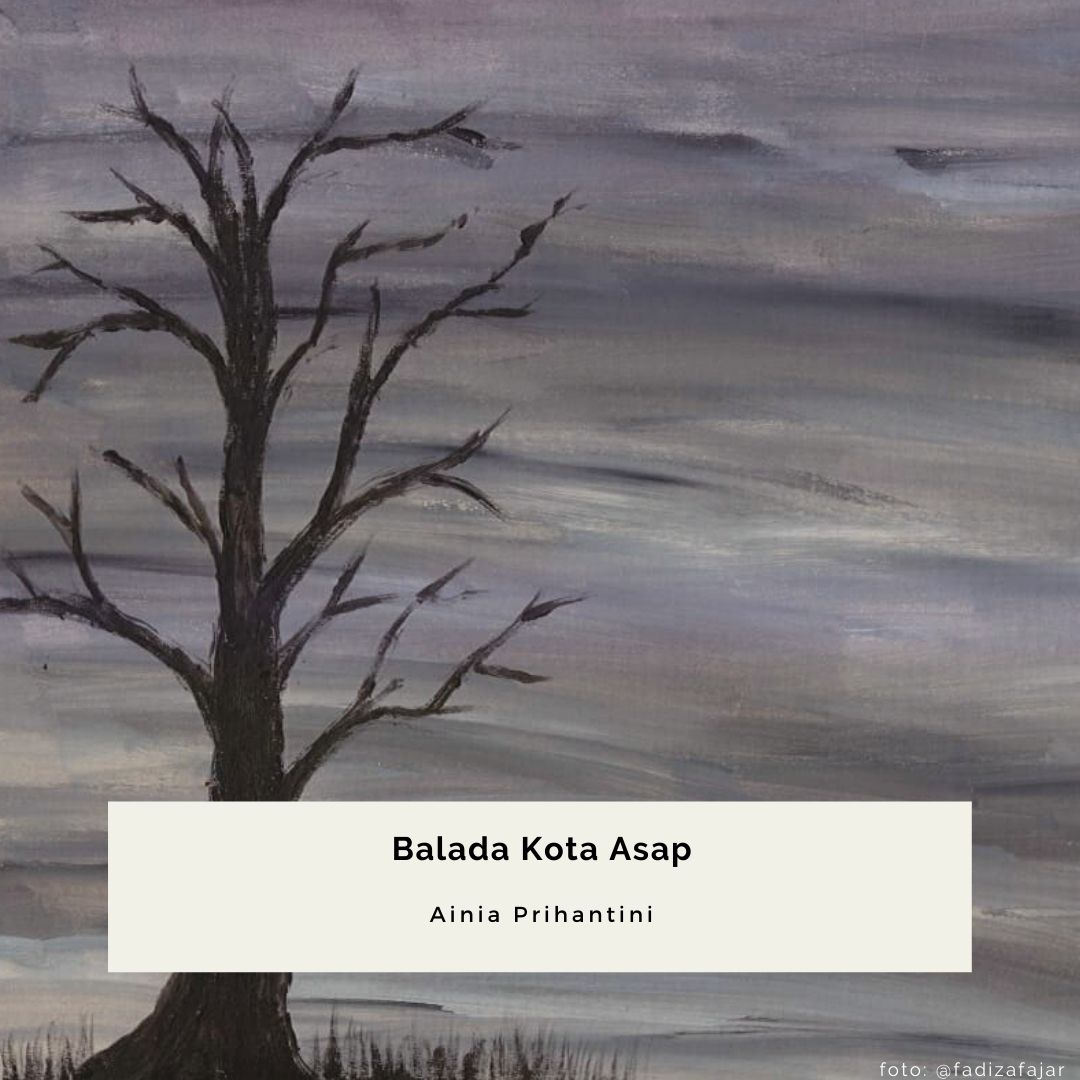Balada Kota Asap
Aku tak bisa menyapa bulan yang hampir bundar sempurna dan keemasan di langit timur. Sebab, kabut sedang menjadi. Kalau beruntung, mungkin aku bisa melihat bulan yang berubah kuning kemerahan dan matahari yang menjadi oranye di sini. Dan jika itu terjadi, mungkin nanti kita bisa bertemu lagi di satu titik sudut pandangan di langit.
Oh iya, jangan bayangkan kota ini sama seperti kotamu. Tidak ada pohon-hujan yang mampu menyaring berton-ton karbon dan nitrogen di sini. Tolonglah Mus, kau terlalu naif memandang pola pikir orang-orang di gedung sini. Sungguh membuang waktu dan tenaga jika aku sampai mengajukan permohonan trembesiisasi pada mereka. Kalau mereka benar-benar peduli, kebakaran tidak akan menjadi agenda tahunan.
Mari sini, aku jelaskan skenarionya ...
Musim penghujan datang. Penduduk tengah akrab dengan hujan yang mengisi minggu-minggu mereka. Matahari dengan sinar kuningnya menyapa di langit yang biru. Udara terasa begitu segar dan jarak pandang pun nyaris tak terbatas. Di sisi lain, calo-calo toke sawit mulai melata di atas bumi. Mereka datang dengan langkah yang tidak begitu mencolok—sudah kubilang kalau mereka melata—menuju beberapa gedung. Di sana, mereka meninggalkan banyak “titipan” pada banyak orang di dalamnya. Segala macam perizinan untuk membuka lahan baru tengah diusahakan masuk ke dalam brankas-brankas para toke. Toke-toke pun akhirnya mengantongi cap legal atas lahan-lahan yang akan dijadikan perkebunan sawitnya.
Apa kau tahu Mus, orang Melayu yang punya lahan menganggur sedikit saja di sini, bakalan langsung menjual tanahnya ke toke sawit.
Beberapa bulan setelahnya ... Saat yang dinantikan pun tiba. Musim k-e-m-a-r-a-u (maafkan aku memakai cara penulisanmu untuk penekanan) datang. Toke sawit, melalui orang-orang kepercayaannya yang lain, mulai berburu eksekutor. Mereka mencari penduduk setempat untuk melakukan pembakaran lahan. Para eksekutor yang berasal dari kalangan warga biasa itupun tidak mempermasalahkan jika harus dibayar dengan sangat murah. Bagi mereka, sekedar untuk makan sehari-hari saja sudah cukup. Dan, kesepakatan pun terjadilah.
Kenapa musim kemarau? Karena pada musim ini, lahan gambut yang umumnya memenuhi daerah di sini, jika terkena percikan api sedikit saja, akan mampu menyimpan api abadi. Api abadi yang tak akan padam hingga hujan lebat turun secara merata selama berjam-jam lamanya. Sesuatu yang sangat sulit untuk dibayangkan akan terjadi pada musim kemarau panjang.
Aha ..., pembakaran pada lahan gambut itu akan sangat membantu membinasakan tumbuhan hijau. Lahan yang masih ditumbuhi pepohonan lebat atau semak belukar setinggi dua meter pun kemudian dibakarlah. Apakah kau tahu Mus, biaya pembukaan ratusan hektar lahan secara legal bisa mencapai miliaran rupiah? Apakah kau juga tahu, hanya butuh setidaknya satu juta rupiah untuk menyewa satu eksekutor? Pembakaran, dengan sendirinya membuat biaya pembukaan lahan menjadi sangat-sangat-rendah, bukan?
Jadi, satu-satunya pengeluaran tinggi—yang jumlahnya pasti tidak sampai miliaran—yang dikelurkan toke sebelum penanaman sawit dimulai hanyalah berupa biaya “titipan” yang dibawakan para calo—sekali lagi dengan cara melata—kepada orang-orang di gedung itu pada musim hujan tempo hari. “Titipan” itu memang sengaja diberikan kepada orang-orang necis yang sering tampil di media untuk berkoar-koar mengutuk aksi pembakaran lahan. Kemarau juga sering dipakai sebagai kambing-hitam-utama untuk mengalihkan isu. Kemarau dijadikan alasan timbulnya titik-titik api yang jumlahnya ratusan itu.
Begitulah...
Hingga waktu kejadiannya berlangsung agak lama, kau bisa melihat kota tempatku menetap (dan daerah-daerah di sekitarnya) menjadi headline di televisi. Mungkin saat itu, kau sedang menontonnya sambil menghirup udara segar di Jogja atau kampung halaman. Dan pada saat itu pula, media berlomba meningkatkan rating acara dengan memberitakan secara besar-besaran kondisi yang katanya sudah sering disebut sebagai bencana-alam. Kembali, alam dipersalahkan ...
Sontak saat sebuah berita sudah menjadi isu nasional, sok sibuklah orang-orang pusat di Ibukota. Kemudian, mulai berdatanganlah para Menteri. Di saat yang lain, Wakil Presiden menyusul. Dan bahkan, karena mengingat semakin dahsyatnya pemberitaan di media, maka Presiden pun dipandang perlu oleh orang-orang sekelilingnya untuk datang. Sidak, katanya.
Pada saat yang sama, saat orang-orang pusat sok sibuk, orang-orang di jajaran daerah Melayu pun ikutan sok sibuk. Diupayakanlah rekayasa hujan buatan dengan teknologi yang dicanggih-canggihkan. Kemudian, ada saatnya hujan buatan itu pun turunlah. Konon, biayanya mencapai miliaran rupiah.
Tapi, tahukah kau? Intensitas hujan buatan yang turun itu layaknya sepuluh balita yang sedang berbaris lalu dipaksa terkencing-kencing dari langit. Tentu saja tidak ada pengaruhnya bagi kebakaran lahan yang semakin menggila. Semua menjadi sok sibuk di mataku. Bahkan, pemuka agama pun didesak untuk ikut dalam arus-sok-sibuk itu. Mereka didorong untuk menggalakkan shalat istisqa’ di segala penjuru kota. Seakan-akan, mereka sedang berkata, “Ya... Allah, ya... Tuhan kami, kami sudah melakukan perbuatan laknat yang menimbulkan kerusakan. Sekarang, tolong bereskan kekacauan yang telah kami perbuat. Turunkan hujan. Segera!!!”
Tak lama berselang, ketika kemarau mendekati masa akhir, turunlah hujan dengan rahmat Allah Yang Mahakuasa. Jumlah titik api menurun drastis. Udara perlahan kembali bersih. Tapi ternyata, pemberitaan belum juga surut. Karena itu, perlu dilakukan sesuatu yang lain. Tujuannya? Tentu saja agar orang-orang di gedung itu dianggap melakukan sesuatu selain rekayasa air kencing... eh, air hujan tadi. Maka, dicarilah tersangka. Apapun dan bagaimanapun caranya, seseorang harus ditangkap.Tapi siapa? Tokek sawit? Tidak mungkin!
Sudah ada banyak “titipan” untuk orang-orang di dalam gedung. Kalau toke yang diseret, maka semua yang makan “titipan” akan terseret pula. Sementara itu, suatu reportase di TiviSepuluh menyatakan, “Pemerintah dinilai lamban dalam menangani pelaku pembakaran lahan... bla...bla...bla...” Nah, itu dia! P.e.l.a.k.u—p.e.m.b.a.k.a.r.a.n—l.a.h.a.n! Mari tangkap eksekutornya!
Kemudian, datanglah aparat terkait ke sebuah perkampungan. Rumah seorang eksekutor miskin itupun kedatangan tamu tak diundang. Kala itu, kalau tidak salah, istrinya sedang girang menanak nasi dari beras yang dibeli suaminya pagi tadi. Belakangan, suaminya memang sedang banyak uang. Ia tidak tahu dari mana asalnya. Yang ia tahu sekarang, anaknya yang bertelanjang dada sedang tak kalah girang menunggu nasi itu matang sambil menelan ludah di kerongkongannya, membayangkan bahwa hari itu mereka akan makan enak. Seiring menguarnya wangi nasi yang masih setengah matang, tamu tak diundang itupun masuk dan membawa paksa sang suami sekaligus ayah tercintanya. Para tamu tak diundang mengatakan bahwa lelaki kurus yang berkulit hitam itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya.
Pemberitaan tentang pembakaran pun mulai menyurut. Persidangan Si Eksekutor Miskin yang kurus-hitam itu ganti mewarnai layar kaca. Hingga akhirnya, segala bentuk berita dihentikan seiring penjatuhan vonis bagi Si Eksekutor Miskin. Semua mulai merasakan kesenangan. Masyarakat senang dengan udara yang kembali segar. Orang-orang di pusat dan di gedung itu juga senang. Toke sawit pun tak kalah senang. Semua senang, hingga musim kemarau berikutnya...
Tapi percayalah, Mus, cerita di atas hanyalah fiktif belaka. Jika ada kesamaan tokoh dan peristiwa, itu adalah sesuatu yang tidak disengaja. Sekarang, katakan padaku, Mus, apakah kau masih percaya dengan pernyataan yang mengatakan bahwa alam mampu membakar dirinya sendiri tanpa ada pemicunya?
*Buletin Jumat Masjid Jendral Sudirman, Jumat 18 September 2015.
Category : buletin
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan
- Buku Ngaji Pascakolonial