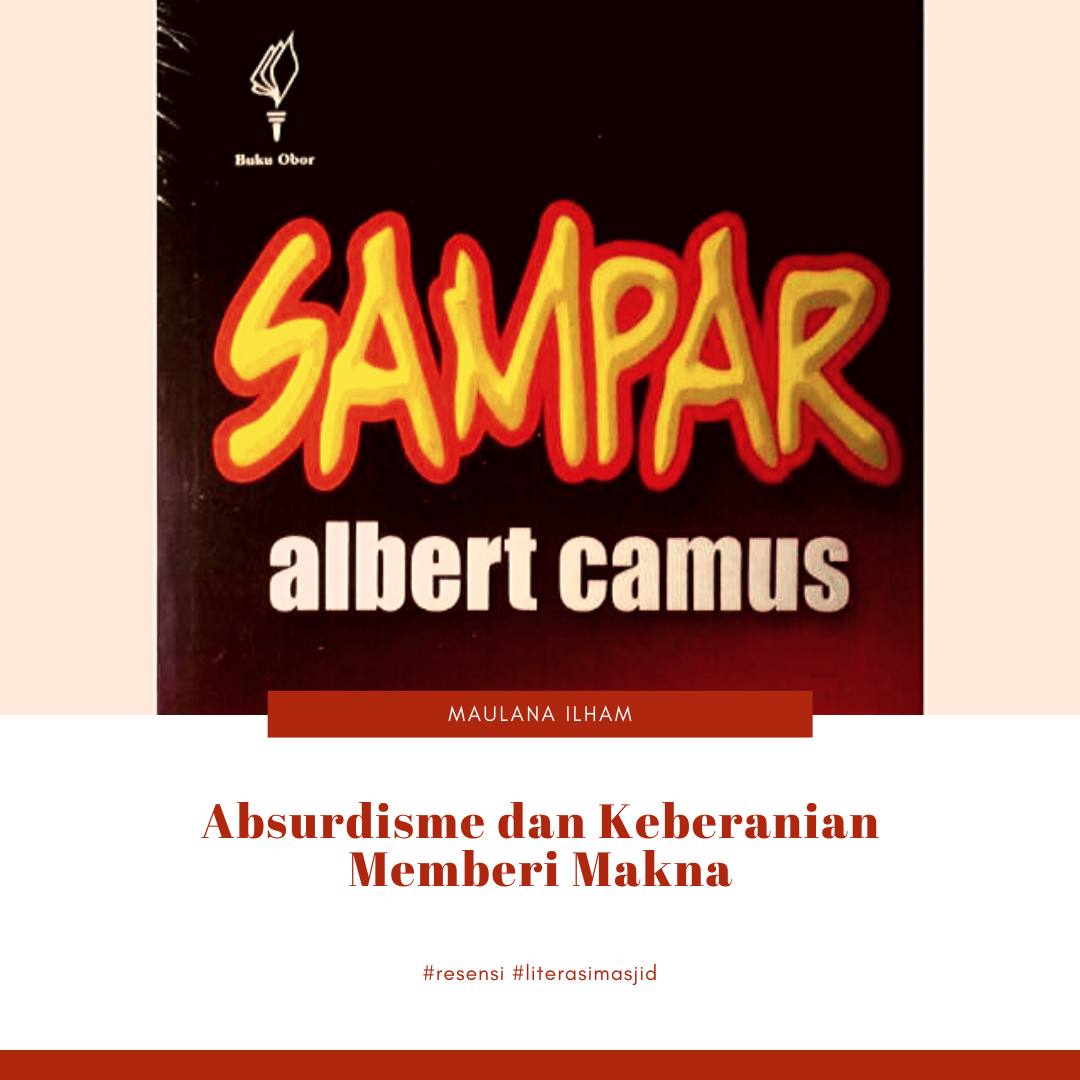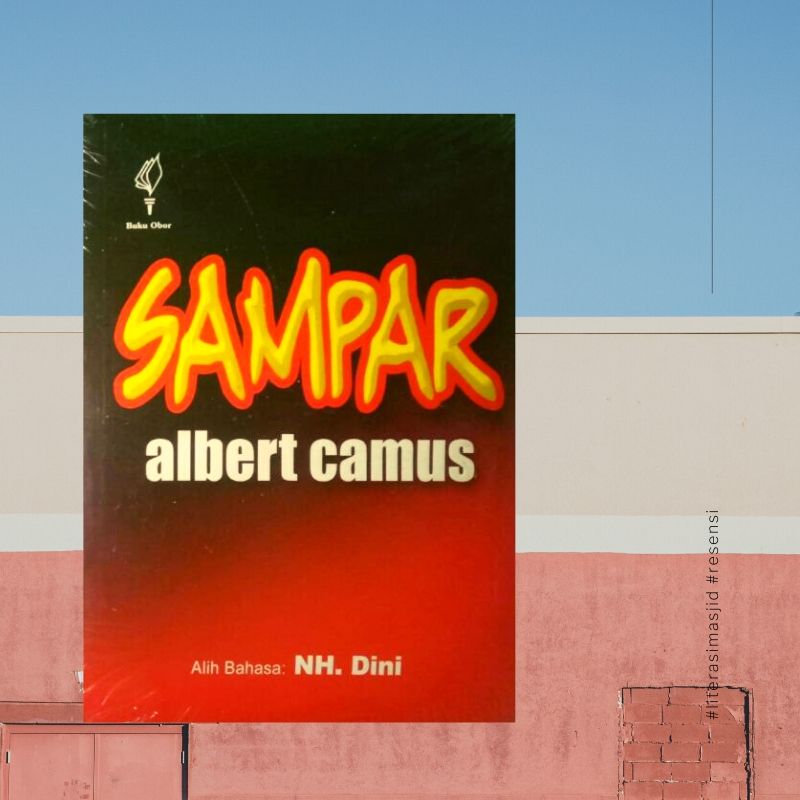Absurdisme dan Keberanian Memberi Makna
Judul: Sampar (Judul asli: La Peste) | Penulis: Albert Camus | Penerjemah: NH. Dini | Penerbit: Yayasan Obor Indonesia, 2014 | Tebal: x + 386 halaman | ISBN: 978-979-461-582-9
Sudah pernah membaca Orang Asing karangan Albert Camus yang lain sebelumnya? Jika di Orang Asing kita diajak untuk fokus pada seorang tokoh yang bernama Meursault dengan segala rutinitas kehidupannya dan ke-absurd-an di dalamnya. Kalau di Sampar kita tidak bisa hanya fokus kepada tokoh utama, yakni seorang dokter bernama Rieux yang berjuang melawan wabah, melainkan ke semua karakter yang terdapat di dalamnya karena Sampar berbicara bagaimana kita, manusia, dihadapkan pada situasi mencekam, yakni wabah mematikan sampar. Di Orang Asing kita melihat dunia dari kacamata absurd seorang Meursault sehingga kita pun menganggap orang-orang yang ditemui Meursault merupakan orang-orang yang absurd, atau justru kita menganggap malah Meursault sendirilah yang absurd. Sedangkan di Sampar kita dibebaskan untuk menafsirkan bagaimana setiap tokoh menghadapi kematian (wabah mematikan), dan itu justru mencerminkan betapa absurdnya kita, manusia. Solidaritas kita diuji. Iman kita diuji. Cinta kita pun diuji.
Oran, latar tempat wabah penyakit sampar itu, menjadi kota mati ketika kota tersebut harus diisolasi sesegera mungkin agar wabah mematikan tersebut tidak sampai menyebar ke luar kota. Wabah sampar merupakan epidemi, bukan pandemi. Oran digambarkan sebagai kota kecil yang sepi dan membosankan. Warga Oran sibuk dengan rutinitas hariannya, bekerja dan mencari hiburan. Disebabkan Sampar sebagai novel filsafat, Camus fokus kepada diri karakter-karakter di dalamnya dan sangat baik dalam menggambarkan bagaimana sikap orang-orang dalam menghadapi kematian. Jadi, hemat penulis, novel ini lebih menekankan pada bagaimana manusia menyikapi kematian daripada menceritakan wabah kematian itu sendiri.
Kota Oran diisolasi. Hubungan dengan dunia luar diputus, kecuali untuk kepentingan logistik. Sekolah dan perkantoran ditutup. Tempat hiburan seperti bioskop sepi pengunjung. Semua orang yang berada di kota tidak bisa keluar dari Kota Oran. Mereka dikurung di sebuah sangkar bersama burung kematian. Pilihannya hanya dua, melawan wabah mematikan atau menjadi absurd.
Dengan ditutupnya kota, orang-orang mulai kebingungan apa yang mesti mereka lakukan setiap harinya. Di sisi lain mereka semakin ketakutan melihat satu demi satu manusia bertumbangan. Apa yang harus dilakukan hari ini? Harus ke mana mereka esok hari? Di kota mati itu orang-orang menyalakan kendaraannya untuk mengitari kota yang kecil itu, tidak jelas. Berjalan-jalan pagi dan sore, apakah masih perlu? Tak punya arah karena sudah tidak lagi bekerja ataupun bersekolah. Jika ada tetangga yang berteriak dari dalam rumah, tanda bahwa ada keluarganya yang terjangkiti virus tersebut, orang-orang tidak lagi memenuhi jalan mencari tahu ada kejadian apa. Terlalu seringnya kabar kematian yang mereka dengar membuat mereka terbiasa dan menganggap bahwa kematian menjadi hal yang wajar. Toh mungkin besok juga giliran mereka.
Dengan ditutupnya kota, orang-orang merindukan kekasihnya yang berada di luar kota. Ia diambang kematian sedangkan kekasihnya tidak hadir di dekatnya. Apa yang seharusnya ia lakukan? Keluar kota dan mencari kekasihnya lalu menularkan penyakit tersebut kepada kekasih dan orang-orang di luar sana? Apa cukup berdiam diri di kota mati itu hingga ajal menjemput? Sedangkan hari demi hari ia makin kesepian karena jauh dari sang kekasih? Begitu juga dengan keluarga. Tentu dalam situasi mencekam seperti itu, orang-orang sangat merindukan kehangatan keluarganya. Tapi apa yang harus ia perbuat? Entah.
Baca juga: Ekstensi Orang Asing: Absurdisme Albert Camus
Di hari-hari awal masyarakat berkumpul di gereja untuk mendengarkan sang pastur berkhotbah. Seperti yang biasa diucapkan oleh para pemuka agama ketika ada musibah, sang pastur berkata bahwa ini ujian dari Tuhan untuk orang-orang yang berdosa. Lantas hari demi hari jemaat bosan mendengarkan khotbah yang dirasa tidak mengubah keadaan. Berdoa dan terus mencoba menenangkan diri bukanlah sebuah solusi. Korban tetap berjatuhan tiap harinya bahkan seorang anak kecil tak berdosa pun meninggal. Apa benar ini merupakan hukuman Tuhan? Keberimanan di saat mencekam seperti itu menjadi sesuatu yang membingungkan. Gereja pun ditinggalkan.
Memangnya harus berbuat apa lagi untuk menghadapi kematian yang sudah di depan mata itu? Kebut-kebutan di jalanan yang sepi tak ada kemacetan sedangkan setiap beberapa jam sekali terdengar sirene ambulan berbunyi. Diam di rumah dan menengok dunia lewat jendela, betapa matinya kota ini. Melihat orang-orang yang masih berkumpul. Mengobrol tidak jelas. Mengejek pemerintah yang dianggap tak becus dalam menangani wabah. Menghujat wabah mematikan itu. Atau mengamati pemuda yang berkelahi di pinggir jalan tanpa sebab yang jelas. Entah karena cinta atau hanya karena sedang saling mempertahankan argumen. Atau memerhatikan anak-anak yang bermain di luar, di jalanan maupun di lapangan. Melihat bagaimana beberapa anak dipaksa pulang oleh ibunya agar tetap di rumah agar tidak tertular virus. Atau justru melihat seorang anak yang bermain sendirian karena teman-temannya sudah tidak diperbolehkan bermain di luar.
Itulah gambaran masyarakat yang sedang dihadapkan dengan kematian. Ditempatkan di sangkar yang sama dengan burung kematian. Gelisah namun juga bingung. Rindu namun juga bimbang. Camus berhasil menggambarkan keadaan membingungkan itu. Penulis pun ikut menafsirkan betapa kacaunya keadaan saat itu yang kebetulan juga sedang kita alami hari ini. Entah sudah seberapa membingungkannya situasi hari ini. Sudahkah kita kehilangan solidaritas kita sesama manusia? Apakah iman kita sudah goyah? Sudahkah kita menderita akibat merindukan sekaligus mengkhawatirkan sang kekasih nun jauh di sana? Pilihannya hanya dua, melawan wabah mematikan ini atau menjadi absurd.
Menurut absurdisme, manusia sepanjang sejarah berusaha untuk menemukan makna hidup. Pencarian ini biasanya berakhir dalam satu dari dua kemungkinan. Pertama, hidup ini tidak bermakna. Kedua, hidup ini memiliki tujuan yang berasal dari kekuatan yang lebih tinggi. Bagi Camus, manusia dapat menciptakan makna dalam kehidupan mereka sendiri, yang mungkin tidak obyektif (seandainya makna obyektif itu ada), namun dapat membuat hidup berharga dan layak untuk diperjuangkan. “Orang harus berani menghadapi kehidupan, berjuang melawan absurditas dan ketidakbermaknaan dengan cara memberi makna sendiri” (Ngaji Filsafat: Albert Camus – Absurditas, 27 Maret 2019).
Category : resensi
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Alam Pikiran Jawa-Islam: Filologi, Simbol, dan Struktur Babad Kraton
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan