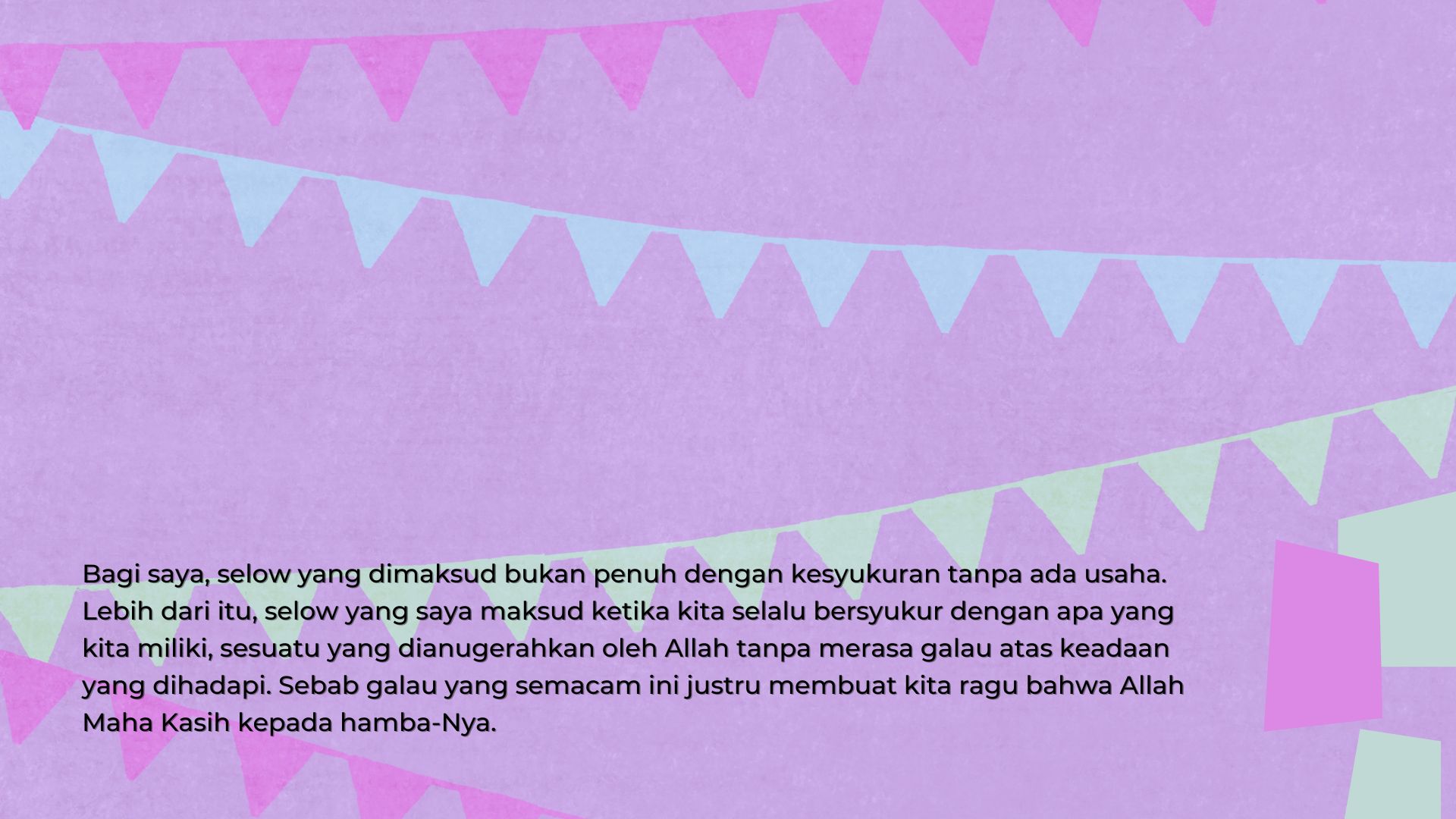Selow Menjalani Hidup
Melalui judul ini, saya ingin menyempurnakan keselowan menjalani hidup dengan pelbagai planning yang sudah saya tulis rapi-rapi, mulai dari jangka pendek yang berupa mingguan, bulanan, hingga jangka panjang berupa rencana tahunan. Tetapi nyatanya tidak semua berjalan sesuai rencana yang sudah tersusun rapi itu.
Pernah juga menjalin hubungan yang begitu lama. Pada akhirnya nikahnya dengan yang lain, bukankah itu sebuah perencanaan matang agar saya dengan dia bisa bersama? Apakah ini bentuk ekspresi selow saya karena tidak cepat-cepat mengiyakan keseriusannya?
Selow yang saya maksud buka semacam itu, sebab pada akhirnya saya kembali pada pemahaman bahwa Allah belum menghendaki saya untuk melakukan itu serta belum menghendaki untuk kita bersama.
Sekali saya merasa mumet dengan impian-impian yang saya tulis rapi, ingin seperti ini, jadi terkenal, punya banyak duit, kemudian ketika tidak semuanya tak tercapai, alhasil saya galau sendiri. Rasanya memang dunia tidak berpihak kepada saya.
Lalu seorang teman menghampiri saya yang masih dalam kondisi mumet dan berujar, “Kamu boleh berharap kepada Tuhan, tapi kamu tidak boleh mendikte Tuhan atas semua keinginan yang sudah ditulis”, ungkapnya.
Sejenak saya berpikir, bahwa apa yang dikatakan teman tadi memang benar. Andai saja saya tidak punya keinginan ini dan itu, pasti saya akan merasakan baik-baik saja, tanpa merasa pusing dan segala macamnya.
Benar saja, hal tersebut juga disampaikan oleh K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha) dalam salah satu kajiannya, “Imam yang mengarang kitab Hikam itu punya resep agar hidupmu seneng terus. Usahakan sedikit sekali apa yang bikin kamu senang, maka sedikit sekali yang bikin kamu susah. Karena tarifmu ideal, harus ini dan itu, maka kekecewaan datang juga semakin besar. Pakai standar yang minimalis saja. Rasulullah juga begitu, jika tidak tersedia makanan, maka beliau puasa”.
Sayangnya, kita hari ini hidup dengan penuh problem yang luar biasa. Terkadang tolok ukur kebahagiaan yang kita rasakan berdasarkan kesepakatan umum di hadapan orang-orang. Kalau dulu konsep kebutuhan yang dikemukakan Abraham Maslow berdasarkan hirarki kebutuhan, seperti kebutuhan fisiologis, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri. Namun, hari ini aktualisasi diri menduduki kebutuhan utama bagi seluruh kehidupan kita.
Kita, misalnya, cenderung mengutamakan membeli iPhone agar terlihat menarik dibandingkan dengan membeli kebutuhan pangan yang membuat kita kenyang. Hari ini kita lebih bersyukur karena follower Twitter bertambah dibandingkan dengan sarapan pagi-pagi dengan penuh nikmat bersama keluarga.
Padahal kebahagiaan semacam ini sifatnya semu, hanya berdasarkan pada titik keinginan dalam mode kebanyakan masyarakat modern. Rasanya adalah kebahagiaan luar biasa jika ada yang bertanya, “Berapa followers Instagrammu?”, lalu dengan bangga kita menjawab dengan atribut centang biru. Aktualisasi semacam ini kian menduduki hirarki pertama dalam tatanan kehidupan masyarakat modern.
Selain itu, muncul laku konsumerisme yang berdampak terhadap perubahan tatanan simbolik struktur makna, dan perilaku sehari-hari. Contoh dalam kehidupan kita, yakni saat ini sapu tangan sudah tidak digunakan lagi berkat keberadaan tisu.
Pada tatanan simbolik, tisu menawarkan kemodernan yang senantiasa diidentikkan dengan kemutakhiran. Dengan memakai tisu, seseorang akan merasa dirinya tampak lebih modern daripada memakai sapu tangan. Padahal kegunaan tisu bisa menghemat pengeluaraan, nilai guna sapu tangan tentu sangat berbeda dengan tisu.
Kondisi ini menyebabkan kebutuhan yang tiada henti, instan culture tercipta di tengah-tengah masyarakat modern yang lebih menyukai sesuatu yang instan daripada menggunakan barang yang bisa dipakai berulang-ulang. Akibatnya manusia modern merasa teralienasi dari dirinya sendiri.
Erich Fromm melihat perbedaan luar biasa yang dilakukan manusia modern yang cenderung teralienasi dari dirinya sendiri. Bagi Fromm sendiri, manusia modern malahan akan merasa teralienasi dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan lingkungannya.
Teralienasi dengan dirinya sendiri manakala manusia berorientasi reseptif, eksploitatif, penimbun, dan orientasi pemasaran. Orientasi pemasaran ini bisa kita lihat dari relasi individu dengan individu lain cenderung berlomba-lomba menjadi sukses. Manusia berlomba agar dirinya selalu dibutuhkan, hingga akhirnya hubungan dengan manusia lainnya menjadi semu, perasaannya diliputi oleh ketakutan gagal dan kesendirian.
Orientasi reseptif kini menjadi bagian dari masyarakat, di mana suatu kelompok masyarakat menganggap memiliki hak untuk memeras orang lain. Orang yang diperas menganggap bahwa kelompok yang menindas adalah tuannya.
Orientasi eksploitatif terjadi ketika manusia dalam segala aktivitasnya ingin merampas hak orang lain, baik secara paksa maupn dengan tipu daya. Seperti tampak pada sistem yang otoriter, ingin menguras sumber daya manusia, hak orang lain yang mereka serbu.
Orientasi penimbun berupa bentuk tidak mempercayai apa pun yang baru dari dunia luar. Bagi manusia semacam ini, keintiman ia anggap sebagai ancaman, sehingga bersikap mengambil jarak dengan orang lain.
Kalau sudah begini, tidak salah ketika kita selalu berambisi untuk lebih daripada orang lain dalam hal apa pun. Kita akan merasa mumet jika teman, tetangga, atau bahkan orang terdekat kita memiliki pencapaian yang luar biasa. Lalu menyalahkan diri sendiri yang masih stagnan dengan kehidupan yang tetap saja begitu.
Padahal, nyatanya banyak hal yang tidak perlu kita pikirkan. Masih banyak hal yang tidak perlu kita apa-apain, termasuk tetap menikmati kehidupan dengan selow versi kita masing-masing.
Termasuk bersikap biasa aja atas pencapaian orang lain yang jauh melambung dibandingkan dengan kita sendiri. Parahnya kalau kita malah menyalahkan diri sendiri atas ketidakmampuan diri yang tidak sama dengan orang lain. Padahal, masing-masing individu memiliki waktu produktif dan pencapaiannya masing-masing.
Manusia tidak akan teralienasi dari dirinya sendiri ketika ia mampu produktif. Keproduktifan ini digambarkan dengan kemampuan untuk mengekspresikan segala bentuk daya dan upaya yang dimiliki. Tak pernah ada kata kesepian jika kita mampu mengekspresikan waktu pada hal yang bisa membuat diri sendiri berkembang, baik secara pengetahuan ataupun finansial.
Nyatanya bahagia itu sesederhana ketika kita ikhlas menarik tiga senti saja untuk tersenyum. Sedih, senang, penderitaan, dan kebahagian adalah bagian dari hidup kita. Tidak ada fase sedih yang abadi, pun sebaliknya. Tidak ada kesenangan yang abadi, makanya dalam menghadapi apa pun kita harus merasa biasa saja, tanpa sikap berlebihan terhadap sesuatu.
Kembali pada prinsip penderitaan yang dikemukakan oleh Ki Ageng Suryamentaram, "Tiap-tiap keinginan yang tercapai, maka akan pindah dengan keinginan yang lain". Pun kalau ada keinginan yang tidak tercapai, maka selowlah menjalani hidup.
Bagi saya, selow yang dimaksud bukan penuh dengan kesyukuran tanpa ada usaha. Lebih dari itu, selow yang saya maksud ketika kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, sesuatu yang dianugerahkan oleh Allah tanpa merasa galau atas keadaan yang dihadapi. Sebab galau yang semacam ini justru membuat kita ragu bahwa Allah Maha Kasih kepada hamba-Nya.
Keinginan yang tidak terpenuhi bukanlah akhir dari segala kehidupan kita. Itulah bentuk keniscayaan kuasa Allah terhadap hamba-Nya.
Category : kolom
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan
- Buku Ngaji Pascakolonial