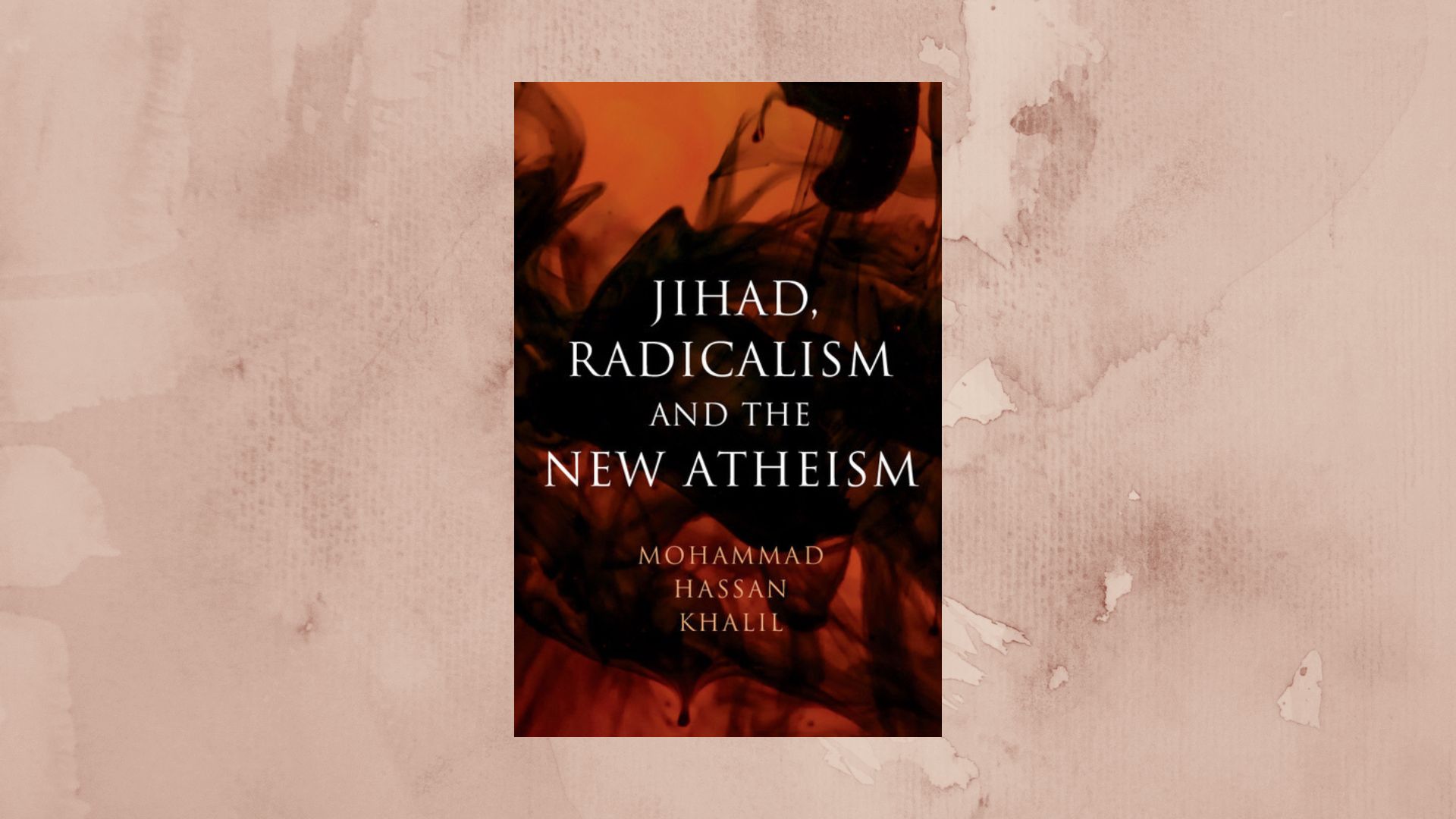Problema New Ateis dan Kubu Jihadis dalam Memahami Islam
Judul: Jihad, Radicalism, and the New Atheism | Penulis: Mohammad Hassan Khalil | Penerbit Cambridge University Press, 2018 | Tebal: x + 195 halaman | ISBN: 978-1-108-42154-6
“Apa benar agama mengajarkan perang dan tidak mengajarkan perdamaian?” Pertanyaan ini selalu mencuat bilamana terjadi terorisme atas nama agama. Biasanya akan juga muncul jawaban pembelaan seperti, “Tidak ada satu pun agama di dunia ini yang mengajarkan kekerasan”. Respons itu merupakan jawaban penenang untuk menghindari kemungkinan labelisasi agama tertentu sebagai agama yang melanggengkan kekerasan.
Pendapat yang menilai agama mengajarkan perdamaian boleh jadi pandangan yang tidak sepenuhnya benar. Begitupun pendapat yang menganggap agama mengajarkan kekerasan tidak juga dapat disebut salah. Pasalnya beberapa tindakan terorisme atas nama agama juga masif ditemukan, termasuk penyangkalannya berdasarkan agama juga marak berserakan. Singkatnya, membayangkan agama tanpa kekerasan seperti halnya mengandaikan kehidupan tanpa kekerasan. Padahal bila mau jujur, tidak ada satu pun agama yang terlepas dari kekerasan. Semua pernah terlibat, sebagaimana dikatakan Karen Amstrong dalam buku Fields of Blood: Religion and the History of Violence (2015).
Untuk menelaah lebih lanjut bagaimana logika keagamaan ini menyusup pada sejumlah pelaku teror dengan latar agama yang bermacam-macam seperti Islam, Kristen, Sikh, dan Yahudi bisa dilihat dalam karya Mark Jurgenmeyer yang bertajuk Teror in The Mind of God (2000).
Mohammad Hassan Khalil yang merupakan seorang Profesor Religious Studies dari Universitas Michigan, hadir dengan bukunya yang berjudul Jihad, Radicalism, and the New Atheism (2018) meneropong bagaimana konsepsi jihad. Keunikan karya Khalil adalah berfokus pada dua argumen dari golongan yang seolah saling bertolak belakang dalam menilai Islam.
Pertama, mereka yang mendukung, memperbolehkan, menginginkan, bahkan memerlukan jihad dan kekerasan sebagai bagian dari ajaran Islam. Kedua, apa yang disebut Khalil sebagai ‘new atheists/ateis baru’ yang memandang Islam sebagai agama yang pada dasarnya memang mengandung dan mengajarkan kekerasan.
Buku ini terdiri dari tiga bab. Bab pertama, berfokus pada bagaimana doktrin perang dan perdamaian dalam teks-teks primer Islam dan mengulik serba-serbi jihad dalam literartur-literatur keislaman dari masa ke masa.
Bab kedua, menyorot pada kekerasan kaum radikalis, khususnya mengacu pada peristiwa Selasa kelabu 11/9 dan tindak-tanduk terorisme ISIS, serta pandangan-pandangan pemikir muslim kontemporer, baik yang mendukung maupun yang mengecamnya.
Bab ketiga, berisi tentang bagaimana argumen-argumen golongan ‘ateis baru’. Mulai dari Sam Harris, Ayaan Hirsi Ali, yang menjadi sub bagian masing-masing, lalu diikuti Richard Dawkins, Christopher Hitchens, dan Daniel Dennett yang menjadi sub bagian tersendiri yang memiliki kesamaan visi dengan mengandaikan kehidupan tanpa agama.
Meskipun buku ini terdiri dari tiga bab, tetap saja secara esensial buku ini dibagi menjadi dua bagian; Pertama, mengkaji argumen-argumen yang dibuat oleh ‘kaum Jihadis’ untuk membenarkan kekerasan. Titik pijaknya berangkat Serangan WTC yang diotaki oleh Osamah Bin Laden dan al-Baghdadi dari ISIS.
Kedua, argumen-argumen yang dibangun oleh ‘kaum ateis baru’ yang menilai Islam sebagai agama kekerasan. Dalam hal ini, pemikir-pemikir kuncinya seperti nama-nama yang disebut di atas. Kesemua nama-nama yang dikaji dalam barisan ini merupakan pemikir kunci yang memiliki karya yang hampir kesemuanya laku keras di pasaran (best-seller). Tidak mengherankan bila ‘kubu ateis baru’ memiliki pengaruh besar dan pengikut setia yang siap sedia dalam menengadah setiap gagasan yang lahir dari mereka.
Dengan kata lain, baik kubu ‘jihadis-radikalis’ dan ‘ateis baru’ tampak berseberangan, tetapi memiliki kesamaan sekaligus, yakni sama-sama ekstrem dalam memahami doktrin-doktrin Islam. Juga sama-sama mengedepankan ayat-ayat yang dibutuhkan sesuai kepentingan untuk mendukung pembacaannya melalui tesis-tesis yang digunakan, termasuk pemahaman terhadap Islam dan politik. Secara tidak langsung keduanya sama-sama tekstualis. Kelompok ini acapkali mengabaikan konteks dan tidak peduli terhadap pemahaman alternatif yang digunakan umat Islam kebanyakan secara moderat.
Membayangkan Dunia Tanpa Agama
Sam Harris dengan bukunya The End of Faith: Religion, Terror, and the Future of Reason (2004), Letter to a Christian Nation (2006), The Moral Landscape: How Science Can Determine Human Values (2010), Lying (2011), Free Will (2012), Waking Up: A Guide to Spirituality Without Religion (2014), The Future of Tolerance: A Dialogue (2015); Ayaan Hirsi Ali dengan militansi dan karyanya Heretic (2015), Infidel (2007), Nomad: A Personal Journey Through the Clash of Civilizations (2010); Richard Dawkins melalui The God Delusion (2006); Daniel C. Dennett dengan karyanya Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (2006); dan terakhir Christopher Hitchens melalui bukunya God is not Great: How Religion Poisons Everything (2007).
Karya-karya di atas secara umum hendak mendemonstrasikan betapa Islam merupakan agama yang kerap dekat dengan kekerasan dan doktrin jihad merupakan salah satu ajaran penting yang tidak terpisahkan di dalamnya serta menjadi ciri khas Islam. Sebab hanya pengaruh agama yang bisa melakukan itu semua. Dawkins dengan tegas menyalahkan agama sebagai biang kekerasan. Konsep kehidupan setelah kematian memicu orang-orang Islam berbondong-bondong menjadi martir. Makanya, ia sangat vokal mengandaikan dunia tanpa agama rasa-rasanya akan lebih aman dan damai.
Bahkan Sam Harris memiliki kesimpulan yang cukup mirip, bahwa kelompok yang disebut “ekstremis” berusaha menerapkan apa yang bisa dibilang sebagai pemahaman paling jujur terhadap doktrin agama yang sebenarnya (p. 123). Harris menyebut orang yang mendeklarasikan dirinya sebagai kubu moderat sebagai orang yang “berpura-pura” dan “ketidakjujuran intelektual” atas keyakinan yang dianut (p. 127).
Rujukan-rujukan yang digunakan pun terkesan tendensius, bahkan terkesan sepihak, sehingga yang terjadi adalah suguhan mono-perspektif. Misalnya seperti yang digunakan Hirsi Ali mengutip ayat-ayat perang dari terjemahan Alquran seorang akademisi muslim tersohor, Abdullah Yusuf Ali (w. 1953) dalam karyanya. Namun ia menukilnya secara terpisah tanpa melihat ayat-ayat di sekitarnya, begitupun juga konteksnya. Padahal Yusuf Ali memberikan informasi latar belakang dari ayat tersebut (p. 142).
Alhasil ayat-ayat perang yang memiliki konteks tersendiri luput dari tesmak Hirsi Ali. Ayat-ayat kekerasan yang dikutip secara luas tidak dipahami sebagai rujukan terhadap musuh-musuh tertentu yang represif dan suka berperang, bukan terhadap warga sipil yang tidak bersalah.
Hitchens juga sama, selain tulisan bombastis dan begitu provokatif, ia juga merujuk pada karya favorit terkait Islam dari Ibn Warraq berjudul Why I Am Not Muslim. Tidak mengherankan jika ia juga menampilkan Islam secara monolitik, menilai Islam sebagai agama yang eksklusif dan didorong oleh penaklukan (p. 161).
Terdapat hal unik dari Hitchens saat berdiskusi dengan Rabbi David Wolpe terkait eksistensi Tuhan dan menilai bahwa Islam merupakan agama yang paling beracun. Bahkan ia pernah berdebat dengan seorang cendekiawan muslim tersohor di dunia Barat, Tariq Ramadan terkait “Apakah Islam adalah agama damai?”. Kemudian Hitchens sepakat dengan Tariq soal kekerasan dan intoleransi umat Islam, yakni masalahnya bukan terletak pada kitab suci, tetapi pada pembacanya. Namun yang sangat disayangkan Hitchens adalah mengapa harus ada doktrin mengenai hadiah surga bagi para martir” (p. 162).
Memang benar kesemua pemikir ateis baru itu mengutip ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis nabi untuk mendukung statemen mereka. Tetapi Khalil menggarisbawahi bahwa mereka gagal dalam melihat sikap politis yang dilakukan para pelaku bom bunuh diri tersebut. Mereka gagal memahami hal ini lantaran terfokus pada tindakan yang dituduh terinspirasi dalam Al-Qur’an, bukan mengulik mengapa mereka melakukan hal tragis yang demikian?
Betapa pun pembawaan Khalil begitu ciamik dalam menyajikan setiap argumen dan data-data penyokong. Buku ini memiliki tantangan tersendiri bahwa semua hal ini tidaklah mengejutkan dan wah, sebab kekerasan yang dilakukan orang-orang radikal telah jamak diketahui oleh orang-orang, bahwa mereka ini bukanlah dari golongan Islam arus utama. Khususnya bagi sarjana studi Islam, atau mereka yang memang dekat dengan wacana perdebatan, argumen-argumen yang terpasang pun tidak banyak hal-hal baru.
Meski demikian, tetap saja apa yang disajikan Khalil merupakan kajian penting, sebab yang menjadikannya unik dan baru adalah memberikan perbandingan dua kubu di atas. Memberikan klaim yang sama atas golongan ateis baru dan kubu jihadis-radikalis dalam memahami peran agama dalam kekerasan.
Sederet nama ateis baru yang dipaparkan Khalil merupakan pemikir cum akademisi moncer yang diakui publik luas dalam bidangnya masing-masing (di luar Studi Islam). Hanya saja ketika mereka berbicara mengenai Islam dan jihad acap kali menggunakan cara yang seringkali tidak akurat, sepotong-sepotong, dan tidak lengkap. Sebagian dipicu metodologi yang digunakan, karena mereka sangat bergantung pada sumber-sumber rujukan yang gagal memberikan spektrum pandangan yang representatif (p. 167).
Buku Khalil ini tetap menjadi penting untuk dibaca sebagai bentuk refleksi atas pemahaman dua kubu yang seolah berseberangan tetapi segaris dalam cara yang sama, yakni sama-sama ekstrem dan brutal dalam memahami Islam. Keduanya secara setengah-setengah berdasar kepentingan masing-masing dalam menggunakan ayat-ayat. Sebagai pembaca dapat menangkap pola-pola argumen yang ditawarkan kedua kelompok ini secara khusus, dan memahami peta konsep jihad dan radikalisme secara umum.
Category : resensi
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan
- Buku Ngaji Pascakolonial
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-8 Desember 2024