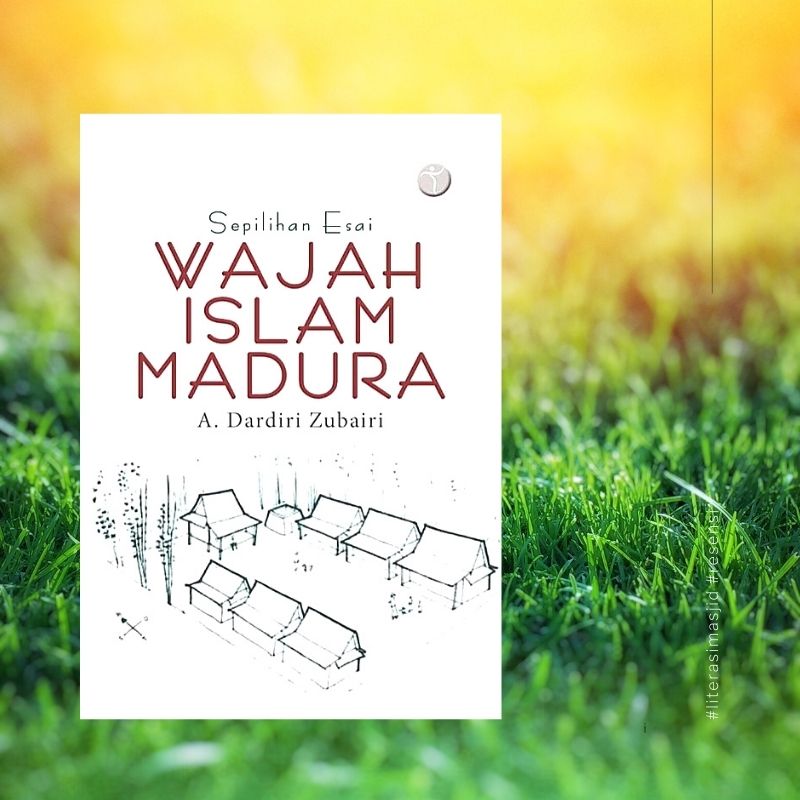Potret Orang Muslim Madura
Judul: Wajah Islam Madura | Penulis: A. Dardiri Zubairi | Penerbit: Tarebooks, 2020 | Tebal: xii + 140 halama | ISBN: 978-602-5819-74-2
Sejauh ini, pengklasifikasian Wajah Islam Madura melalui tesmak A. Dardiri Zubairi terajah menjadi tiga pilar pokok yang saling berkelindan antara ritus Islam orang Madura beserta dekadensi budaya yang berjalan beriringan di dalamnya.
Hal yang paling prima, bagaimana sikap hidup orang Madura berkomunikasi dengan Tuhannya. Hal yang kedua, bagaimana orang Madura berinteraksi dengan sesamanya. Dan hal yang terakhir, bagaimana orang Madura menempatkan buana sebagai cagar alam yang menopang kehidupannya.
Tentu tiga pilar utama tersebut tidak terlepas dari riwayat masuknya Islam ke Madura kali pertama pada 1330-an. Islam dikenalkan pertama bermula dari Sumenep, tepatnya di sebuah pulau yang bernama Sepudi.
Pada awal tadbir Pangeran Joharsari (1319-1331), datang seorang mubalig yang berdakwah di Sumenep. Ia sendiri seorang wali, adik dari Sunan Ampel yang bernama Sayyid Ali Murtadha, atau dikenal dengan sebutan Sunan Lembayung. Di Pulau Sepudi pula Sunan Lembayung mendirikan pesantren yang menjadikan Islam semakin menyebar sampai ke Madura paling barat (Bangkalan).
Huub de Jonge (1995) menyebut bahwa etnik Madura sebagai pemeluk agama yang ortodok. Hal ini sejalan dengan interpretasi pada sub bab mukadimah yang menyatakan, “Jika berbicara tentang Madura, ya berarti berbicara tentang Islam”.
Melepaskan Madura dari Islam ibarat melepas asin dari air laut. Penganalogian Islam bukan semata agama mayoritas yang dipeluk oleh orang Madura, akan tetapi sudah menjadi identitas kemaduraan. Pulau Madura ya Islam.
Sebagai penyebutan untuk Aceh masyhur disebut sebagai Serambi Makkah, sedangkan Madura acapkali disebut sebagai Serambi Madinah. Pemberian identitas tersebut bukan tanpa asas. Madura sendiri mempunyai tiga institusi penting dalam merawat sikap hidup manusia terhadap Sang Pencipta yang sampai hari ini masih terus lestari.
Tiga institusi penting yang sejauh ini menggawangi bumi Madura yang pertama adalah langgar atau surau. Keberadaan langgar yang sangat mudat dapat ditemukan digunakan sebagai tempat untuk belajar ilmu Al-Qur’an. Tempat yang kedua yakni madrasah, untuk menerima dan belajar perihal ilmu agama. Terakhir, ada pondok pesantren, tempat dimana anak ditempa untuk belajar agama Islam secara menyeluruh.
Sikap hidup orang Madura terhadap Tuhan juga dinegasikan melalui frase “Rizkina Pangeran ta’ kera taporop” (Rezeki dari Tuhan tidak akan tertukar).
Penggambaran sikap hidup orang Madura tersebut setidaknya dapat penulis lihat—sekadar sebagai ejawantah—dari seorang penjual rengginang di Desa Prenduen, Sumenep.
Banyak saingan bukan menjadi alasan untuk tidak berjualan. Justru saingan merupakan ladang melatih kesabaran. Bila jualan laku berarti sudah rezekinya, dan bila jualan orang lain yang laku, di situlah sabar harus diletakkan.
Mungkin ada yang memaknai ungkapan tersebut sebagai sikap yang fatalistik. Menyerah pada nasib, atau ungkapan sekadar untuk menenangkan diri dalam kompetisi hidup yang kian sengit. Bagi A. Dardiri Zubairi ungkapan tersebut memiliki nilai dan makna filosofis yang begitu dalam. Setidaknya tercatat dalam beberapa hal berikut.
Pertama, sebagai wujud dari keyakinan bahwa yang mengatur rezeki adalah Allah Swt, bukan manusia. Kedua, berusaha dan bekerja butuh ketegaran (kesuksesan tidak ada yang instan). Ketiga, sebagai manusia kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Keempat, hindari menganggap orang lain sebagai perampas rezeki kita. Hal ini dimaksudkan untuk terhindar dari sifat iri dan dengki (hlm. 45).
Sikap hidup sebagai muslim yang terelasi dalam kehidupan di tengah masyarakat, tergambarkan seperti praktik ibadah haji ke Tanah Suci. Jutaan orang berpakaian serba putih. Presiden, pejabat negara, menteri, pemilik perusahaan, petani, buruh, dan pedagang semua sama. Tidak ada perbedaan. Sama-sama dibalut dengan kain putih, persis kain murni yang dijadikan pembungkus orang meninggal. Semua status, entah kekuasaan maupun kekayaan menjadi tidak penting. Hilang. Terlucuti.
Penyamarataan baju yang dipakai ketika melaksanakan ibadah haji sebagai cara Allah untuk mengajari umat muslim agar kita semua menjadi orang terhormat tanpa embel-embel status. Semua sama dihadapan-Nya.
Cuma satu yang membedakan, yakni amal apa yang telah kita torehkan ketika masih hidup di bentala raya. Selayaknya sikap sombong bukan bagian dari identitas kaum muslim. Apa yang mau disombongkan? Kemewahan? Adikara? Itu semua sama sekali tidak ada artinya di mata Allah Swt.
Penghormatan kepada bhâpa’, bhâbu’, ghuru, rato (bapak, ibu, guru, pemimpin) menempati urutan wahid dalam seseorang berperilaku. Menghormati kedua orang tua merupakan darma yang harus direalisasikan oleh setiap orang Madura. Sebagaimana Islam telah melantangkan bahwa surganya anak terletak pada pengestu kedua orang tuanya.
Seorang guru juga dijunjung tinggi keberadaannya setelah menghormati kedua orang tua. Peranan guru sebagai talang ilmu merupakan entitas vital yang tidak bisa dipisahkan dari orang Madura. Tatanan ketiga ada seorang pemimpin yang juga tak luput dari keharusan dipatuhi dan dihormati dalam budaya Islam di Madura.
Allah sebagai sandaran mengantarkan umat Muslim di Madura pada prinsip hidup padâ ta’ nanto (tidak ada yang tahu). Agama sebagai sandaran hidup direalisasikan melalui peribahasa abântal syahâdât, asapo’ iman (berbantal syahadat, berselimut iman). Agama tak ubahnya tumpuan, tidak boleh lepas. Bila diabaikan, ketidakseimbangan hidup, bahkan guncangan, akan segera hadir. Semakin jauh orang dari agamanya, semakin jauh pula orang tersebut dari Tuhannya (hlm. 47).
Gatra religiousitas juga tergambar pada kearifan lokal berupa keharusan bisa mengaji. Para orang tua di Madura akan sangat bera bilamana buah hatinya tidak bisa mengaji. Mengaji merupakan suatu keharusan yang sejak dini sudah ditanamkan kepada anak. Orang yang tidak dapat mengaji disebut dengan ta’ tao ka battona langgâr (tidak tahu pada pinggirnya langgar, tempat mengaji).
Selain itu, disebutkan juga bahwa orang Madura sangat karib dalam hal menjaga solidaritas kekeluargaan. Ada istilah pettong popo yang secara harfiah berarti bermakna tujuh pupu, yang maksudnya semasih ada tali persaudaraan, meski tujuh pupu sekalipun, orang Madura masih menganggapnya sebagai saudara dekat.
Laju agresi modernisasi yang masif telah banyak melunturkan kearifan lokal (local wisdom) yang sudah terpatri sejak lama pada kebudayaan Madura. Keresahan pada mata penghidupan orang Madura di antara agraria dan maritim kini pun mulai terasa. Seperti habisnya tuah tanah sangkol yang jatuh ke investor (lokal/asing) juga semakin memperburuk keadaan.
Akibatnya, terlahirlah budaya urban. Banyak orang Madura malah pergi ke kota besar, sementara tanahnya sendiri diberangus oleh kaum kapitalis yang siap melucuti tuah tanah sangkol sekaligus warisan budaya peninggalan para leluhur.
Ditilikan dalam bentuk esai di buku ini menarik untuk dilihat, lebih tepatnya melihat potret rupa gambar Islam (orang) Madura dengan segala kelebihan dan kekurangannya.
Category : resensi
SHARE THIS POST