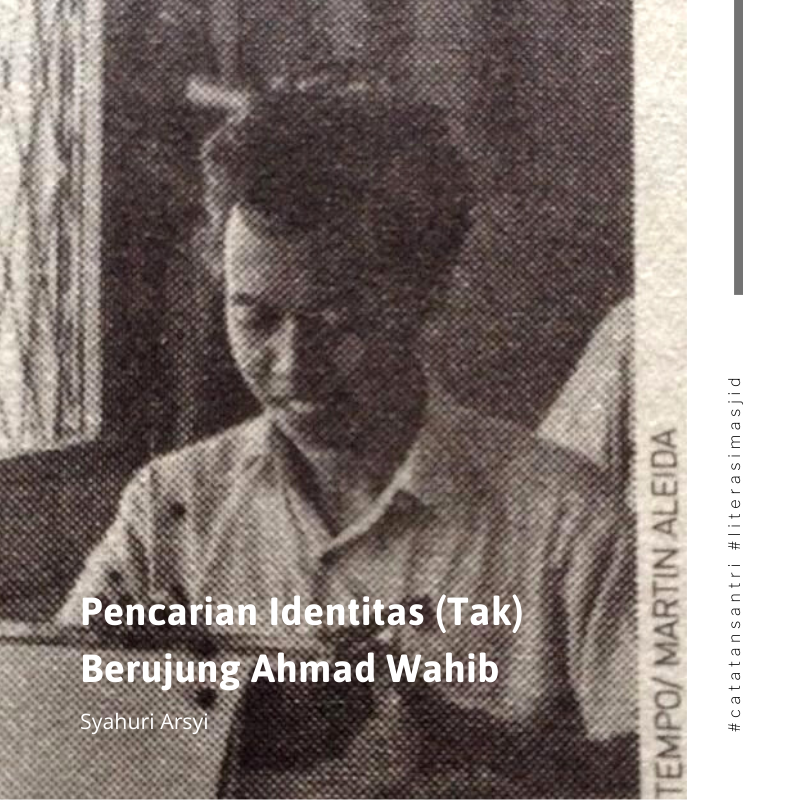Pencarian Identitas (Tak) Berujung Ahmad Wahib
Pada awalanya, perkenalan saya dengan pemikiran-pemikiran Ahmad Wahid melalui seorang teman beberapa tahun lalu—sekarang entah ada di mana. Perkenalan itu, tentu lewat buku saku kecil berjudul Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib, yang disunting oleh dua sahabatnya, Djohan Effendi dan Ismet Natsir, terbitan LP3ES, tahun 1981 dan diberi pengantar oleh A. Mukti Ali yang notabene adalah mantan Menteri Agama, sekaligus mentor di lingkaran diskusi Limited Group.
Saya masih ingat betul hingga kini, apa yang dikatakan teman saya ketika menyodorkan buku tersebut. Ia berkata “Sebagai mahasiswa Jurusan Pemikiran Islam dan Filsafat Islam, kamu harus membaca buku ini, rugi kalau tidak dibaca”, begitu katanya.
Di bilang rugi kalau tidak dibaca, akhirnya saya harus meminjam buku catatan harian Wahib tersebut. Namun, sayangnya saya cuma dikasih waktu sehari, karena teman saya ini ingin membaca juga hingga selesai. Bayangkan, waktu itu saya disuruh membaca dan melahap isi buku catatan Wahib, kalau tak salah tebalnya 428 halaman, hanya dalam waktu sehari. Tak selesainya pembacaan saya, pada berakhirnya berujung pada usaha pembelian di toko buku sebagai pustaka pribadi.
Ada kesan yang sangat mendalam ketika membaca pergolakan pemikiran Islam catatan harian tokoh kelahiran 09 November 1942 Sampang Madura ini, yang beberapa waktu lalu pada gelaran Ngaji Filsafat oleh Pak Fahruddin Faiz dimasukkan sebagai tokoh muda. Oleha karena itu, ketika mengambil mata kuliah Pemikiran Teologi Islam Modern di Indonesia, saya memberanikan diri untuk menulis pemikiran Ahmad Wahib. Namun, lagi-lagi saya harus kecewa, dosen yang mengampuh tak mengizinkan, “Biarlah pemikiran Ahmad Wahib seperti itu, tak perlu diperluas”, begitu katanya.
Hal senada dari Mukti Ali di dalam pengantar buku Pergolakan Pemikiran Islam. Kita simak, “Dalam perbicangan-perbincangan di lingkungan diskusi, memang almarhum Ahmad Wahib sering kali mengeluarkan pendapat-pendapat yang tidak biasa didengar oleh banyak orang. Terutama yang berkaitan dengan masalah-maslah agama. Kesan saya pada waktu itu, almarhum sedang menghadapi pergulatan pikiran yang keras dalam proses pencariannya”.
Setidaknya, kesan pertama yang saya tangkap saat itu hampir sama dengan kesan Mukti Ali. Saya langusng jatuh hati. Gagasan-gagasannya sangat memesona dan orisinal. Ide-ide Wahib sangat segar (bahkan hingga sekarang), dan tentu saja sangat bernas. Saya sangat suka meski tak sepenuhnya setuju dengan gagasannya. Namun, yang sangat tampak bagi saya, Wahib saat itu sedang menghadapi pergulatan pemikiran Islam yang sangat keras dalam proses pencarian identitas diri.
Pencarian identitas tersebut tampak begitu kuat dalam mendefinisikan Muslim melalui kalimat-kalimat yang sangat terkesan memiliki nuansa emosi. Kita simak pernyataan Wahib dalam catatanya tertanggal 09 Oktober 1969, “... Aku bukan nasionalis, bukan Katolik, bukan sosialis. Aku bukan Buddha, bukan Protestan, bukan westernis. Aku bukan komunis. Aku bukan humanis. Aku adalah semuanya. Mudah-mudahan inilah yang disebut Muslim.”
Catatan lain Wahib tentang pencarian identitas juga tergambar dalam catatan pada 1 Desember 1969, “Aku bukan Hatta, bukan Soekarno, buka Sjahrir, bukan Natsir, bukan Marx dan bukan pula yang lain-lain. Bahkan... aku bukan Wahib. Aku adalah me-Wahib. Aku mencari dan terus-menerus mencari, menuju dan menjadi Wahib. Ya, aku bukan aku. Aku adalah meng-Aku, yang terus berproses menjadi aku. Aku adalah aku, pada saat sakaratul maut.”
Pencarian indentitas diri bagi Wahib melalui proses bertanya, termasuk dalam hal agama, bahkan Tuhan sekalipun, adalah bagian dari proses menjadi Muslim, dan kalau berhenti bertanya, maka ia berhenti menjadi Muslim. Dalam catatannya tertanggal 28 Maret 1969 ia menyatakan, “Aku belum tahu apakah Islam itu sebenarnya. Aku baru tahu Islam itu menurut Hamka, Islam menurut Natsir, Islan menurut Abduh, Islam menurut ulama-ulama kuno, Islam menurut Djohan, Islam menurut Subki, Islam menurut yang lain-lain dan terus terang aku tidak puas. Yang kucari belum ketemu, dan belum terdapat yaitu Islam menurut Allah, pembuatnya.”
Anyaman bahasa yang digunakan Wahib penuh dengan letupan-letupan protes di dalam lembar demi lembar catatan hariannya. Siapa pun yang membaca pergolakan pemikiran Wahib akan mudah terseret dalam arus pergulatan pemikiran yang mengelisahkan. Bahkan mungkin ada ketidakterimaan bahwa gagasan-gagasan itu lahir dari tempurung anak Sampang, Madura yang sudah terlanjur terkenal dengan sate, potong rambut dan caroknya.
Bagi saya, letupan-letupan kalimat yang dilontarkan, Wahib “seakan-akan” mau melepaskan baju identitas diri yang sudah melekat pada dirinya. Identitas ini oleh Wahib lebih banyak dicurahkan terhadap pluralitas, dialog antariman, dan penolakan yang sangat tegas atas bentuk absolustisme, fanatisme, dan tafsir tunggul terhadap pemahaman agama.
Identitas diri telah yang dibangun Wahib sebagai mahasiswa dalam jajaran tertinggi para pemimpin HMI, sekaligus penggerak lingkar diskusi Limited Group, tak sejalan dengan kondisi generasi mahasiswa milenial yang abai dan terlalu dimanjakan dengan jargon dan istilah Agent of Change. Menurut Pak Faiz, generasi milenial saat ini bukan sebagai pencari ilmu, akan tetapi sebagai penerima ilmu.
Fakta ini sesuai dengan kondisi generasi milenial yang tak mau lagi repot-repot “berkeringat”, bersusah-payah datang dan mencari guru. Cukup hanya dengan menjentikkan jari di gawai layar smartphone, komputer jinjing, kita bisa mendengarkan ceramah-ceramah dan kisah keagamaan secara virtual.
Bagi saya, mengenal Wahib melalui catatan harianya adalah teriakan semesta hampa dalam pencarian indentitas tak berujung sebagai seorang pencari yang serius untuk membangun jembatan dari kejumudan diri. Maka pantas saja Greg Barton dalam Gagasan Islam Liberal di Indonesia (1999), memasukkan nama Ahmad Wahib sejajar dengan Abdurrahman Wahib, Djohan Effendi, dan Nurcholis Madjid sebagai cendekiawan yang memberikan sumbangsih atas gerakan pembaruan pemikiran Islam Neo-Modernisme Islam di Indonesia.
Kita sebagai generasi milenial perlu mambaca ulang pergolakan pemikiran Islam Ahmad Wahib yang dirasa sudah mulai pudar, cenderung membeku, diam bahkan cederung statis. Melalui pergolakan pemikiran Islam catatan harian Wahib ini, kita bisa belajar banyak mulai dari isu-isu sekularisme, liberalisme, kapitalisme, pluarlisme, kebebasan beragama hingga kegagalan kisah cinta Ahmad Wahib. Begitu.
Category : catatan santri
SHARE THIS POST