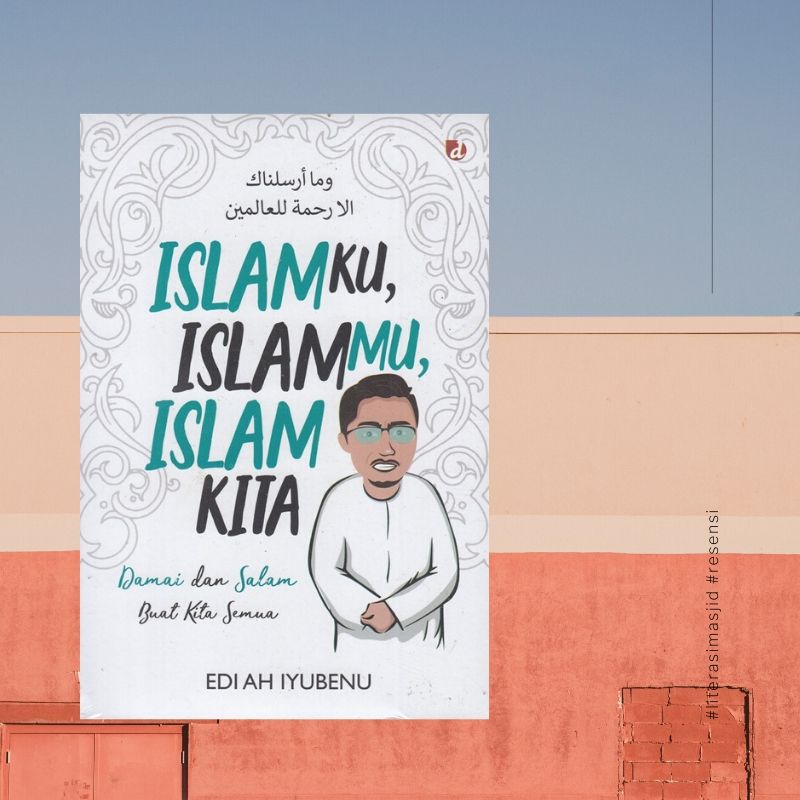Menjadi Muslim yang Tahu Diri
Judul: Islamku, Islammu, Islam Kita | Penulis: Edi AH Iyubenu | Penerbit: Diva Press, 2018 | Tebal: 196 halaman | ISBN: 978-602-391-667-2
Ribut-ribut soal agama rasanya setiap hari dapat kita saksikan. Semua jenis media sosial, baik Facebook, Instagram, Twitter, yang sewajarnya digunakan untuk menyambung pertemanan dan penghiburan justru menjadi tempat membiaknya perselisihan atas nama agama. Belum lagi jika teman-teman kita yang sebelumnya akur-akur saja kini membawa bahasan tentang keributan itu di dunia nyata. Tadinya ngobrol-guyon asik-asik aja, kini menjadi tidak begitu lagi, suasana santai menjadi kaku mendadak.
Masalahnya jika ribut-ribut terus dibiarkan, lama-lama akan dianggap biasa dan wajar-wajar saja. Padahal sungguh tak sehat. Dampaknya kita sudah lihat bersama, bahwa kehidupan sosial kita semakin tidak akur.
Apa sebenarnya yang menyebabkan praktik beragama justru menimbulkan konflik? Apa sebenarnya yang menyebabkan umat beragama kesulitan mengedepankan ukhuwah di antara perbedaan yang merupakan sunatullah? Benarkah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan sebagian umat Islam yang menyebut bahwa yang salah bukan agamanya tapi soal pengejawantahan ajaran-ajarannya?
Persoalan-persoalan itulah yang dibabar oleh Edi AH Iyubenu dalam buku Islamku, Islammu, Islam Kita (2018). Menurut yang dapat saya simpulkan atas pembacaan buku tersebut, penyebab perselisihan atas nama agama ini adalah pemahaman ajaran agama masyarakat hari ini tidak mendalam namun sudah merasa paling agamis.
Salah satu contoh perilaku yang dikritik dalam buku ini adalah lantangnya seruan “kembali pada Al-Quran dan Sunah”. Rasanya ajakan tersebut memang patut dikritisi. Misalnya dengan mempertanyakan apakah sebenarnya yang dimaksud para penyeru ini tentang kembali pada Al-Quran dan Sunah? Bila yang dimaksud adalah menerjemahkan secara literal kata per kata tanpa ditunjang penjabaran dari kitab-kitab pendukung (tafsir, dan sebagainya) tentu itu justru bukan sebenar ajakan kembali pada Al-Quran dan Sunah. Mengingat saat ini kita hidup beratus-ratus tahun setelah masa kenabian maka dibutuhkan perangkat penyambung Sunah Nabi Saw yang tak lain adalah ulama beserta kitab-kitabnya.
Hal ini sejalan dengan penelitian dari Pew Research Center yang dipublikasikan jurnal Nature. Penelitian itu menyebut bahwa orang yang tingkat wawasannya lebih sedikit justru lebih ngotot. Mereka ini mengidap illusion of knowledge (ilusi pengetahuan) sehingga meyakini seyakin-yakinnya suatu pendapat sampai-sampai merasa punya kapasitas untuk menentang mereka yang lebih berkompeten, pakar serta mumpuni secara keilmuan.
Setiap ayat dalam Al-Quran maupun hadis, memiliki konteks yang perlu dipahami sebelum kita bergerak mempraktikkannya. Tanpa dibarengi usaha mempelajari agama dengan keseriusan menelusuri sumber-sumber utama yang bukan terjemahan, yang terjadi adalah ngebet mempraktikkan mentah-mentah setiap ayat tanpa memerhatikan konteks.
Ada banyak kata-kata perintah dalam Al-Quran yang justru dapat membahayakan jika dipraktikkan tanpa pemahaman, misalnya jihad yang diartikan satu-satu sebagai perintah perang, fadhribu yang diartikan memukul istri, libasun (pakaian), dan sebagainya. Mari kita urai salah satunya, kita ambil contoh kata yang terakhir. Kata libasun terdapat dalam surah Al-Baqarah (2): 187 yang artinya, “Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami) dan kalian adalah pakaian bagi mereka”. Bila berlandaskan ilmu maka akan diperoleh pemaknaan bahwa hubungan suami-istri layaknya fungsi pakaian yaitu melindungi, memperindah, serta memuliakan, sehingga ayat ini bukanlah suatu hujah (tanda; bukti; alasan) untuk ‘memakai’ istri sekehendak hati tanpa memberikan penghormatan kepadanya.
Kritik lainnya tentang praktik beragama juga disampaikan dalam buku ini yaitu belajar tanpa bimbingan langsung dari guru. Akibatnya, pemahaman agama yang utuh tidak didapat serta tak ada sosok yang menjadi teladan dalam keseharian. Dapat terjadi kemudian tidak bisa mengaplikasikan perintah agama secara bijaksana. Parahnya lagi, bermodal link, hasil mencari di internet, menyaksikan dari Youtube atau berusaha seadanya menerjemahan satu ayat atau hadis sudah berani ceramah ke mana-mana. Sikap tahu diri menjadi semakin jarang terlihat. Semangat mengemban dakwah itu tidak dibarengi dengan berbenah diri. Padahal, dakwah tanpa bekal keilmuan mumpuni bisa menjadi tindakan tidak menguntungkan yang akhirnya dapat mengguncang harmoni sosial.
Berhadap kepada orang-orang dengan pemahaman dan pengalaman hidup luaslah yang mampu memahami berbagai permasalahan masyarakat yang majemuk. Dengan begitu mereka dapat memberi tuturan-tuturan adem seputar anjuran Ilahi, bukannya sok menjadi Tuhan dengan memvonis segala macam persoalan, bahasan, dengan dan secara hitam-putih. Dakwah yang kasar hanya akan memicu perselisihan. Tapi serulah (dakwah) dengan kelembutan.
Berikut saya kutipkan pernyataan yang kiranya dapat memberi tamparan bagi kita yang masih dalam proses belajar, atau baru-baru belajar agama untuk tidak kemudian menjadi sok.
“…, mari mengertilah segera bahwa yang dikenakan (khitab) perintah mengamalkan dakwah adalah sebagian kita, bukan semua kita. Karena tidak semua dari kita punya kompetensi untuk mengembannya dengan baik. Pemangku dakwah mestinya adalah hanya para ulama, yaitu orang-orang yang alim (mumpuni ilmunya) dan saleh (mengamalkan ilmunya). Kalangan di luar kriteria tersebut, mestinya tahu diri saja untuk lebih bersibuk dengan berbenah diri.” (hlm. 72).
Masalah lain umat Islam hari ini yang tak kalah memicu ketegangan adalah menang-menangan dengan maksud menyeragamkan pemahaman. Perihal perbedaan pendapat sudah ada sejak beratus-ratus tahun lalu bahkan pada masa Nabi Muhammad Saw.
Ada beberapa kisah ikhtilaf yang dituturkan dalam buku ini. Salah satunya adalah obrolan Khalifah Al-Ma’mun dengan seseorang yang baru saja pindah agama dari Islam ke Nasrani dengan alasan terlalu banyak beda pandangan dalam Islam. Salah satu nukilan dari penjelasan sang khalifah adalah bahwasanya bermacam-macam pandangan itu sejatinya merupakan opsi sebagai bentuk kelonggaran agar umat tidak merasa terbebani atau kesulitan. Khalifah Al-Ma’mun tak lupa berpesan bahwa masing-masing tak boleh saling mencela dan memaki. Menurut penulis buku ini menyebut upaya penyeragaman itu sebagai wujud yang tak hanya menentang sunatullah tetapi juga melukai akhlak karimah Nabi Muhammad Saw.
Kita tahu, agama dapat mudah digunakan sebagai isu oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab untuk urusan, kepentingan apa saja. Kita telah menyaksikan beragam peristiwa membela agama yang digaungkan baik di mimbar media sosial hingga di mimbar khotbah yang sebenarnya hanyalah pemanfaatan untuk keuntungan kelangan atau kelompok tertentu demi perebutan kekuasaan politik. Semoga kita tidak terikut dalam arus ini.
Masih banyak kritik lain yang tertuang dalam buku ini, meliputi di antaranya tentang zikir, perihal bidah, prinsip hukum, hingga mazhab. Apresiasi yang tinggi patut dihaturkan untuk lahirnya buku ini yang bertutur refleksi dan kegelisahan yang diakui dikerjakan hanya dalam waktu dua belas hari, tentu dengan segala permenungan. Meskipun disampaikan secara ringan dan sederhana, namun tidak meninggalkan ihwal sebenarnya dari sesuatu; isi; pokok; inti bahasan berupa kritik atas praktik beragama kita dewasa ini.
Category : resensi
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan
- Buku Ngaji Pascakolonial