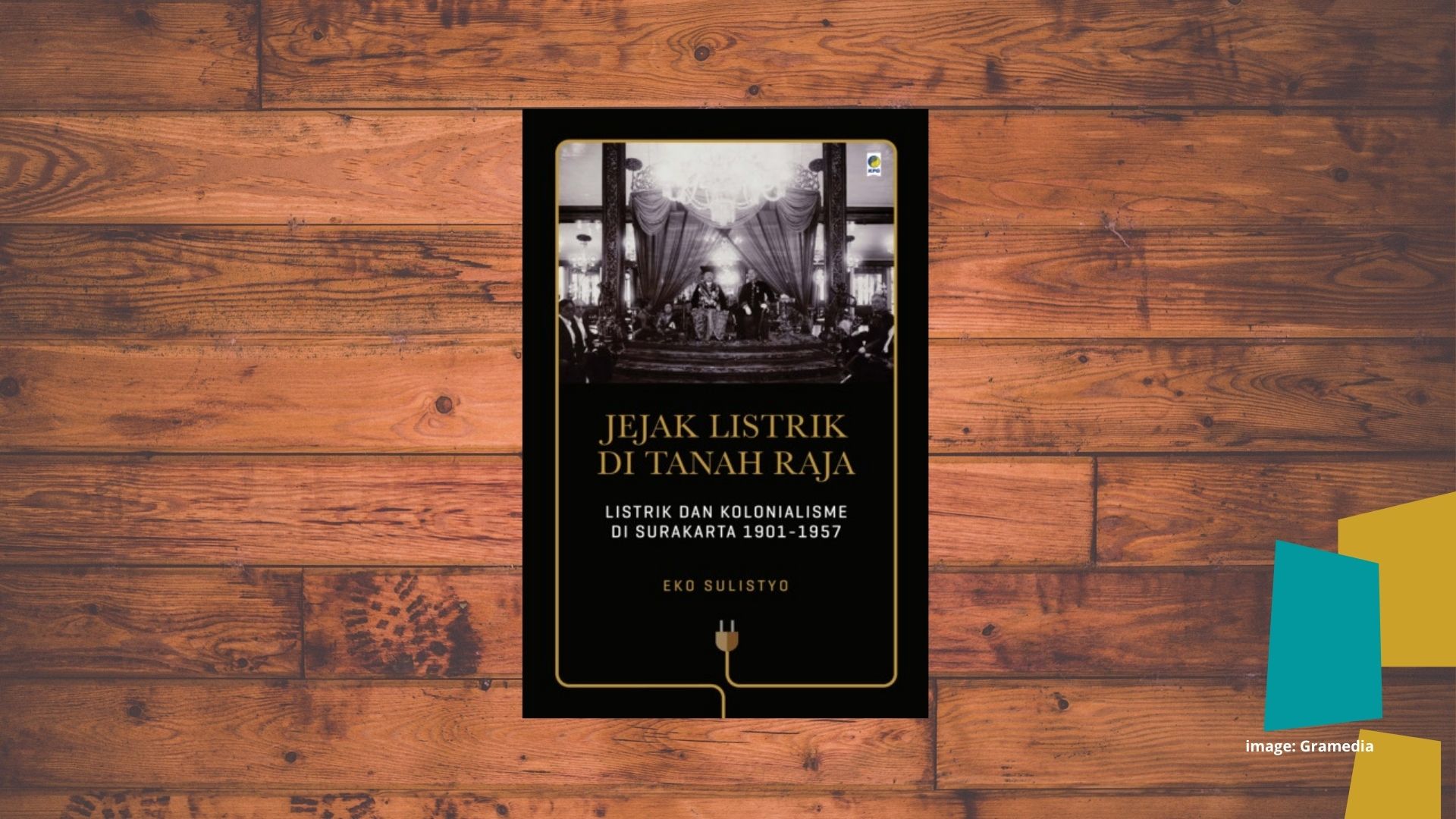Listrik Tempo Dulu
Judul Buku : Jejak Listrik di Tanah Raja: Listrik dan Kolonialisme di Surakarta 1901-1957 | Penulis: Eko Sulistiyo | Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia | Tahun Terbit : November 2021 | ISBN : 978-602-481-676-6 | Halaman : xviii + 278
Peminat studi sejarah patut menyambut dengan baik atas kehadiran buku Jejak Listrik di Tanah Raja: Listrik dan Kolonialisme di Surakarta 1901-1957 (2021) yang ditulis oleh Eko Sulistiyo, karena memperkaya historiografi di Indonesia, mengingat selama ini topik mengenai listrik jarang mendapat perhatian di kalangangan sejarawan. Padahal, sebagaimana ungkapan sejarawan Rudolf Mrazek yang dikutip oleh Eko Sulistiyo, bahwa kehadiran listrik bersamaan dengan teknologi lainnya, mempunyai hubungan dengan fajar nasionalisme kaum bumiputra pada awal abad 20 (hlm, 12). Dengan demikian, persoalan listrik sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan penerangan, tetapi juga dengan politik.
Lebih jauh lagi, studi Eko Sulistiyo memperlihatkan bagaimana kehadiran listrik, di samping berkaitan erat dengan ekonomi politik, juga membawa dampak perubahan secara sosial budaya. Batas temporal yang dipilih dalam studi ini dari 1901 sampai 1957. Karena pada tahun 1901 inilah disahkan akte pendirian Solosche Electriciteit Maatschappij (SEM) di Batavia, dan 1957 merupakan tahun pengambilalihan perusahaan SEM oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam kebijakan nasionalisasi (hlm, 16).
Selain itu, yang dimaksud kepentingan ekonomi politik dalam buku ini adalah kekuasaan kolonial yang memanfaatkan pengendalian infrastruktur kelistrikan untuk mengontrol kekuasaan atas negeri koloni, di samping strategis untuk menggerakkan ekonomi. Pemanfaatan energi listrik pun memperlancar tumbuhnya industri dan kapitalisme perkebubanan. Sementara dalam konteks sosial budaya, kehadiran listrik bermanfaat untuk semakin menghidupkan praktik budaya kesenian atau hiburan masyarakat di malam hari. Bahkan, kehadiran listrik bermanfaat untuk kehidupan keagamaan (hlm, 16&45).
Melihat listrik dari sisi ekonomi politik, juga dampak dari sisi sosial budaya yang menyebabkan penulis buku ini berargumen bahwa kehadiran listrik telah memicu lahirnya budaya perkotaan. Lokus dalam studi yang dilakukan oleh Eko terletak di Surakarta, yang saat era kolonial dikenal sebagai daerah Vorstenlanden (wilayah raja-raja). Dalam wilayah Vorstenlanden ini berlaku dua hukum, yakni hukum tradisional untuk masyarakat umum dan hukum Belanda bagi orang kulit putih (hlm, 10).
Kolaborasi Raja dan Pemerintah Kolonial Belanda dalam Pengembangan Listrik di Solo
Listrik di Solo mengalami kemajuan. Hal itu bisa terjadi, salah satunya karena dukungan kuat dari pemerintah lokal, dalam hal ini pihak kerajaan (hlm, 58). Bahkan dalam studinya tersebut, Eko Sulistiyo pun memaparkan sosok Pakubuwana X yang begitu merasakan manfaat dengan adanya listrik (hlm, 87).
Melalui dukungan kerajaan, SEM semakin memperluas pengadaan listrik. Sebagai contoh, pada 1937 diadakan perjanjian baru antara SEM dengan Keraton Kesunanan dan Pura Mangkunegaran tentang lampu di jalan wilayah Solo, Klaten, dan sebagainya. Maksud dari perjanjian itu, salah satunya agar listrik dialirkan lebih banyak lagi dari sebelumnya. Pihak kerajaan mempunyai kesadaran bahwa minimnya penerangan listrik di jalanan mengakibatkan potensi terjadinya kecelakaan yang lebih besar (hlm, 88-91).
Akan tetapi, ada pergeseran dalam peta politik dunia yang menyebabkan terjadinya perubahan di Hindia Belanda, termasuk di Surakarta. Pada 1942, tentara Jepang mengalami kemenangan pada Perang Pasifik dan ini menjadi jalan masuk bagi Jepang untuk menduduki Hindia Belanda. Salah satu imbasnya, Jepang mengambil alih perusahaan-perusahaan milik Bangsa Eropa, termasuk listrik. Meski demikian, Jepang tetap menyadari pentingnya kehadiran listrik, sehingga perubahan struktur kekuasaan dari Belanda ke Jepang ini tidak menghentikan penerangan listrik (hlm, 211-225).
Pengaruh Perubahan Struktur Kekuasaan dalam Pengelolaan Listrik di Tingkat Nasional
Singkat cerita, peta politik kembali berubah dengan menyerahnya Jepang pada Sekutu 15 Agustus 1945. Setelah itu, para buruh pun bergerak dengan mengambil alih listrik yang semula dikelola oleh Jepang. Aksi buruh ini terjadi pada September 1945. Delegasi para buruh ini, dengan ditemani Kasman Sigodimejo bertemu Sukarno untuk menyerahkan perusahaan listrik dan gas kepada Pemerintah Republik Indonesia (hlm, 235).
Namun sayangnya, keterbatasan pengetahuan Pemerintah dalam mengelola kelistrikan dan ketidakjelasan status kepemilikan perusahaan-perusahaan itu, menyebabkan pengembangannya menjadi mandek. Hal ini semakin diperparah dengan adanya agresi militer Belanda pada 1947 dan 1949. Agresi militer Belanda tersebut sempat memberi angin segar bagi para pemilik modal Belanda untuk kembali mengelola listrik dan sebagainya (hlm, 236).
Akan tetapi, dengan adanya hasil Konferensi Meja Bundar yang membuat sentimen terhadap Belanda semakin menguat, angin segar untuk para pemilik modal Belanda ini tidak berlangsung lama. Ditambah lagi ada masalah seperti pencurian listrik, pekerja yang berkurang, dan sebagainya. Ide nasionalisasi pun semakin menguat dan mendesak perusahaan asing ini (hlm, 236-237).
Pada 1953, pemerintah Indonesia berinisiatif membentuk Panitia Nasionalisasi Listrik. Singkat cerita, pada 1959, mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 tahun 1959, aneka perusahaan listrik yang tersebar di penjuru Indonesia telah menjadi Perusahaan Listrik Negara (PLN) (hlm, 238).
Pengembangan Lebih Lanjut Studi Kelistrikan
Dari uraian di atas, ada beberapa poin penting dan menarik. Pertama, kolaborasi kedua pihak kerajaan (Keraton Kasunanan dan Pura Mangkunegaran) dengan pemerintah kolonial yang justru berlangsung secara positif dalam program penerangan listrik. Temuan dalam studi ini, berbeda dengan kebanyakan studi yang membenturkan antara pihak kerajaan tradisional dan pemerintahan kolonial. Meskipun dalam konteks hubungan kerajaan dengan pemerintah kolonail dalam hal ini pun mengalami kontestasi dengan diwarnai adanya perbedaan pandangan terkait pengembangan listrik lebih lanjut.
Kedua, studi tersebut menunjukkan bahwa semangat beragama bisa adaptif dengan kemajuan teknologi, dibuktikan dengan adanya anggapan bahwa kehadiran listrik dapat mendukung kegiataan keagamaan (ngaji). Ketiga, adanya kesadaran penting bahwa teknologi untuk kemajuan mesti selalu digelorakan, tentu saja dengan tidak mengabaikan asas kemanfaatan dan keberlanjutan.
Studi Eko Sulistiyo ini menunjukkan bahwa listrik turut menjadi penggerak perubahan sosial. Oleh karena itu, soal listrik tidak hanya berurusan dengan angka-angka. Maka saya rasa, penelitian sejarah kelistrikan perlu untuk lebih dikembangkan dengan mendialogkan secara mendalam dan kritis dengan teori-teori sosial ataupun ekonomi politik.
Sebagai contoh, meskipun kita tidak bisa membantah betapa penting kehadiran listrik, tapi kita perlu meninjau lagi keterkaitan listrik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat kalangan bawah pada umumnya di era kolonial. Misalnya saja, apakah kehadiran listrik yang amat penting untuk kehidupan kapitalis perkebunan, juga berdampak positif terhadap tingkat kesejahteraan kelas pekerjanya? Atau listrik hanya mengefektifkan akumulasi kapital bagi kelas pemodal?
Masalah lainnya yang perlu diteliti lebih lanjut, mengapa kelas buruh secara heroik berupaya mengambil alih perusahaan listrik yang dikelola asing? Apa hanya karena sentiment nasionalisme yang kuat dan menghadirkan semangat anti-Belanda, atau berkaitan juga dengan kesejahteraan kelas pekerja di perusahaan-perusahaan listrik tersebut?
Meneliti dinamika di dalam perusahaan listrik pun menjadi hal penting dan bisa jadi PR buat peneliti selanjutnya. Mengingat kehadiran listrik yang sangat penting dalam penggerak perubahan sosial ini, tidak mungkin dapat berjalan secara efektif tanpa adanya kelas pekerja.
Category : resensi
SHARE THIS POST