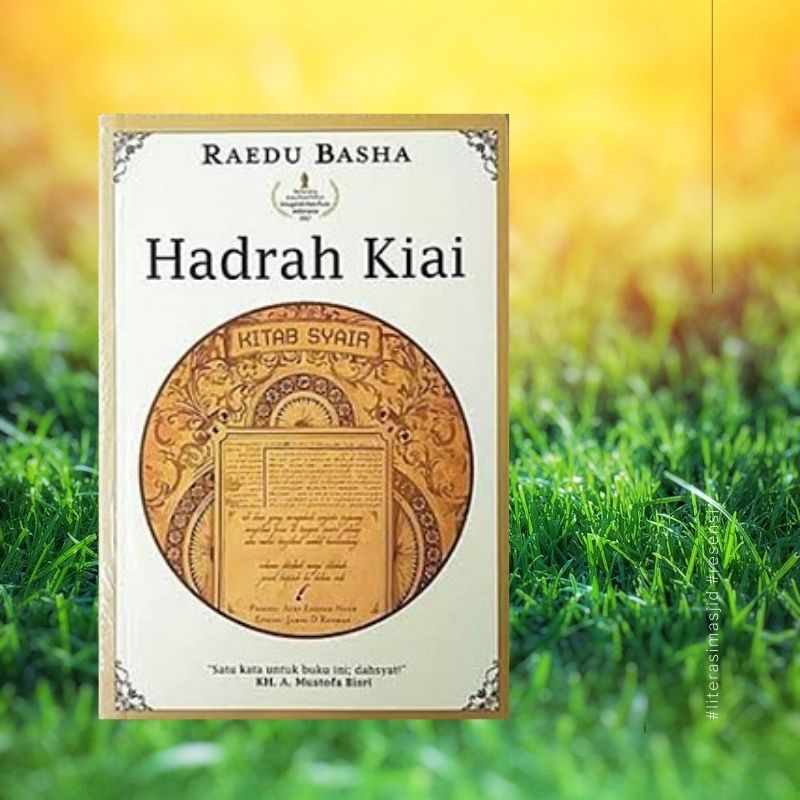Kiai dalam Hadrah Puisi
Judul: Hadrah Kiai | Penyusun: Raedu Basha | Tahun: 2017 | Penerbit: Ganding Pustaka | Tebal: 140 halaman | ISBN: 978-602-6505-17-0
Saya bukan pembaca puisi yang tekun. Kalau disuruh memilih pasti akan lebih memilih menulis prosa berlembar-lembar daripada harus menulis selembar puisi. Saya hanya setia membaca puisi dua penyair, Joko Pinurbo dan Puitri Hati Ningsih. Puisi Joko Pinurbo jauh dari ndakik-ndakik tapi mengena, sedang Puitri yang saya kenal personal, celetukannya pun adalah puisi bagi saya. Saya kurang suka puisi dengan diksi yang rumit.
Sebagai seorang yang besar di lingkungan nahdliyin, saya terlambat sekian tahun membaca puisi Hadrah Kiai karya Raedu Basha ini. Tahun-tahun lalu saya malah lebih kenal dengan Mario Lawi dengan Ekaristi-nya. Saya suka puisi bertema religius seperti cerita tentang tradisi gereja Katholik dan kehidupan biara. Hadrah Kiai membuat saya tertampar karena seharusnya buku ini lebih dekat dengan kultur keagamaan di lingkungan saya.
Raedu seorang putra Madura, lahir dan besar di lingkungan pesantren. Puisinya bertebaran kata-kata yang biasa digunakan dalam lingkungan pesantren. Jika kita pernah nyantri atau minimal ngaji di madrasah tentu tidak asing dengan kata-kata seperti syakal, i’rab, dlamir, alfiyah, safinah, utawi iki iku atau hu, hu, hu (kata ganti “dia” untuk Tuhan) dalam zikiran yang umum di kalangan kaum nahdliyin. Kita bisa bernostalgia sejenak mengenang ngaji sharaf dalam puisi Tasrifan Kiai Maksum Jombang di halaman 48 karena ada fa’ala, yaf’ulu, fa’lan sampai unsur la tansur di sana. Tasrifan yang sangat populer, sampai-sampai ketika takut dengan hantu pun yang diucapkan adalah tasrifan tersebut.
Atau jika ingin menguji ingatan hukum tajwid bisa kita temukan dalam puisi Simurgh di Ujong Panco di halaman 10. Ketika Simurgh bertanya, “Apa bedanya alif dan hamzah tanpa syakal?”, dan dijawab oleh Syekh Hamzah Fansuri, “Seperti huruf ya dan alif layyinah tanpa syakal”. Memang untuk orang awam atau di luar nahdliyin agak kesulitan dengan banyaknya diksi tersebut. Namun Raedu tidak pelit dengan memberi glosarium sebagai penjelasan di halaman akhir, meski saya pribadi lebih suka dengan catatan kaki.
Saya teringat salah satu ceramah Gus Baha tentang pentingnya mengenalkan nama-nama wali dan ulama kepada anak-anak kita agar, dalam ingatannya tidak hanya selebritis luar negeri yang menjadi idolanya. Raedu mengajak kita mengenal, menziarahi dan sowan kepada wali-wali dan ulama melalui puisi-puisinya. Semua puisinya dipersembahkan untuk para ulama baik yang masih hidup atau sudah meninggal.
Ia membagi kumpulan puisinya menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah Hadrah Arwah yang diperuntukan untuk para ulama yang sudah meninggal dan bagian dua adalah Hadrah Hayah yang diperuntukan untuk ulama yang masih hidup (hayah berarti hidup). Raedu dalam bukunya seperti pemimpin rombongan wisata ziarah bagi saya. Di setiap puisi ia menunjukkan wawasan literernya tentang para ulama yang diziarahi. Ia bisa mengambil satu ciri khas atau sudut pandang dalam tiap ulama. Bisa karena keilmuannya atau sejarahnya. Ada juga sisi personal yang ia tunjukkan dalam puisi Ziarah Walisongo. Ia menyatakan penyesalan dan kerinduannya kepada Sunan Gunung Jati karena belum sempat berziarah ke sana.
sepanjang ini belum sempat aku ziarah
ke haribaanmu syarif hidayatullah
(Ziarah Walisongo, hlm. 18)
Puisi naratif panjang tapi tidak membosankan menurut saya adalah Tahlil Fadilah Bagi Kiai Hasyim Asy’ari. Sebagai orang yang akrab dengan kultur yasinan, saya merasa familiar sekaligus aneh dengan judul puisi ini. Saya mengenal ‘yasin fadilah’ yaitu QS. Yasin yang ditambahi bacaan-bacaan fadilah (keutamaan). Dalam penjelasan Raedu di catatan kakinya, ‘tahlil fadilah’ ini mengumpamai ‘yasin fadilah’ yaitu bacaan tahlil yang disertai bacaan-bacaan keutamaan berupa bait-bait puisi berbahasa Indonesia.
Puisi panjang yang menceritakan sejarah perjuangan KH. Hasyim Asy’ari dalam mendirikan Nahdhatul Ulama (NU). Dari puisi ini saya juga mendapatkan referensi dasar hukum tawasul (berdoa dengan perantara). Tradisi yang umum dilakukan dalam kultur masyarakat nahdliyin.
‘maka atas nama Muhammad kekasihmu
Aku bersujud dan kembali kepadamu’
Bertaubatlah keduanya
…
“wahai adam hawa
maka atas nama kekasih-ku Muhammad
kalian ku-ampuni meski akhirnya
mesti kulemparkan ke bumi” firmannya
aku terhenyak menyimak kisahmu, kiai.
“santriku, inilah yang disebut tawasul
menyambung perantara kasih ke hadirat rasul
untuk mendapatkan kasih sang maha kasih
:tahlil
o bertahlillah!”
lailahailallah
muhammadur rasulallah
(Tahlil Fadilah Bagi Kiai Hasyim Asy’ari hlm. 36)
Dalam Hadrah Arwah, kita akan mengenang perjalanan Sunan Gresik, kontroversi Syekh Siti Jenar, Nashaihul Ibad-nya Syekh Nawawi Al Bantani, kisahnya Mbah Cholil Bangkalan, sejarah pendirian Muhammadiyah oleh KH. Ahmad Dahlan, tasrifan Kiai Maksum Jombang, makna miring dalam kitab peninggalan Sunan Gunung Jati, tafsir Al Ibriz Kiai Bisri Musthofa, zuhudnya Kiai Ahmad Sarang, pencipta yalal wathon Kiai Wahab Chasbullah, doa keramat sang nenek Kiai Ihsan Jampes, kisah syahidnya Kiai Abdullah Sajjad dibedil kumpeni, sampai Buya Hamka dan asiknya Gus Dur. Raedu tidak hanya menyebutkan ulama NU saja karena ada KH. Ahmad Dahlan dan Buya Hamka di dalamnya. Saya jadi teringat dengan teman-teman nahdliyin yang selalu mampir di makam KH. Ahmad Dahlan ketika berkunjung ke Yogyakarta untuk berziarah. Raedu telah melakukannya dalam puisinya.
Dalam Hadrah Hayah kita diajak sowan ke Habib Luthfi bin Yahya di Pekalongan, Gus Mus di Rembang, Prof. Quraish Shihab dan mata ini tiba-tiba basah karena nama Mbah Moen dan Kiai Ahmad Basyir AS masih tercantum di Hadrah Hayah. Andai buku ini diterbitkan ulang, tentu saja nama Mbah Moen dan Kiai Ahmad Basyir AS sudah ada dalam Hadrah Arwah. Sepanjang 2020 sampai awal 2021, ketika saya meresensi buku ini sudah banyak para alim yang kapundhut. Kepergian ulama ini tentu saja membuat hati sedih dan terus berinstropeksi. Hadrah Kiai mengingatkan saya dengan keilmuan para ulama yang sudah berpulang tersebut.
Category : resensi
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan
- Buku Ngaji Pascakolonial
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-8 Desember 2024