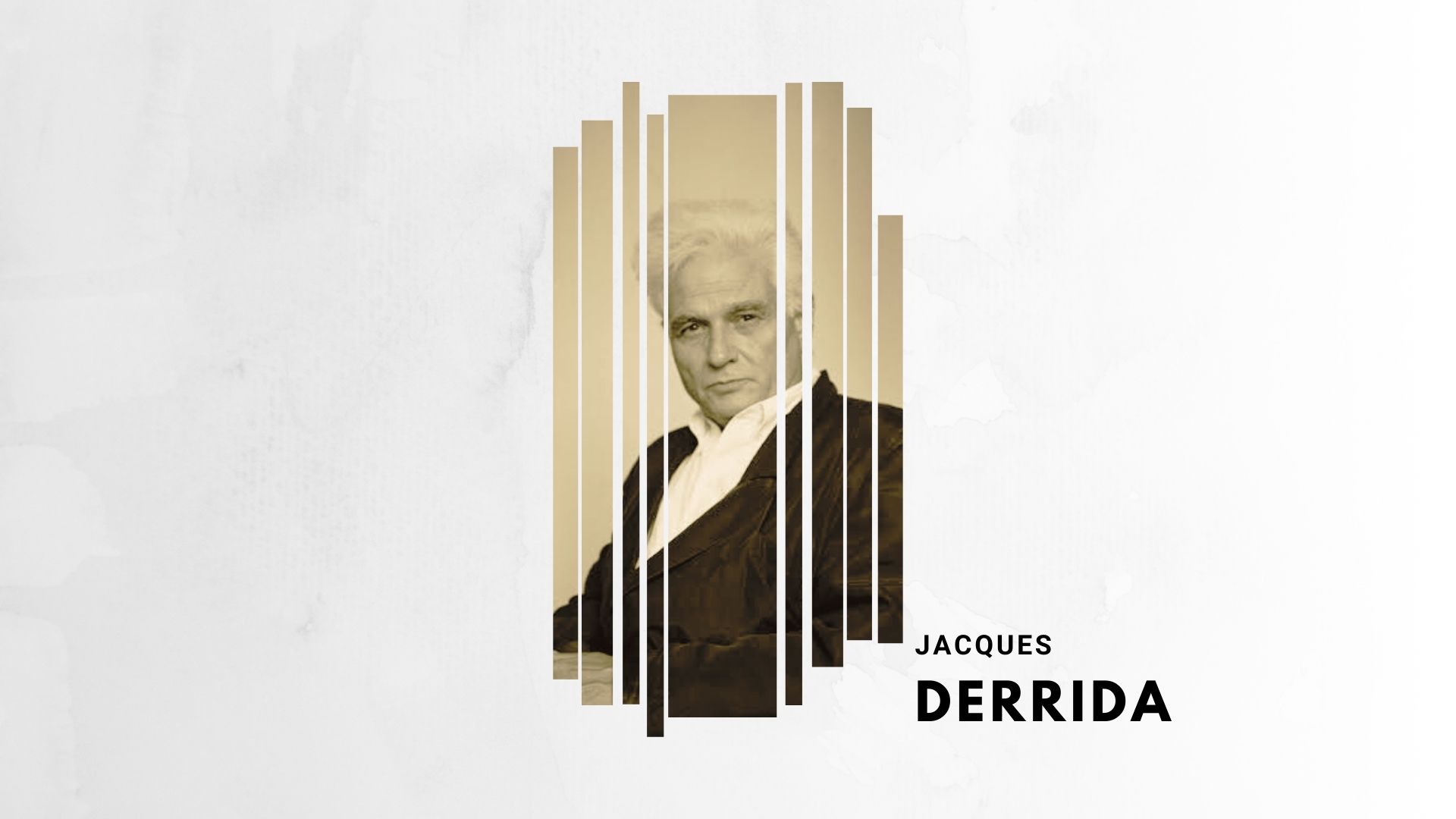Dekonstruksi Derrida: Upaya Memaknai Ulang Konstruksi Sosial
Manusia selalu dihadapkan pada dua pilihan yang saling bertolak belakang (oposisi biner), seperti benar dan salah; baik dan buruk; indah dan tidak indah; atau pantas dan tidak pantas.
Oposisi biner seperti itu tentu sangat dibutuhkan oleh manusia modern, sebab mereka membutuhkan suatu acuan nilai sebagai landasan berpikir dan bertindaknya. Dapat dibayangkan, bila tidak ada suatu acuan nilai, maka akan terjadi kekacauan dalam kehidupan manusia di muka bumi ini.
Akan tetapi, suatu acuan nilai tidak selamanya membawa dampak keharmonisan bagi manusia. Adakalanya suatu acuan nilai malah akan membelenggu kehidupan manusia.
Sebagai contoh, seseorang yang menganggap bahwa A adalah benar, pasti akan menganggap bahwa yang selain A adalah salah; atau seseorang yang menganggap bahwa B adalah baik, pasti akan sulit membuka pikirannya untuk menerima bahwa yang selain B pun baik.
Bila demikian halnya, bukankah suatu acuan nilai merupakan belenggu bagi manusia? Dan bila demikian halnya, siapakah yang harus bertanggung jawab akan semua hal tersebut?
Meminjam teori kekuasaan Michel Foucault, lembaga sosial-lah yang seharusnya bertanggung jawab akan semua hal tersebut. Sebab bagaimanapun, lembaga sosial (seperti keluarga, agama, hukum adat, norma masyarakat, dan sebagainya)-lah yang telah menciptakan suatu acuan nilai, yang sebenarnya merupakan klaim kebenaran.
Adapun klaim kebenaran merupakan suatu rekayasa kebenaran yang diciptakan oleh lembaga-lembaga sosial yang memiliki kuasa atas pengetahuan dan wacana; sehingga dari pengetahuan dan wacana itulah kemudian lahir sesuatu yang oleh masyarakat diadopsi sebagai “kebenaran”.
Sebagai contoh, seorang anak yang di rumahnya diharuskan untuk tidur di bawah jam sembilan malam, akan merasa berdosa jika ia tidur di atas jam sembilan malam. Hal tersebut menunjukkan bahwa si anak telah mengadopsi aturan yang diciptakan oleh kekuasaan orang tuanya sebagai suatu “kebenaran”, yaitu ketika si anak merasa berdosa bila ia tidur di atas jam sembilan malam.
Lantas, bagaimana bila si anak tidak merasa berdosa jika ia tidur di atas jam sembilan malam? Tentu, hal tersebut menunjukkan bahwa si anak telah mengabaikan kekuasaan orang tuanya—dengan mengabaikan aturan jam tidur—meskipun pada dasarnya ia tetap meyakini bahwa tidur di atas jam sembilan malam merupakan suatu hal yang tidak baik, sebab dapat membuat bangun menjadi kesiangan dan akan terlambat datang ke sekolah, misalnya).
Dari uraian mengenai teori kekuasaan di atas, lantas adakah kaitannya dengan teori dekonstruksi? Sebenarnya teori kekuasaan Foucault memiliki kemiripan dengan teori dekonstruksi yang digagas oleh Jacques Derrida, yaitu sama-sama membongkar suatu “kebenaran” yang sebenarnya merupakan konstruksi yang telah disepakati bersama (konstruksi sosial).
Akan tetapi, Foucault dengan teori kekuasaannya lebih memfokuskan analisisnya terhadap relasi kekuasaan dan bagaimana cara kekuasaan itu beroperasi; teori dekonstruksi Derrida lebih memfokuskan analisisnya terhadap objek yang memuat “nilai-nilai kebenaran” yang telah disepakati tersebut.
Secara definisi, dekonstruksi adalah suatu pemikiran atau metode berpikir untuk memahami kontradiksi yang terdapat di dalam sebuah teks dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat di dalam teks tersebut.
Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, teori dekonstruksi tidak hanya digunakan untuk menganalisis sebuah teks saja (seperti karya sastra misalnya), tetapi bisa juga digunakan untuk menganalisis berbagai konstruksi sosial.
Pemikiran dekonstruksi percaya bahwa sebuah teks atau konstruksi sosial memiliki makna-makna yang tersembunyi di dalamnya dan memiliki arti yang berbeda sesuai penafsiran dari masing-masing subjek. Oleh karena itu, pemikiran dekonstruksi membutuhkan proses pencarian makna secara struktural (menyeluruh) dari makna tunggal yang telah disepakati bersama (konstruksi sosial).
Sebagai contoh, kita bisa mengambil kasus anak kecil tadi, yaitu seorang anak kecil yang di rumahnya diharuskan untuk tidur di bawah jam sembilan malam dan merasa berdosa bila ia tidur di atas jam sembilan malam.
Bila sebelumnya kita memakai teori kekuasaan Foucault, tentu sangat jelas bahwa relasi kekuasaan tersebut ialah orang tua dan anak—si anak sebagai agen kekuasaan orang tuanya—sebab tanpa anak kekuasaan orang tua tidak berarti apa-apa. Sedangkan terkait bagaimana cara kekuasaan itu beroperasi, ialah ketika si anak merasa berdosa bila ia tidur di atas jam sembilan malam, atau ketika si anak mendapatkan dampak dari pelanggarannya tersebut (dimarahi atau terlambat datang ke sekolah).
Lantas, bagaimana jika kita menggunakan teori dekonstruksi? Bila kita menggunakan teori dekonstruksi, langkah pertama yang harus kita lakukan ialah mencari terlebih dahulu secara keseluruhan konstruksi atau makna awal pada kasus tersebut.
Bila konstruksi atau makna awal pada kasus tersebut kita pahami sebagai “Aturan untuk mencegah keterlambatan si anak datang ke sekolah”, maka selanjutnya kita bisa mencari kontradiksi pada kasus tersebut, yaitu “Mengapa si anak diharuskan untuk tidur di bawah jam sembilan malam dan tidak diperbolehkan untuk tidur di atas jam sembilan malam? Bukankah tidur di atas jam sembilan malam tidak menjamin si anak terlambat datang ke sekolah?”.
Dari kedua pertanyaan tersebut, kita bisa mendayagunakan pikiran kita pada satu kesimpulan yang lebih radikal, yaitu “Jangan-jangan orang tuanya memiliki maksud lain di balik aturan tidur tersebut—agar tidak diganggu oleh si anak, misalnya (?)”
Secara sederhana, seperti itulah penerapan teori dekonstruksi Derrida, yaitu untuk mengajak kita berpikir lebih kritis, skeptis, dan radikal dengan memaknai ulang berbagai konstruksi sosial yang terdapat di masyarakat tanpa harus menjadikan suatu oposisi biner (benar atau salah dan sebagainya) sebagai kemutlakan.
Sebab, seperti yang dikatakan oleh Derrida sendiri, bahwasanya tidak ada yang pasti di dunia ini selain ketidakpastian. Oleh karena itu, pemikiran dekonstruksi percaya bahwa makna yang melekat pada suatu hal atau objek tidak bisa stabil atau terus-menerus bergerak sesuai penafsiran dari masing-masing subjek.
Sebagai salah satu metode berpikir postmodernisme, teori dekonstruksi bersifat lebih fleksibel (karena sifatnya yang subjektif) dan banyak digunakan untuk membedah berbagai macam teks, seperti karya sastra, undang-undang, aturan tertulis, atau bahkan kitab suci.
Selain itu, teori dekonstruksi pun memungkinkan kita untuk menjadikannya sebagai “pisau” untuk membedah berbagai konstruksi sosial, karena berbagai konstruksi sosial yang ada sering kali berupa perlambang.
Akan tetapi, kita jangan sampai lupa, bahwa tidak selayaknya bagi kita umat manusia—yang memiliki keterbatasan pengetahuan—untuk mendekonstruksikan setiap hal yang terdapat di dunia ini. Sebab, seperti yang telah disampaikan oleh Pak Fahruddin Faiz dalam Ngaji Filsafat ke-222: Rene Descartes - Skeptisisme, edisi Filsafat Barat Lagi, Rabu, 13 Maret 2019, bahwa, “Bila setiap hal di dunia ini kamu pertanyakan, maka hidupmu akan sumpek sendiri.” Begitu.
Referensi:
Agnes Setyowati, “Memahami Kekuasaan dalam Pemikiran Michel Foucault”, dalam kompas.com, 20 Juni 2022.
Mangihut Siregar, “Kritik Terhadap Teori Dekonstruksi Derrida”, dalam Jurnal of Urban Sociology, Vol. 2, No. 1, 2019.
Yohanes Florianus Tana, “Memahami Teori Dekonstruksi Jacques Derrida sebagai Hermeneutika Radikal”, dalam lsfdiscourse.org, 26 Juli 2019.
Category : filsafat
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan
- Buku Ngaji Pascakolonial
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-8 Desember 2024