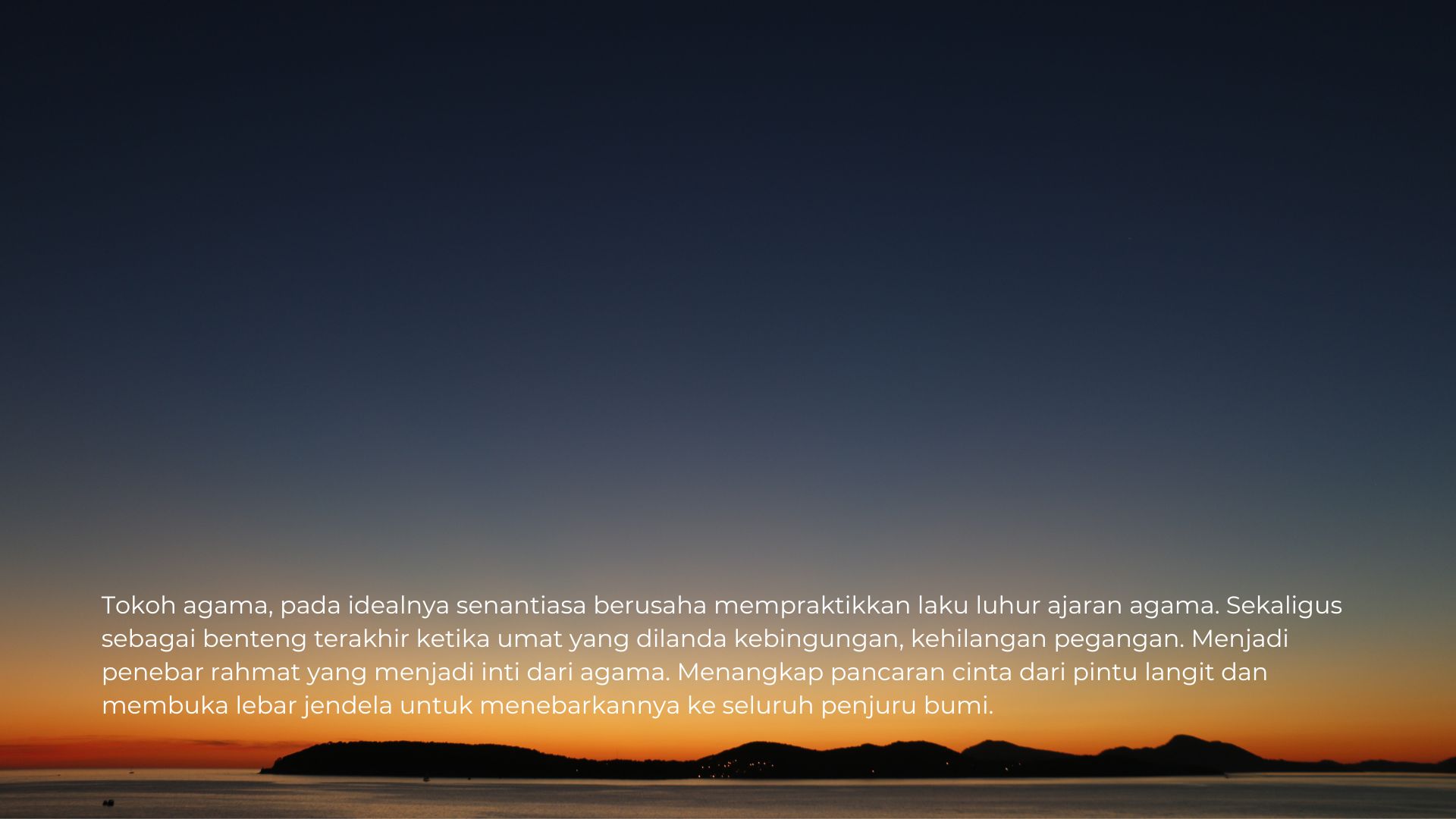Tokoh Agama
Bulan Maulud 1335 Hijriyah, para tokoh agama berkumpul di serambi Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta. Di hadapan para penghulu, khatib, ulama, dan kiai yang hadir, Kiai Ahmad Dahlan memberikan wejangan tentang kerusakan umat dan kaitannya dengan kerusakan para ulama.
Kiai Dahlan mengutip Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa ulama yang jahat menjadikan ilmu yang dimilikinya untuk tujuan yang keliru: guna memperkaya diri, menyombongkan diri dengan kedudukannya, membanggakan diri dengan banyaknya pengikut, dan seterusnya. Imam Al-Ghazali juga mengingatkan, kerusakan rakyat disebabkan oleh karena kerusakan para pemimpin dan kerusakan pemimpin disebabkan oleh kerusakan para ulama.
Setelah penjabaran itu, Kiai Dahlan menyinggung tentang sikap tokoh agama yang kadang saling menunjuk orang lain sebagai ulama’ al-su’. Lumrahnya sikap dasar manusia untuk selalu merasa benar dan dibenarkan. Sebaliknya juga tidak ingin merasa salah. Mengakui kesalahan dianggap dapat meluruhkan harga diri.
Tutur Kiai Dahlan, “Marilah kita sekarang mengajak para ulama mengakui bahwa ulama’ al-su’, ulama dajjal, adalah diri kita ini. Dan saya, Ahmad Dahlan, termasuk ulama’ al-su’ yang merusak agama Islam. Mudah-mudahan pengakuan ini dapat menghapus dosa dan melebur amalku.”
Peristiwa tersebut diabadikan oleh K.R.H. Hadjid dalam Pelajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan, 7 Falsafah dan 17 Kelompok Ayat Al-Qur’an. Sebagai sahabat dan murid termuda dari Kiai Dahlan, Kiai Hadjid sangat memahami jalan pikiran gurunya. Kiai Hadjid memberikan syarahan, “Kiai Dahlan mengajak untuk memperbaiki diri sendiri terlebih dahulu, sebelum mengajak orang lain. Atau sambil mengajak orang lain dan sambil memperbaiki masyarakat, mulai dari mendidik perseorangan serta membersihkan dirinya sendiri.”
Kisah ini begitu menggugah saya ketika dalam suasana duka gempa dan tsunami di Lombok dan Palu, beredar meme yang mengatasnamakan Kiai Dahlan. Berisi gambar Kiai Dahlan dengan cuplikan kalimat bahwa sebab mutlak dari bencana alam yang melanda bangsa ini adalah karena pucuk pimpinan atau presiden yang rusak. (Kutipan Kiai Dahlan dari Imam Ghazali diselewengkan). Tafsiran politik ini cukup mengiris rasa kemanusiaan. Dan lebih miris lagi, beberapa tokoh agama ikut serta menyebarluaskan.
Belakangan, ada teman yang merasa aneh dengan mimbar-mimbar agama yang berisi ujaran yang tidak sepantasnya. Terkadang, khotbah Jumat tak ubahnya panggung kampanye politik. Beberapa ruang pengajian juga berubah fungsi. Saling menyalahkan sesama tokoh agama yang berbeda pilihan. Teman lainnya yang seorang takmir masjid ikut bersuara, ia merasakan grup WhatsApp jamaah masjid berubah jadi ajang pertarungan ambisi kekuasaan.
Hari-hari ini, di saat publik larut dalam histeria politik dan gejala populisme, tokoh agama kadang justru ikut serta. Mungkin oknum tokoh agama, melalui mimbar agama, membawakan narasi yang membelah umat menjadi dua: kita dan mereka. Golongan ‘kita’ sebagai yang utama dan harus mendapat perlakukan istimewa. Sebaliknya, kelompok ‘mereka’ adalah yang mengancam kita, bukan yang utama, dan seharusnya boleh diperlakukan tidak sama dengan kita.
Beberapa kali, oknum tokoh agama yang seperti ini membawakan ceramah dengan narasi yang mengaduk perasaan dan emosi jamaah. Bertema tentang ancaman terhadap umat kita yang datang dari mereka: Yahudi, Nasrani, Cina, gendruwo, terorisme, narkoba, ideologi asing, imigran gelap, komunis, penguasa ekonomi minoritas, dan seterusnya. Pada ujungnya, sebagai solusi bagi umat, dikatakan bahwa kita membutuhkan sosok penyelamat untuk keluar dari ketakukan, yaitu calon pemimpin yang ini atau yang itu.
Bangsa kita yang besar ini tidak mengalami kemiskinan sumberdaya, namun terkadang mengidap kemiskinan etika dan keteladanan. Sementara itu, penyakit yang melanda masyarakat urban umumnya adalah penyakit akibat dari kekeringan jiwa dan cinta. Dahaga spiritualnya menggebu-gebu. Namun, kadang terjebak pada lapis permukaan. Ritme hidup bergerak cepat, silih berganti dalam keseketikaan. Jauh dari permenungan mendalam. Mereka mudah disulut, apalagi atas nama Tuhan dan keyakinan.
Dalam kondisi ini, kita merindukan tokoh-tokoh agama yang hadir di tengah umat sebagai penyejuk suasana. Terlebih dalam masyarakat kita yang majemuk, selalu dinantikan kehadiran tokoh yang menampilkan sikap welas asih. Foto pelukan antara Buya Ahmad Syafii Maarif dan KH. Mustofa Bisri (28/12) di tengah ketegangan politik, menjadi contoh bahwa tokoh agama bisa membawa keteduhan.
Para tokoh perlu menyadari posisinya sebagai kompas bagi banyak orang. Tutur kata dan perilakunya senantiasa menjadi sorotan, positif maupun negatif. Mereka dengan keluasaan ilmu yang dimiliki, menjadi teladan dalam ujaran dan tindakan. Mereka dengan pengalaman hidup dan kebijaksanaan, ikut menuntun pada kesalehan sosial. Agama tidak sekadar apa yang dipercaya, tetapi juga tentang apa yang diperbuat secara nyata.
Tokoh agama, pada idealnya senantiasa berusaha mempraktikkan laku luhur ajaran agama. Sekaligus sebagai benteng terakhir ketika umat yang dilanda kebingungan, kehilangan pegangan. Menjadi penebar rahmat yang menjadi inti dari agama. Menangkap pancaran cinta dari pintu langit dan membuka lebar jendela untuk menebarkannya ke seluruh penjuru bumi. Sabda Nabi Saw, “Cintailah mereka yang di bumi, maka Dia yang di langit akan mencintaimu.”
Dalam konteks kehidupan bernegara, peran tokoh agama dalam menerjemahkan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, tak kalah pentingnya. Kata ke-Tuhan-an berarti proses menjiwai, meniru, mendekati sifat-sifat Tuhan. Sifat-Nya yang paling dominan adalah rahman dan rahim. Karena limpahan kasih sayang-Nya, Allah mencipta semesta. Keseluruhan gerak alam raya diperjalankan dengan segenap prinsip rahmat. Tugas para hamba sebagai wakil-Nya di muka bumi adalah menjaga keserasian gerak semesta tetap dalam liputan kedamaian yang penuh kasih.
Menebar damai dan kasih adalah tugas tokoh agama dan kita semua. Barangkali film Where Do We Go Now (2011) karya Nadine Labaki cukup dapat menggambarkan tentang makna perdamaian positif dan peran tokoh agama. Film ini dibuka dengan tarian requiem oleh sekelompok perempuan berbusana serba hitam yang membawa foto dan seikat bunga di tengah sahara. Menuju ke pemakaman yang menguburkan anak-anak mereka oleh karena perseteruan yang mengatasnamakan agama. Perempuan berkalung salib dan berkerudung ini ditimpa pilu yang sama, berpeluh darah akibat perang atas nama salib dan bulan bintang.
Berawal dari masuknya berita tentang konflik di kampung lain melalui TV, radio, dan koran bekas. Kampung terisolir yang mulanya damai ini tiba-tiba menjadi tegang dan kacau. Para perempuan dari kedua agama berjuang keras menjaga suasana tetap aman dengan merusak sambungan pemancar komunikasi dan mengubur senjata di malam hari. Beragam cara digunakan untuk meredam kaum laki-laki yang mudah tersulut emosi.
Jelang akhir film, dua tokoh agama Kristen dan Muslim muncul di masjid dan gereja yang letaknya berdekatan, mengumumkan undangan penting melalui pengeras suara rumah ibadah. Ternyata, mereka bersepakat dengan para perempuan dan penari untuk mengadakan pesta besar-besaran yang mempertemukan semua pria di kampung. Dengan berat hati dan supaya tidak ada lagi korban jiwa, mereka terpaksa untuk berbuat sesuatu yang mungkin kurang beretika secara moral agama. Demi menyelamatkan nyawa manusia dan demi suasana damai yang tidak ternilai harganya.
*Buletin Jumat Masjid Jendral Sudirman, Edisi-18 Jumat 08 Februari 2019/03 Jumadilakhir 1440 H
Category : buletin
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Alam Pikiran Jawa-Islam: Filologi, Simbol, dan Struktur Babad Kraton
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan