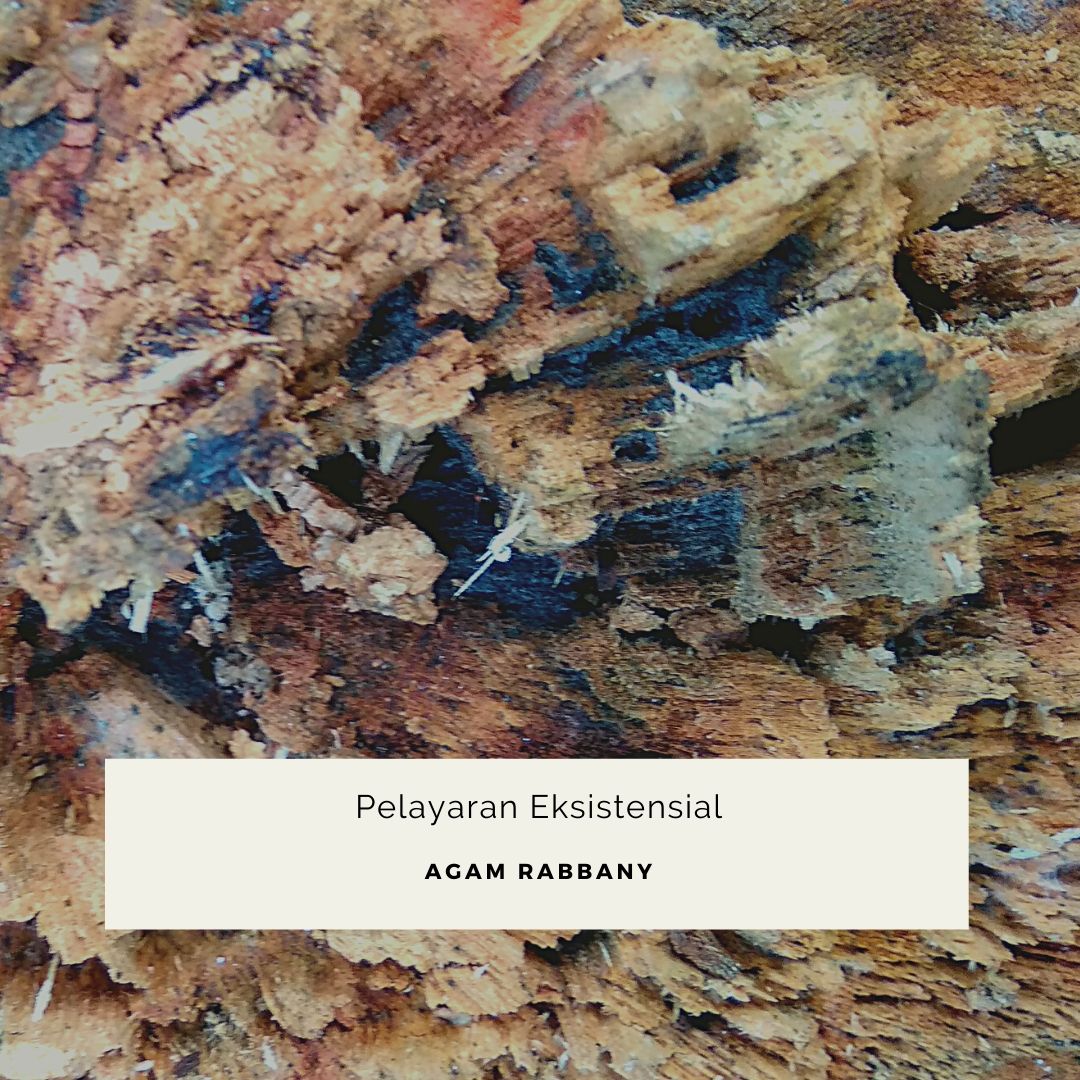Pelayaran Eksistensial
Awal 2017, saya seperti dihantam sesuatu yang tak jelas darimana datangnya. Bukan benda tajam atau tumpul, tetapi sesuatu yang membuat hati dan pikiran saya bergejolak. Tak soal jodoh, umur, dan pekerjaan yang tak kunjung menghampiri, tapi lebih pada perasaan yang sulit untuk dijelaskan mengapa bisa terjadi seperti itu. Kadang saya berpikir apakah ini bagian dari quarterlifer crisis atau bahasa familiarnya yaitu krisis eksistensial.
Kurang lebih sudah dua tahun bisa dibilang saya mencari apa yang disebut makna dalam hidup. Pada masa-masa krisis seperti itu, filsafatlah yang menyelamatkan saya dari fase awal kehidupan untuk beranjak lebih “dewasa”. Dari filosof alam seperti Heraclitus sampai kontemporer saya pelajari satu per satu, saya saring ide-idenya yang menurut saya cocok untuk saya berlayar.
Semua bermula pada saat saya melihat konten sejarah kejatuhan paham atau ideologi yang menganut ajaran Karl Marx di Indonesia dari laman Instagram. Saya membaca konten tersebut secara pelan-pelan hingga akhir dan selesai membaca, saya tersadar dan seperti ada yang memukul wajah saya. Ternyata, doktrin yang selama ini saya pegang tentang paham atau ideologi ajaran Karl Marx itu jahat, tak bertuhan, dan stigma negatif lainnya runtuh seketika.
Pada saat itu juga saya mencari sumber-sumber ilmiah tentang sejarah paham atau ideologi tersebut, hingga saya sering menghadiri diskusi konflik-konflik kelas entah itu soal agraria, lingkungan, sampai upah murah yang terjadi Indonesia. Pertanyaan yang muncul di kepala saya pada saat itu adalah mengapa paham atau ideologi itu bisa hadir di Indonesia? Dari pertanyaan “mengapa” tersebut saya sampai pada sesepuh teoritikus sampai praktikus Marxisme seperti Vladimir Lenin, Mao Zedong, maupun Fidel Castro. Seiring pembacaan saya akan sejarahnya, semakin saya mendekatkan diri pada filsafat Marxisme. Inilah titik di mana saya mengarungi samudera yang bernama filsafat, samudera yang membuat saya ingin terus berlayar, samudera yang mengharuskan saya bertualang dari suatu tempat ke tempat lainnya dan samudera yang membawa saya pada perjalanan intelektual hingga tidak ada batasnya.
Namun, apakah semua yang telah saya pelajari mampu menyelasaikan masalah dalam hidup? Jawabannya adalah bisa “tidak” bisa juga “ya” tergantung kita menghadapi medan pertempuran. Pak Faiz sering berbicara dalam kesempatan Ngaji Filsafat yang diampunya, bahwa kita belajar sesuatu seperti kita dapat senjata yang akan kita gunakan jika ada sesuatu yang mengancam diri kita. Senjata yang kita peroleh kita sesuaikan dengan ancaman yang membuat diri kita semakin terancam. Contohnya, ketika kita mengalami fase di mana keimanan kita goyah, gunakanlah senjata yang sesuai dengan konteks masalah tersebut, misalnya filsafat eksistensialisnya Soren Kierkegaard. Menurut Kierkegaard, keimanan itu tak perlu konsekuensi logis atau kalkulasi matematis. Maka, bisa diambil hikmahnya yaitu kita tak perlu mengukur sebab akibat dari keimanan. Cukup hayati dengan serius bahwa kita selama ini salah memahami keimanan masih berdasarkan kalkulasi surga dan neraka bukan karena lillahi ta’ala.
Kierkegaard memberi contoh level eksistensi religius dari kisah Ibrahim yang mengorbankan Ismail karena Tuhan. Pertama, infinite resignation. Menyerah secara total kepada Tuhan akan membawa seseorang lebih dekat kepada Tuhan, ke dalam kesadaran abadi bahwa yang ia butuhkan hanya Tuhan. Kedua, knight of faith is delighted. Ia percaya bahwa bersama Tuhan segalanya menjadi mungkin dan Tuhan akan memberinya segala yang ia butuhkan; oleh karena itu ia selalu gembira. Ketiga, the teleological suspension of the ethical. Ibrahim menunda evaluasi etika demi tujuan yang lebih besar, yaitu hubungan personalnya dengan Tuhan. Apa yang akan dianggap “pembunuhan” dari sudut pandang etika, dipandang sebagai pengorbanan dari sudut pandang religious (Ngaji Filsafat Soren Kiekegaard-Eksistensialisme, 26 Februari 2014).
Pelabuhan yang saya singgahi sekarang bernama postmodernisme, saya begitu takjub akan kritik-kritikan para filosof di dalamnya terhadap kehidupan abad modern. Mulai dari Nietzsche akan optimismenya akan kehidupan serta pandangannya terhadap konsep-konsep yang beku yang menihilkan peran penting diri sendiri. Hingga yang kontemporer sekalipun seperti Jurgen Habermas yang membawa saya akan makna atau esensi dari kehidupan berdemokrasi yang deliberatif. Tak luput juga sang pemikat saya, yaitu Albert Camus yang mengajarkan saya akan pentingnya memahami hidup tak hanya sebatas hitam dan putih; bahwa kita harus menerima keabsurdan dalam hidup.
Terakhir, sebelum pergi ke kapal untuk berlayar kembali saya bertemu dengan filosof yang bernama Ludwig Wittgenstein, ia pernah berujar, “Where of one cannot speak, there of one must be silent” (Apa yang tak bisa ia katakan maka kita harus diam). Frase itu sebagai bentuk kritik terhadap filsafat dan sains yang mengkonsepkan segala sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan, seperti contohnya tentang cinta. Apa itu cinta? Jika nalar logika tak bisa menjelaskan apa itu cinta maka ia harus diam.
Pelayaran saya masih jauh, banyak samudera kehidupan dan pulau ilmu pengetahuan yang belum saya kunjungi, ombak di lautan juga semakin meninggi maka saya harus mempersiapkan bekal yang cukup untuk menerjangnya sampai akhir memisahkan.
Category : kolom
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Alam Pikiran Jawa-Islam: Filologi, Simbol, dan Struktur Babad Kraton
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan