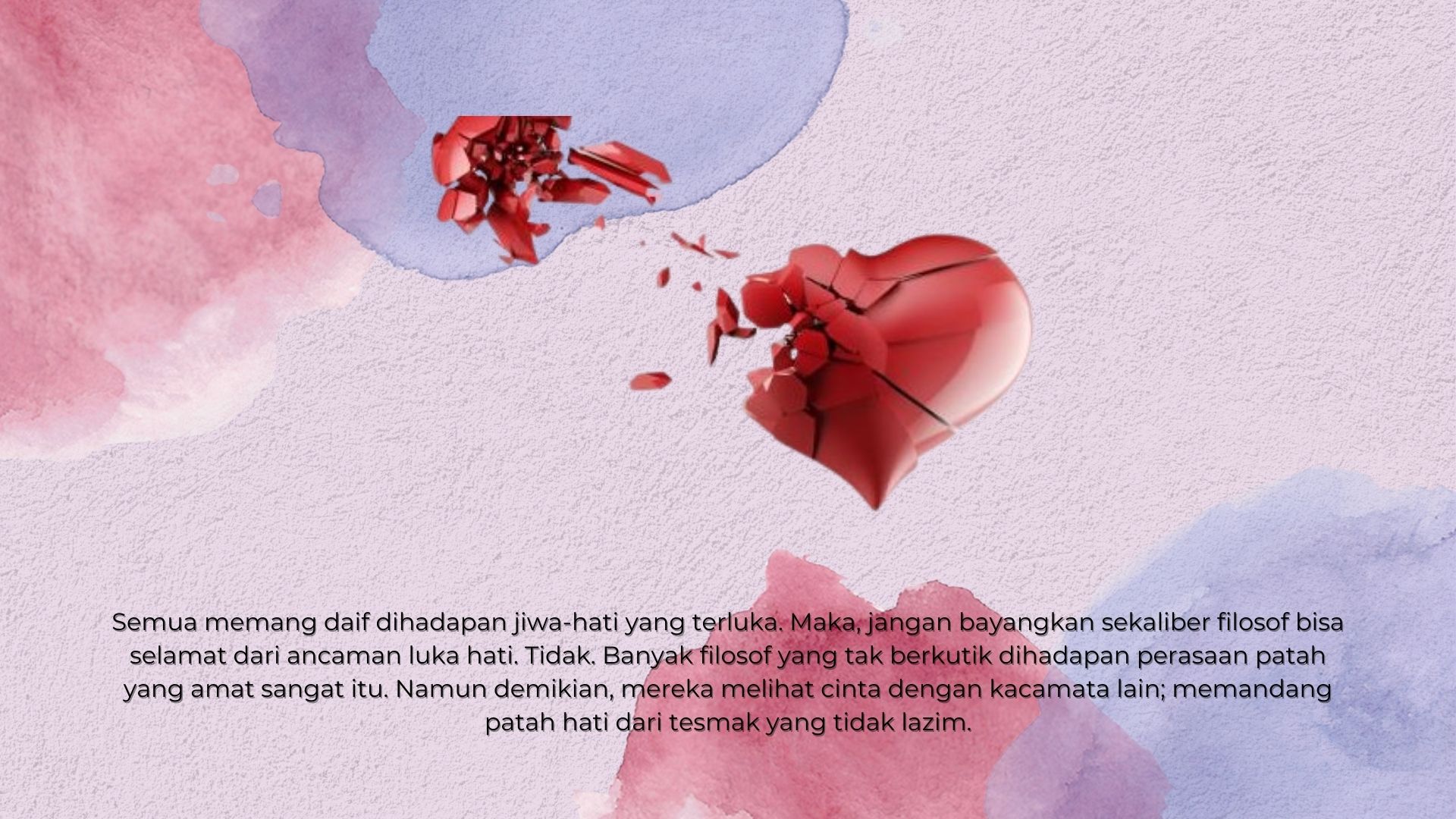Patah Hati dari Tesmak Filosof Eksistensialis
Kita bisa membaca banyak buku, belajar hingga ke negeri yang jauh, tetapi dihadapan patah hati kita bukan siapa-siapa. Betapa banyak manusia hebat, namun dihadapan rasa patah hati yang mengerikan mereka tidak berkutik. Sederet gelar, sederet presetasi, hanya kata yang tidak mempunyai makna apa-apa.
Semua memang daif dihadapan jiwa-hati yang terluka. Maka, jangan bayangkan sekaliber filosof bisa selamat dari ancaman luka hati. Tidak. Nyaris tidak masuk akal. Banyak filosof yang tak berkutik dihadapan perasaan patah yang amat sangat itu.
Wajar saja, jika orang biasa semacam kita tidak punya kuasa apa-apa. Toh, orang-orang hebat juga nyaris tidak berkutik dihadapan luka, tidak bisa bergerak dihadapan patah hati paling parah. Artinya, semua adalah hal yang alamiah belaka.
Puncaknya, semua bergantung pada cara bagaimana luka-luka itu disembuhkan. Juga bergantung pada sisi bagaimana patah hati itu dipandang dan dikuliti. Di sini, saya tidak hanya membicarakan luka yang natural, melainkan juga cinta dan patah hati dari termak filosof eksistensialis.
Orang-orang macam Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, dan kawan-kawan eksistensialis memberikan pandangannya. Mula-mula pada cinta, hingga berlanjut tatkala cinta bermetamorfosa menjadi luka yang parah. Hampir keseluruhan nama di atas dipantik oleh pergumulannya dengan perempuan.
Ya, Anda tidak salah baca, pergumulan mereka dengan perempuan. Tidak perlu kaget, filosof juga manusia. Mereka juga berhak merasakan menjadi manusia pada umumnya. Kierkegaard yang overthinking, Nietzsche yang gayungnya tak bersambut, hingga hubungan Heidegger-Hannah Arendt yang berantakan akibat gejolak Nazi-Yahudi.
Sampai di sini, pelan-pelan kita perlu merevisi persepsi kepada para filosof. Mereka tidak hanya orang-orang dengan pemikiran yang sekilas terlihat lugu, sekaligus jenius. Mereka bukan hanya lingkaran orang yang membangun teorinya dari apel yang jatuh. Tidak senantiasa serumit itu.
Lagi-lagi, mereka juga berhak menjadi manusia biasa—mencicipi lubang asmara. Tentu satu paket dengan rasa sakitnya, sebagaimana kata Kierkegaard. Pergumulan-pergumulan ke-patah-hati-an itu yang justru membawa mereka melihat cinta dengan kacamata lain; memandang patah hati dari tesmak yang tidak lazim.
Dari Kierkegaard, bahwa manusia terlahir untuk mencintai dan dicintai. Tanpa itu semua, maka hidup manusia menjadi hampa. Yang paling menarik, ia melihat titik luar biasa dari cinta hanya musabab segenap penderitaannya. Seorang pecinta mestinya sejak awal harus memahami ini, satu paket antara cinta dan patah hati.
Sampai pada bagian ini saya teringat salah satu ungkapan di dalam kaidah fikih: rela terhadap sesuatu, itu berarti rela terhadap efek yang timbul daripadanya. Singkatnya, rela jatuh cinta, rela patah hati pula.
Cinta seperti itu yang disebut Kierkegaard sebagai cinta hakiki. Berbanding terbalik dengan cinta yang romantik, entitas cinta yang timbal-balik. Cinta yang sesungguhnya tidak berbicara soal sebab dan akibat. Tepat pada cinta romantik inilah, patah hati banyak lahir.
Simpelnya, patah hati lahir dari perasaan kalkulatif dan perspektif utilitarian dalam mencinta. Dalam cinta yang hakiki, segala macam keuntungan dengan segera dinafikan. Cinta hanya untuk cinta itu sendiri, bukan hal lain di luar dirinya.
Lain dengan Keirkegaard, Sartre lebih lugas menuding cinta sebagai perampas kebebasan. Baginya, cinta adalah konflik, laki-laki dan perempuan saling mengobjekkan satu sama lain. Lalu, manusia kehilangan dirinya dan terjebak pada dunia orang lain. Bahkan, hasrat seksual mereduksi orang lain hanya sebagai daging dan tubuh semata. Apalagi pasca tenggelam dalam fantasi hubungan fisik.
Hampir senada dengan Sartre, Arthur Schopenhauer menegaskan cinta mampunyai rias yang menipu. Katanya, masalah pokok dalam cinta adalah hasrat untuk memiliki apa yang tidak bisa dimiliki.
Lagi pula, Schopenhauer menambahkan, seseorang hidup bersama memang berdasar pada asas kebutuhan. Dalam konteks cinta, kebutuhan dan hasrat untuk berketurunan. Puncaknya, ketika keinginan itu tidak terpenuhi, maka akan merasa sakit hati. Manusia akan merasa patah ketika hasrat agar cintanya berbalas justru bertepuk sebelah tangan.
Gayung tak bersambut pernah dialami Nietzsche. Kendati demikian, Nietzsche mengatakan saat patah hati manusia dapat mengevaluasi dirinya. Mulai melihat diri sendiri juga meningkatkan diri menuju versi terbaik. Hingga terwujud apa yang disebutnya sebagai ubermensch.
Kata Nietzsche, “Saat patah hati kita berada di titik terendah, mempertanyakan diri sendiri, nilai, dan bakat kita. Di sini kita diingatkan akan diri kita sendiri, bahwa kita berharga, berbakat, dan dapat dicintai, bahkan kita juga dapat meningkatkan diri dan menjadi versi yang lebih baik dari diri sendiri saat ini. Dan ini bukan untuk orang lain kecuali untuk kita, meskipun sebelumnya hanya untuk ‘dia’.”
Berbeda ketika keinginan dan hasrat itu terwujud, yang muncul justru rasa bosan. Kalau tidak bosan, maka keinginan tersebut akan terus berkembang biak. Di sisi lain, sifat dasariah manusia memang tidak bisa terlepas dari kendali keinginan.
Scopenhauer memberika tiga jalan mengatasi penderitaan dari keinginan yang terwujud. Mulai dari jalan estetis, etis, hingga asketis. Jalan estetis bentuknya seperti katarsis, yang hanya memberi kelegaan sementara, sesaat.
Mengatasi penderitaan lewat jalan etis dengan cara menjalankan “kebajikan”; membantu orang lain yang menderita. Namun jalan etis pun masih berhubungan dengan dunia nyata, tidak bebas sepenuhnya dari penderitaan.
Jalan mengatasi penderitaan paling awet dari Scopenhauer yakni dengan cara melakukan aktivitas membebaskan diri dari apa yang diinginkan. Langkah asketis ini berpijak pada negasi terhadap dunia untuk mencapai kedamaian dan ketenangan dimana ego terlampaui.
Schopenhauer juga mempunyai pandangan sekaligus taktik terkait patah hati. Antara lain pandangannya bahwa dunia itu berubah. Seseorang boleh mencintai Anda hari ini, tetapi tidak menutup kemungkinan ia pergi esok. Ketika hal tersebut terjadi, maka penderitaan kemudian menjadi guru terbaik. Pengalaman pahit tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kesakitan semata. Kalau dibahasakan dengan sedikit popular, mungkin begini: jika tidak mendapat cintanya, minimal mendapat hikmahnya.
Kemudian, merubah barometer untuk mengukur kebahagiaan. Mestinya, kebahagiaan diukur bukan sejauh mana hasrat dan keinginan itu tercapai, melainkan sebebas apa dari rasa sakit. Yang paling puncak dari taktik Schopenhauer adalah ketika kita menaruh harapan pada diri sendiri.
Memang susah menemukan kebahagian yang bersumber dari dalam (diri sendiri), namun lebih muhal menemukannya melalui orang lain. Padahal, bahagia yang sejati memancar dari dalam diri sendiri.
Kata Schopenhauer, temukanlah kebahagiaan itu dalam diri. “It is difficult to find happiness within oneself, but it is impossible to find it anywhere else”. Kebahagiaan sejati hanya dapat ditemukan di dalam diri, bukan melalui hubungan dengan orang lain, ketenaran, atau harta benda. Ketika kita cenderung melekat pada orang lain, atau kepemilikan apa pun di luar diri, menuntut mereka untuk membuat kita bahagia.
Kita harus mulai belajar menemukan dan menikmati kesendirian. Semakin cepat kita akan membebaskan diri dari ketergantungan dan rasa takut sendirian, semakin mudah kita menemukan kebahagiaan dan kedamaian.
Sekian, cinta-patah hati dan panduan mitigasi dari kacamata filosof eksistensialis.
Category : catatan santri
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan
- Buku Ngaji Pascakolonial