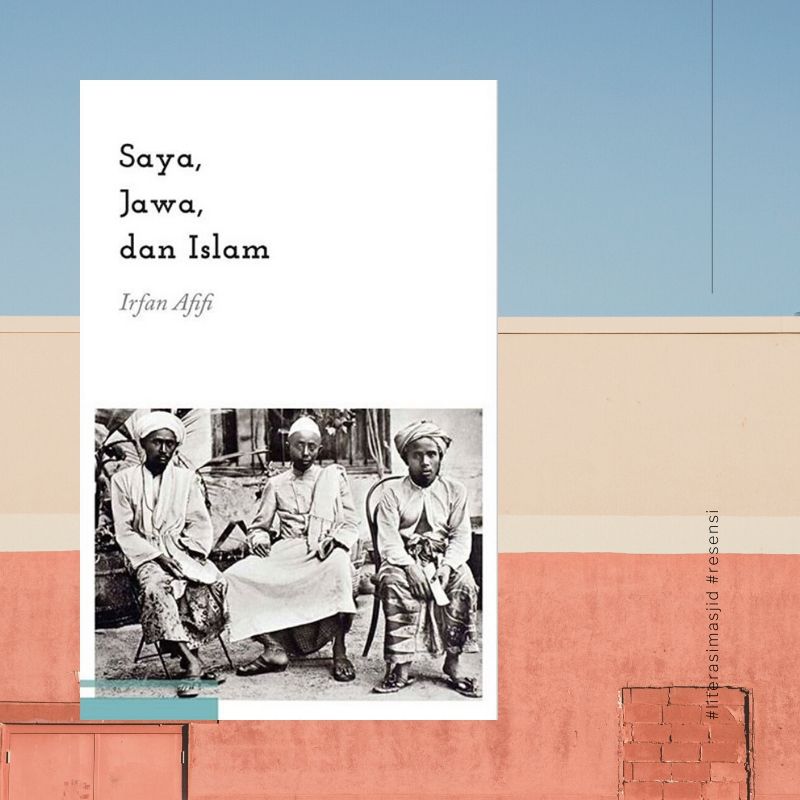Menyelami Mulat Sarira
Judul: Saya, Jawa, dan Islam | Penulis: Irfan Afifi | Penerbit: Tanda Baca, 2019 | Tebal: xii + 222 halaman | ISBN: 978-623-90624-1-5
Buku Saya, Jawa, dan Islam karya Irfan Afifi merupakan manifestasi pemikiran yang kaya dan syarat akan laku suluk menuju proses pengolahan diri. Uraian dalam buku ini akan menjadi serumpun gagasan untuk mengenali diri, memahami proses keberlangsungan kehidupan, menumbuhkan kembali kesadaran, dan “ingin mengingatkan keberadaan ontis manusia serta tujuan teologis akhirnya selama ini ia hidup atau ber-‘ada’ di dunia ini.” (hlm. 43).
Dari membaca buku ini, kita akan mendapatkan ajaran Jawa yang oleh kebanyakan orang dianggap memiliki unsur Hinduisme, ternyata tidak. Artinya anggapan tersebut terbantahkan, seperti terlihat dari “temuan Nancy K. Florida dari 500 naskah di Keraton Kasunanan Surakarta, ternyata hanya 17 naskah yang ‘berbau’ Hinduisme. Selebihnya Islam.” (hlm. 23).
Pergulatan penulis dalam menemukan serta mengulik galur keislaman dan kejawaannya melewati proses yang memakan waktu tidak sebentar. Apalagi dengan berbagai pergulatan hati (rasa) dan pikiran yang terkadang bertolak belakang. Belum lagi ketika mendapati pandangan yang telah kelewat jauh dan sentimental menjelaskan Islam Jawa ke dalam tiga varian ala Clifford Geertz: santri, abangan, dan priyayi? Menjelaskan warisan Islam Jawa setelah terpisahnya Jawa ke dalam kerajaan besar, Kasultanan dan Kasunanan? Atau bagaimana menjelaskan Jawa yang dulu sebagai ‘aksioma kebudayaan’ kemudian mengerut menjadi ‘kejawen’?” (hlm. 27-28).
Selain menarasikan jawaban atas pertanyaan-pertayaan tersebut, buku ini barangkali mewakili pertanyaan dari kalangan yang tumbuh di lingkungan pesantren dalam masyarakat Jawa, terkait bagaimana menjadi Jawa sekaligus muslim? Apakah keduanya saling berlawanan? Ataukah bisa saling berkoeksistensi? Atau adakah kemungkinan yang lain?
Saya sepakat dengan apa yang diungkapkan Irfan Afifi dalam buku ini, bahwa Islam di Jawa bercorak (melalui) tasawuf yang berpilin dengan tradisi, sehingga jalinan antara keduanya (Islam dan Jawa) hampir-hampir tak terlihat. Corak Islam di Jawa yang demikian ini berlainan dari asumsi Harun Hadiwiyono dalam karya disertasinya, Man in The Present Javanese Mysticism (1967)—mengkaji hubungan antara Serat Wirit Hidayat Jati dan Serat Chentini—bahwa Islam di Jawa hanya menempati “lapisan tipis” dalam masyarakat (hlm. 163). Atau usaha H.M Rasyidi, mantan Menteri Agama, dalam buku Islam dan Kebatinan (1987) yang menegaskan ketidakcocokan, keberbedaan, dan bahkan pertentangan [antara] Islam dengan Jawa (hlm. 171).
Padahal, corak Islam di Jawa dapat kita lihat pada bentuk wirid yang dan tak jarang diajarkan lewat tembang atau suluk. Seperti juga pada macapat, yang di dalamnya berupa pitutur untuk manusia sejak dalam kandungan hingga masuk ke liang lahat. Mulai dari maskumambang (dalam kandungan), mijil (lahir) sinom (muda), kinanthi (yang perlu tuntunan), gambuh (menikah), dhandhanggula (merasakan pahit getir kehidupan), durma (memberi bakti baik pada masyarakat), pangkur (masa tua), yang terakhir adalah pucung, pocung (jasad yang dibungkus kain kafan).” (hlm. 32).
Mengenai mawas diri atau mulat sarira dalam buku ini dipaparkan bukan hanya semacam teoretis, melainkan dielaborasikan ke dalam sebuah makalah dengan bahasa yang santun dan tanpa menggurui. Dengan kata lain, buku ini kaya akan sikap mulat sarira seperti dalam tulisan Ngelmu Rasa (hlm. 79). Hingga segala sesuatu pasti memiliki kesejatian rasa atau “ra(h)sa” terdalamnya. Laku olah diri mengenali “ra(h)sa” terdalamnya adalah sebuah pertaruhan yang berujung pada pertemuan dengan “diri (se)jati”-Nya (hlm. 85).
Mulat berarti melihat atau mengamati ke dalam diri, sarira berarti tubuh atau badan atau wadag. Apabila diterjemahkan memiliki arti introspeksi (mengamati ke dalam) diri. Mulat sarira merupakan konsep untuk sadar, dan kembali, menemui (bukan menemukan) diri yang sejati. Kata “menemui” yang berarti bertemu dengan yang selalu ada, berbeda dengan kata “menemukan” yang berkonotasi mendapatkan dari pencarian akan sesuatu yang hilang. Sebagaimana qaul yang cukup populer dalam dunia tasawuf, “Man arafa nafsahu, faqad arafa Rabbahu”. Artinya, “Siapa yang mengenal dirinya, akan mengenal Rabb-nya”.
Tentunya banyak ragam perspektif dari makna mulat sarira. Dari konstelasi maknanya kita bisa sinau memadupadankan akal, pikiran, dan logika dalam mengevaluasi diri. Apabila dikaitkan dengan diri, semua berawal dari kesadaran untuk terus-menerus mengamati dan menerima sepenuhnya unsur yang ada dalam diri kita, yakni fisik (raga), nonfisik (hawa nafsu, pikiran, emosi, ego), dan metafisik (jiwa).
Category : resensi
SHARE THIS POST