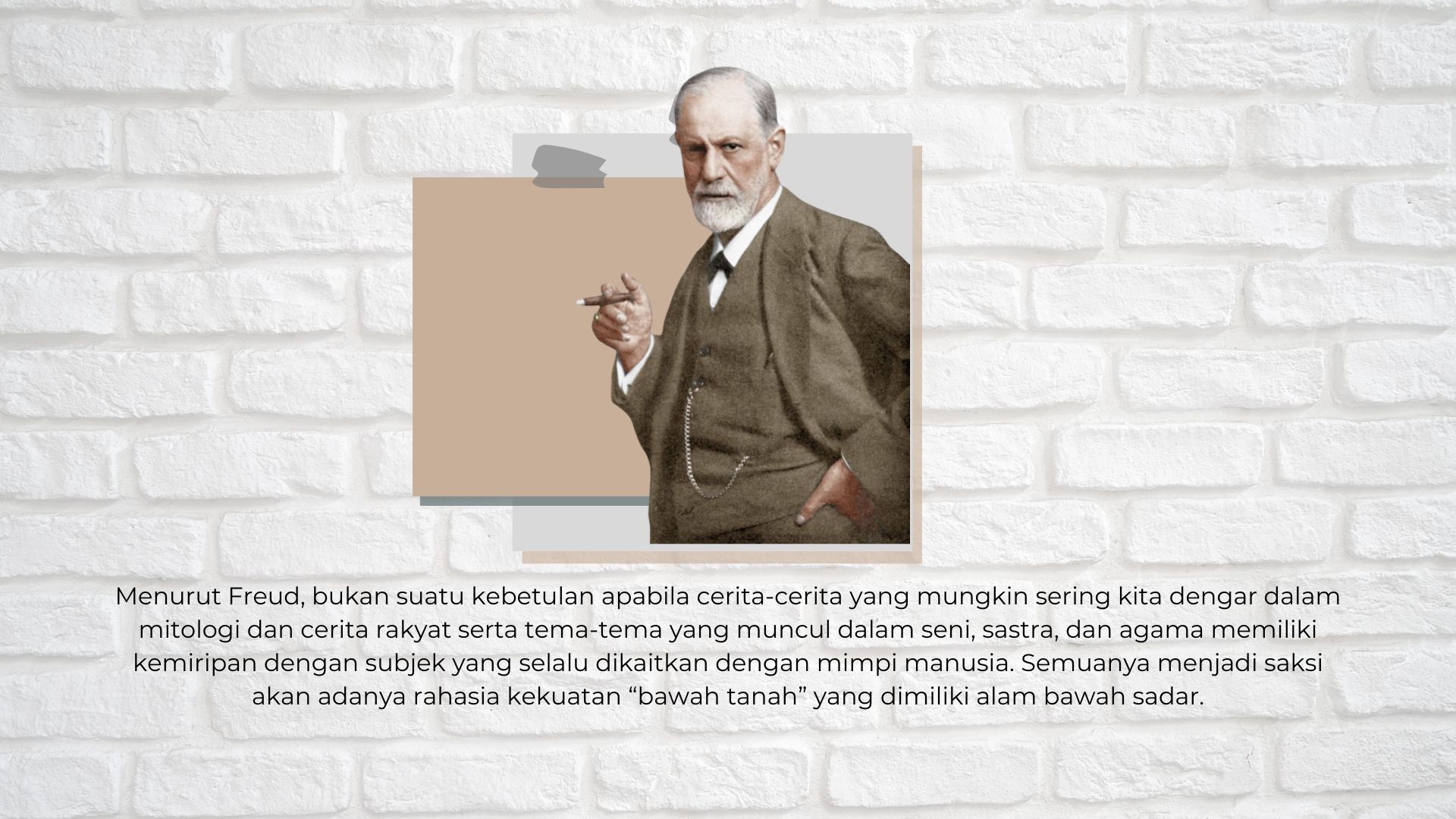Memahami Relasi Agama dan Kepribadian Perspektif Sigmund Freud
“Agama akan menjadi penyakit saraf yang mengganggu manusia sedunia,” begitu kata Sigmund Freud.
Sebagai umat beragama, boleh jujur kita pasti tersinggung dengan kutipan di atas. Namun, melihat realitas yang terjadi akhir-akhir ini, bisa jadi apa yang diungkapkan oleh Freud tersebut benar. Dalam hal ini, agama tentu dipahami berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan konteks setiap subjek. Karena itu, dalam tulisan sederhana ini, kita akan membahas sekelumit kisah Freud dan pendapatnya tentang agama.
Sigmund Freud yang cukup fenomenal itu dilahirkan pada 1856 di Moravia, bagian dari Eropa Tengah yang kemudian diambil alih kekuasaannya oleh kerajaan Austro-Hongaria.
Keluarga Freud adalah penganut agama Yahudi, namun tidak begitu taat. Meskipun sebagian besar keluarga besarnya tidak saleh, ia memahami betul isi cerita dan tulisan-tulisan Perjanjian Lama.
Ketika masih anak-anak, keluarga Freud pindah ke ibukota kerajaan Vienna, tempat Freud menetap dan bekerja hampir selama hidupnya. Sebagai seorang Yahudi, ia kemudian menyadari tidak mungkin terlalu menunjukkan kesalehan agamanya sendiri di daerah yang didominasi oleh Kristen Katolik. Sehingga ia dan keluarganya tidak banyak mengikuti cara hidup orang Yahudi, dan memutuskan untuk menyesuaikan diri dengan hari-hari besar Kristen, seperti Natal dan Paskah.
Berangkat dari latar belakang tersebut, Freud kemudian menjelaskan bahwa setiap orang paling tidak pasti memiliki pikiran sadar mengenai realitas kehidupan sehari-hari. Saat kita berbicara dengan teman kita, menulis artikel, ngopi, atau mungkin membaca buku, menurut Freud kita tidak hanya menggunakan pikiran, namun juga sadar dan tahu bahwa kita sedang menggunakannya.
Lebih lanjut Freud mengungkapkan bahwa kita juga tahu di bawah permukaan kesadaran kita terdapat ide, konsep, dan gagasan lain diinterpretasikan sebagai alam pra-sadar. Dalam artian, memori, ide, niat-niat yang saat itu memang belum kita sadari, namun bisa dipanggil kapan saja saat diperlukan. Sebagai contoh umur orang tua kita, hidangan makan malam kemarin, atau mungkin ke mana niat kita untuk jalan-jalan di akhir pekan.
Meskipun dalam waktu tertentu, pikiran kita tidak bisa menyadarinya, namun pikiran dengan mudah bisa mendapatkannya kembali saat diperlukan. Karena itu, Freud menjelaskan mengenai pengalaman di alam mimpi sebagai sesuatu yang berbeda dari aktivitas di alam sadar maupun pra-sadar. Ketika itu, kita menggunakan lapisan yang berasal dari wilayah lain dari pikiran kita, yang cukup dalam, tersembunyi, banyak, dan cukup kuat.
Hal itulah yang kemudian oleh Freud disebut sebagai alam bawah sadar. Ia bagaikan inti sebongkah es, bagian terdalam dari diri yang tanpa disadari perannya cukup penting dalam kehidupan manusia. Alam bawah sadar merupakan sumber dorongan jasmaniah kita yang paling dasar, misalnya keinginan untuk makan, minum, atau aktivitas seksual. Sehingga bergabungnya alam bawar sadar dengan keinginan ini akan menciptakan ikatan luar biasa dari ide, kesan, dan emosi.
Pasalnya, ide, kesan, dan emosi-emosi dapat dihubungkan dengan segala hal yang mungkin pernah dialami, dilakukan atau yang ingin dilakukan seseorang semenjak hari pertama dilahirkan sampai saat akhir hayatnya. Dalam hal ini, alam bawah sadar tetap ada dan memberikan pengaruh secara tidak langsung yang cukup dahsyat dalam hal apa pun yang kita pikirkan dan lakukan.
Jadi, menurut Freud, bukan suatu kebetulan apabila cerita-cerita yang mungkin sering kita dengar dalam mitologi dan cerita rakyat serta tema-tema yang muncul dalam seni, sastra, dan agama memiliki kemiripan dengan subjek yang selalu dikaitkan dengan mimpi manusia. Semuanya menjadi saksi akan adanya rahasia kekuatan “bawah tanah” yang dimiliki alam bawah sadar.
Setelah mengembangkan ide dasarnya mengenai psikoanalisa dan alam bawah sadar, Freud menempatkan agama sebagai objek studi lanjutan yang menantang. Bagaimana tidak menantang? Freud sendiri merupakan sosok penolak yang cukup kompleks terhadap agama. Bahkan, para penulis biografi yang cukup dekat dengan Freud, mengungkapkan dengan terus terang bahwa Freud menjalani hidup dari awal sampai akhir hayatnya sebagai orang yang benar-benar ateis.
Freud diceritakan tidak atau lebih tepatnya belum menemukan satu pun alasan untuk percaya kepada Tuhan. Sehingga ia menganggap ritual keagamaan tidak memiliki arti dan manfaat apa pun dalam kehidupan ini. Freud bahkan cukup yakin bahwa ide-ide agama tidak datang dari Tuhan Yang Esa atau tuhan-tuhan yang lain, lantaran tuhan-tuhan itu memang tidak ada dan juga bukan berasal dari suara hati dalam perenungan mengenai dunia yang biasanya membawa pada kebenaran.
Dalam hal ini, Freud menyimpulkan bahwa perilaku orang beragama mirip dengan perilaku pasien neurotisnya. Misalnya, keduanya sama-sama menekankan bentuk-bentuk seremonial dalam melakukan sesuatu, dan sama-sama akan merasa bersalah apabila tidak melakukan ritual-ritual tersebut dengan sempurna. Dalam kedua kasus tersebut, ritual-ritual yang dilakukan juga diasosiasikan dengan represi terhadap dorongan dasar.
Gangguan psikologis biasanya muncul dari ketertekanan hasrat seksual, sedangkan dalam agama sebagai akibat ketertekanan diri, yakni pengontrolan terhadap insting-ego. Jadi, apabila represi seksual terjadi dalam gangguan obsesi mental diri seseorang, maka agama yang dipraktikkan oleh lebih banyak kalangan bisa dikatakan sebagai gangguan obsesi mental secara universal. Maka dari itu, Freud memandang bahwa perilaku orang beragama selalu mirip dengan penyakit jiwa.
Belajar dari beberapa pandangan Freud di atas, kita bisa memahami bahwa sedari awal Freud sudah menyatakan bahwa dirinya memang tidak tertarik dengan persoalan-persoalan agama. Maka dari itu, kita tidak bisa begitu yakin dengan penjelasan-penjelasannya secara utuh. Meskipun kita berusaha sekuat tenaga untuk menyatukan berbagai pandangan Freud, namun usaha itu tampaknya juga akan sulit menemukan titik terang. Selain itu, teori-teori Freud sebagai ilmu hanya bisa untuk sekadar menjadi salah satu pisau analisis untuk menjelaskan agama, bukan sebagai penentu kebenaran agama.
Terlepas dari itu semua, sebagai umat beragama kita tentu memiliki pandangan lain soal relasi agama dan kepribadian manusia. Sebagai muslim yang kebetulan bersuku Jawa, saya memahami bahwa agama merupakan ageman (pegangan) dalam menyelami samudera hidup dan kehidupan. Karena itu, sedikit banyak kepribadian kita pasti akan diselaraskan dan diadaptasikan agar selaras dengan ajaran agama.
Lebih jauh, dalam sufisme juga dijelaskan setidaknya tiga tipe kepribadian.
Pertama, muthmainnah, yakni kepribadian yang didominasi oleh kalbu, yang dibantu oleh daya akal dan daya nafsu. Kedua, lawwamah, yakni kepribadian yang didominasi oleh daya akal, yang dibantu oleh daya kalbu dan daya nafsu. Ketiga, amarah, yakni kepribadian yang didominasi oleh daya nafsu, yang dibantu oleh daya akal dan daya kalbu.
Barang siapa bisa mengintegrasikan antara kalbu, akal, dan nafsu dengan baik, maka perilaku yang keluar dari manusia tersebut juga akan baik. Sehingga diharapkan bisa selaras dengan misi utama Rasulullah Saw, yakni sebagai penebar rahmat dan penyempurna akhlak manusia.
Category : keilmuan
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan
- Buku Ngaji Pascakolonial