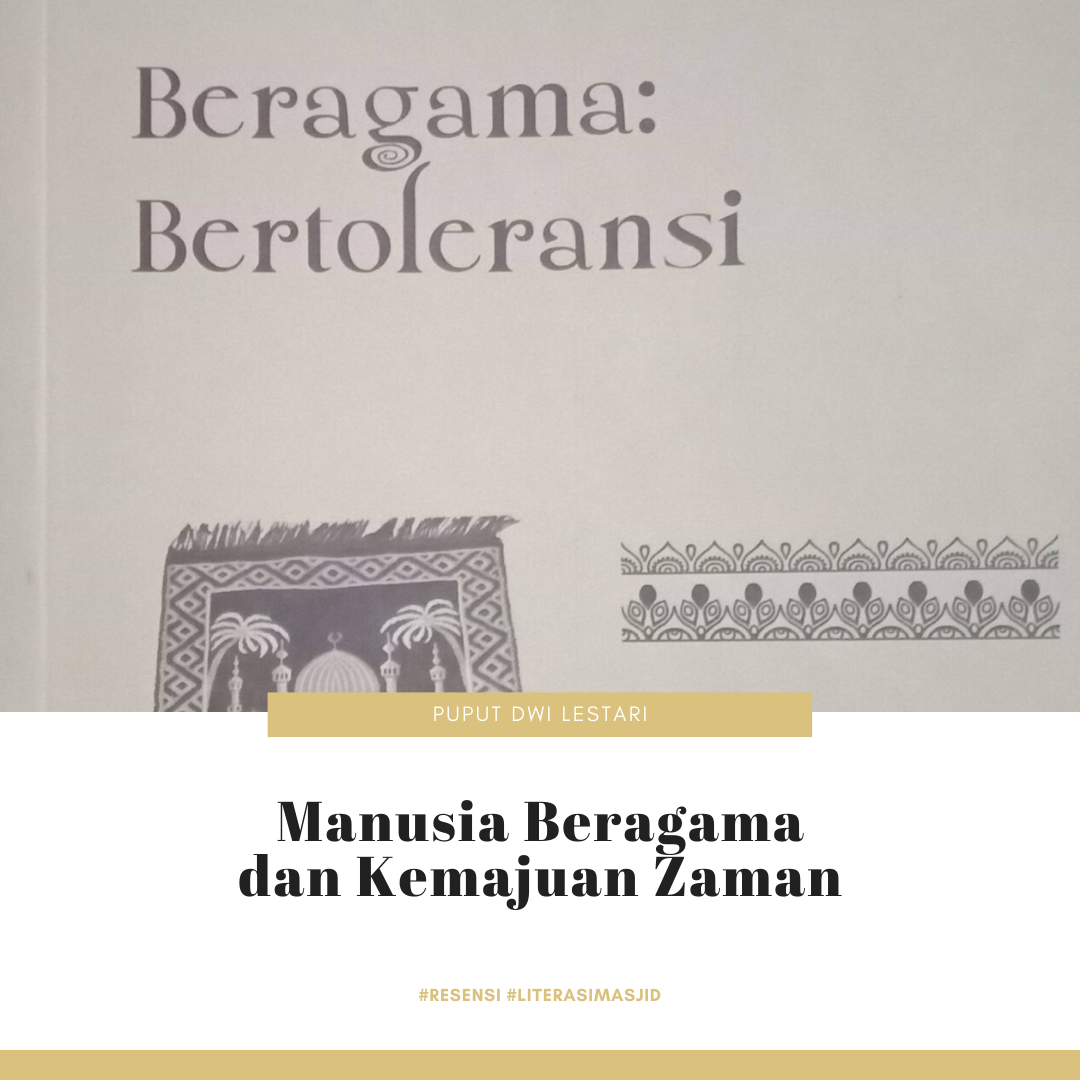Manusia Beragama dan Kemajuan Zaman
Judul: Beragama: Bertoleransi | Penulis: Muhammad Milkhan | Penerbit: Bilik Literasi, 2019 | Tebal: 98 halaman | ISBN: 978-623-7258-18-6
Kata “beragama” dan “bertoleransi” seakan menjadi dua kata yang tak dapat dipisahkan. Pembicaraan menyangkut tentang agama sering diiringi dengan toleransi atau dapat kita dengar ungkapan “toleransi beragama”. Toleransi sendiri terus didorong sebagai resep mujarab mengatasi persoalan keagamaan, sehingga dapat mampu menyembuhkan penyakit keagamaan di era sekarang ini yang secara pemahaman lebih ekstrim kanan (sikap eksklusif) dan cenderung tidak menghargai keyakinan pemeluk agama lain.
Berkaitan dengan kenyataan di atas, buku karya Muhammad Milkhan berjudul Beragama: Bertoleransi—diterbitkan Bilik Literasi, Karanganyar—menarik untuk dibaca. Buku ini merupakan kumpulan esai yang berangkat dari keadaaan keberagamaan di lingkungan sekitar penulis. Terlihat bahwa penulis menghadirkan realitas disekelilingnya itu baik menyangkut masalah politik, ekonomi, adat, budaya, maupun agama ke dalam tulisan.
Seperti halnya Milkhan, kita pun merasa khawatir dengan perubahan zaman yang begitu cepat akibat kecanggihan teknologi. Banyak orang terbuai dengan kemudahan dan kecanggihan teknologi, sehingga lebih banyak melakukan hal-hal yang kurang berfaedah ketimbang melakukan kegiatan yang bernilai ibadah. Misalnya, saat ketika terdengar suara azan dan tindak menyegerakan salat. Milkhan menulis, “Saat azan berkumandang orang mulai acuh. Azan dipandang hanya sebagai bergantinya waktu salat semata”. (hlm. 20-21). Padahal, “Azan adalah pengingat akan Tuhan Yang Maha Esa yang mencintai keindahan dan yang lima kali sehari menyambut mereka menjawab panggilan indah untuk bertemu Yang Maha Indah”. (hlm. 19-20). Kenyataan yang didapati, kumandang azan terdengar malah tidak mengubah perilaku kita; dari anak-anak sampai orang dewasa lebih asik bermain handphone pintar ketimbang menyegerakan salat.
Menurut Milkhan, bagaimanapun kemajuan zaman yang melenakan ini harus tetap disyukuri namun juga harus diimbangi dengan kesadaran beragama yang baik. Sulit dimungkiri telah terjadi perubahan dalam cara kita menjalani kehidupan maupun motif beragama masyarakat di era teknologi sekarang ini. Misalnya, dibalik motivasi untuk membaca Al-Quran di bulan Ramadhan, ada rupanya dilakukan demi mendapatkan hadiah kuota internet, bukan dengan niatan membaca Al-Quran secara ikhlas semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT.
“Sekarang ini Al-Quran telah digunakan untuk kepentingan pribadi demi merengkuh keuntungan duniawi semata. Lebih dalam lagi kita dapat membuat tafsiran bahwa Al-Quran bukan lagi kitab suci yang pantas dimuliakan. [Apa] yang pantas dimuliakan adalah kuota data internet 12 GB yang menjadi tajuk utama dalam model promosi…”. (hlm. 40-41).
Padahal, “Al-Quran memiliki kedudukan yang tinggi sebagai sumber hukum Islam, setiap umat Islam diharapkan untuk tidak memanfaatkan Al-Quran hanya untuk keuntungan duniawi.” Milkhan mengutip dari M. Quraish Shihab, “Betapa pentingnya membaca Al-Qur’an dengan penuh kesungguhan, sebab Al-Quran merupakan bacaan sempurna dan tidak ada satu pun bacaan sejak manusia mengenal baca tulis lima ribu tahun lalu yang dapat menandingi Al-Qur’anul karim”. (hlm. 41).
Dari kasus di atas dapat dipahami, ternyata membaca Al-Quran tidak lagi dianggap sebagai laku ibadah membaca yang sakral. Manusia pembacanya pun telah mengalami pengaburan dalam memaknai kata membaca itu sendiri. “Manusia modern cenderung memaknai membaca hanya sebuah ritual untuk merengkuh keuntungan material semata. Terlebih Al-Quran yang menjadi objek bacaan, terkesan hanya dijadikan syarat menggapai hadiah. Padahal, apabila kita dapat memaknai kata membaca sesuai KBBI bahwa membaca memiliki arti ‘melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis’. Maka apabila ditarik dalam kasus membaca Al-Quran dengan iming-iming hadiah, tentu sulit membayangkan si pembaca akan benar-benar tulus melihat serta memahami bacaan yang sedang ia baca. Iming-iming hadiah terkesan lebih menggiurkan untuk dijadikan motivasi utama para pembaca untuk membaca Al-Quran”. (hlm. 43).
Dengan mudah, kita pun akan menjumpai banyak contoh yang sama dalam laku ibadah lainnya. Hal-hal semacam ini—motif ekonomi maupun kalkulasi dalam beribadah—menjejak di era melinial, apabila dibiarkan akan memperburuk perilaku kita dalam setiap menjalankan perintah agama. Akibatnya juga akan dijumpai umat yang materialistik dan pemalas, enggan melakukan perintah agama apabila tidak ada iming-iming hadiah.
Selain permasalahan iming-iming hadiah sebagai motivasi seseorang dalam melakukan ibadah, umat beragama dihadapkan pada masalah intoleransi beragama. Apalagi di era teknologi informasi, basis agama mudah menjadi permasalahan yang sangat sensitif. Sedikit perbedaan saja dapat menjadi memicu terjadinya saling ejek, permusuhan maupun kerusuhan. Terkait agama juga, “Kerap dijadikan dalih kepentingan segelitir golongan, sehingga agama dianggap sebagai penghambat kemajuan manusia dan mempertinggi fanatisme semata tanpa memiliki efek yang positif bagi manusia. Sifat fanatisme terhadap agama hanya melahirkan tindakan tidak toleran, pengacuhan, pengabaian, takhayul, dan kesia-sian”. (hlm. 35).
Menurut Milkhan—mengutip Thomas E O’dea, “Agama seharusnya menjadi pemersatu aspirasi manusia yang paling sublim, sebagai sumber tatanan masyarakat, dan perdamaian batin individu, sebagai sesuatu yang membuat manusia lebih beradab”. Dalam rangka mengupayakan idealitas tersebut, Zamir Hassan (seorang aktivis sosial sekaligus pendiri Muslims Against Hunger, sebuah jaringan komunitas relawan yang membatu orang-orang yang membutuhkan makanan) melakukan dialog senyap lintas iman.
“Zamir Hasan telah melakukan dialog yang paling efektif dengan melakukan dialog lintas iman sekaligus dialog multikultur melalui makanan tanpa memandang suku, ras, dan agama. Siapa pun berhak menerima donasi makanan. Dialog senyap lintas iman ini dirasa sangat cukup manjur dan efektif untuk memupuk toleransi antar umat menusia tanpa memandang asal-usul agar hidup rukun dan saling mengasihi”. (hlm. 33).
Dialog semacam inilah yang dibutuhkan untuk meredam masalah intoleransi beragama. Dialog agama, sebenarnya bukanlah dialog dengan memberikan penjelasan teologis, melainkan aksi nyata meleburkan diri ke dalam realitas dan tatanan sosial yang tidak adil—jalan mengakhiri kerusuhan sosial yang bernuansa agama, maupun bersama-sama membangun sikap kritis, serta saling mengasihi sebagai manusia yang beragama.
Selanjutnya hal yang disoroti oleh Milkhan dalam buku tersebut mengenai masalah adat budaya masyarakat Indonesia. Apabila melihat jumlah penduduk Indonesia, mayoritas beragama Islam, setidaknya kita akan memiliki pemahaman bahwa Indonesia adalah negara yang mencerminkan adat budaya ke-muslim-an (‘islami’) berikut kondisi kehidupan dan tempat tinggal yang seharusnya kondusif, aman, dan sejahtera. Namun, pada kenyataannya kehidupan belum mencerminkan kondisi hal yang demikian itu, banyak lokasi tinggal (seperti diperkotaan) yang masih jauh dari harapan penghuninya: tempat singgah yang nyaman, rasa aman, dan kebahagiaan hidup. Lokasi tinggal seperti diperkotaan justru terindikasi gagal memenuhi kebutuhan warganya, dan sebaliknya tak luput terjadi kemacetan, penggusuran, tingkat kriminalitas yang tinggi sebagai ciri banyak kota di Indonesia.
Berbanding terbalik—seperti ditulis Milkhan—dengan pengalaman Pak Joko yang sudah puluhan tahun tinggal di Minesota, sebuah negara bagian di Amerika. Hampir semua rumah tidak ada yang berpagar, memiliki halaman depan dan belakang yang bersih dan terawat, serta mobil-mobil yang terparkir rapi disepanjang jalan, dan warga tidak merasa waswas akan tindak kejahatan. Pak Joko justru lebih mudah menemukan kehidupan yang ‘islami’ di Amerika yang notabene mayoritas penduduknya bukan beragama Islam, ketimbang menemukan kehidupan yang ‘islami’ di Indonesia yang notabene penduduk mayoritasnya beragama Islam. Kondisi ini menjadi suatu realitas yang sangat bertolak belakang. “Masyarakat Indonesia yang terkenal ‘agamis’ belum mampu berperan aktif dalam proses pembangunan ke arah yang lebih baik. Kota sebagai representasi dari kemajuan sebuah bangsa, terkesan masih jauh dari hasil yang patut kita banggakan kepada khalayak umum”. (hlm. 49).
Dari buku Beragama: Bertoleransi memberikan gambaran kepada kita bahwa masih begitu banyak hal yang perlu diperbaiki dalam sikap keberagamaan kita sebagai umat Islam. Begitu sentralnya peran agama dalam membawa perubahan di segala sendi kehidupan. Era industri 4.0 atau yang biasa disebut era revolusi industri atau biasa juga disebut era milenal, memang memberi pengaruh yang begitu dahsyat, sampai pada sikap keberagamaan seseorang. Buku ini begitu jelas memberikan gambaran bagaimana motivasi beragama seseorang telah mengalami pergeseran yang begitu signifikan.
Bagaimanapun kemajuan zaman tak dapat ditolak, bisa jadi anugerah atau musibah yang keduanya tetap untuk disyukuri, sementara sikap keberagamaan yang toleran terus diupayakan agar tetap lestari.
Category : resensi
SHARE THIS POST