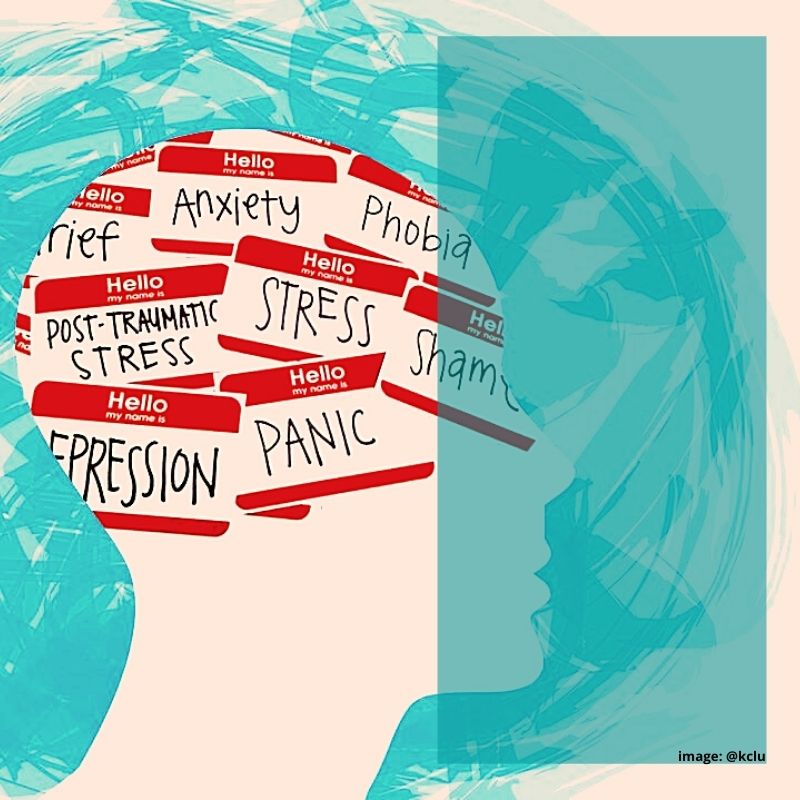Filsafat untuk Bahagia
Di fase pandemi yang belum berkesudahan ini, rasa-rasanya orang galau semakin meningkat. Jelasnya, galau yang kita rasakaan saat ini sangat berbeda dengan galau yang seperti dialami oleh Albert Einstein dengan teori relativitasnya, atau seperti Isaac Newton ketika melihat apel jatuh ke bawah dengan terheran-heran dan butuh galau yang begitu panjang hingga melahirkan teori gravitasi.
Jelasnya lagi, galau kita tidak seperti Nabi Ibrahim ketika merenungkan penciptaan bumi dan seisinya, setiap waktu dalam hidupnya, Nabi Ibrahim mencari Tuhannya. Mulai dari menebak matahari sebagai Tuhan, bulan, hingga siang dan malam, akhirnya menemukan bahwa Allah-lah yang menciptakan bumi dengan segala isinya.
Galaunya kita saat ini tanpa kejelasan mau melakukan apa, mau melangkah ke mana, seperti diombang-ambing. Tidak sedikit galau karena di PHK, beban sekolah yang semakin meningkat, padahal uang saku juga tidak meningkat. Sedangkan kebutuhan untuk kuota internet semakin besar.
Bisakah filsafat menjawab kegalauan kita hari ini? Kalau filsafat kita maknai sebagai pandangan hidup, justru dengan belajar filsafat kita akan memiliki pandangan sebagai pedoman dalam melangkah dalam setiap tapak perjalanan.
Rasa galau memang tidak dilepaskan dari diri kita, ia menjadi bagian diri kita. Namun, menyerah dan berputus asa akibat kegalauan adalah bukti kebodohan.
Kebutuhan kita hanya sedikit, makan, minum itu sudah cukup. Namun, keinginan yang lain-lain sebenarnya yang membuat seseorang menjadi galau. Keinginan untuk membeli mobil, bahagia dengan banyak harta, jalan-jalan ke luar negeri. Akhirnya, bila semua itu tidak tercapai, kekecewaan itu datang menghampiri, galau jadinya.
Pada suatu kesempatan mendengar ceramah K.H. Ahmad Bahauddin Nursalim (Gus Baha), ngendikan, “Semakin sedikit keinginan yang kita miliki, semakin sedikit pula rasa kecewa yang akan kita alami”. Semakin besar harapan yang dimiliki seseorang, sebanding dengan besarnya kecewa yang akan di dapatkan. Apalagi pengharapan itu disandarkan kepada manusia. Bukankah sudah termaktub dalam ajaran Islam bahwa hedaknya kita hanya berharap kepada-Nya, bukan kepada yang lain.
Selain kegalauan, bahagia merupakan sesuatu yang dapat kita raih. Rasa syukur atas apa yang kita miliki menjadi kunci kebahagiaan. Kita tetap bisa hidup, meski tidak kaya, menghirup udara secara gratis, minum kopi, tidak dimarahi oleh orang tua, masih bisa tertawa. Itu juga bagian dari kebahagiaan yang jarang kita syukuri keberadaannya. Sementara di luar sana masih banyak orang kaya tetapi tidak bisa makan nasi telor lantaran kolesterol, banyak orang bermobil tetapi terlilit hutang, dikejar-kejar dep collector.
Disinggung pula oleh Gus Baha dalam sebuah pengajiannya, “Selayaknya hamba, kita seharusnya bisa mensifati Tuhan dengan hal-hal baik. Misalnya, bersyukur karena masih bisa makan, masih bisa merokok”. Sederhananya, rasa galau itu sebenarnya hanya lahir dalam diri kita sendiri. Perihal kebahagiaan, juga sumbernya berasal dari kita sendiri. Sebab mindset, kehendak diri, dan kontrol diri dijalankan oleh diri seseorang, tanpa ada kehendak orang lain yang bisa mengubah keduanya.
Filsafat kebahagiaan Stoa
Sejalan dengan ini, menurut kaum Stoa, kebahagiaan ialah saat tidak adanya atau tidak timbulnya emosi yang negatif. Atau dibahasakan lain yakni “Bahagia jika kita tidak merasa cemas, sedih, dan takut”. Seorang filosof Stoa bernama Epictetus mengatakan, “It is not things that disturb us, but our opinion of them”.
Maksud perkataan Epictetus ialah seringkali perasaan galau, takut, cemas, terganggu terhadap suatu hal, itu timbul karena opini kita sendiri. Bagi kaum Stoa, emosi negatif itu timbul karena nalar yang sesat, bukan disebabkan oleh peristiwa eksternal. Marcus Aurelius seorang kaisar dan juga filosof Stoa mengatakan, “Jika kamu bersusah hati karena hal-hal eksternal, kesusahan itu datangnya bukanlah dari hal tersebut, tetapi dari opinimu sendiri mengenai hal itu. Dan kamu memiliki kemampuan mengubah opini itu kapan saja”. Hal-hal eksternal yang dimaksud adalah seperti kekayaan, reputasi, tahta, dan lain-lain. Menurut kaum Stoa, opini kita berada di dalam otak dan hanya kita sendiri yang dapat mengendalikannya.
Pada dasarnya kaum Stoa mengajarkan dikotomi kendali menjadi dua hal. Pertama, hal-hal yang bukan di bawah kendali kita, yakni tindakan orang lain, opini orang lain, reputasi, kekayaan, kondisi tubuh, segala sesuatu yang di luar pikiran dan tindakan kita seperti cuaca, gempa bumi, dan peristiwa alam lainnya. Kedua adalah hal-hal yang di bawah kendali kita, yaitu pertimbangan, opini, persepsi, tujuan hidup, dan segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita. Karenanya, dalam setiap diri individu untuk mampu menerima kenyataan bahwa banyak hal-hal di luar sana yang senantiasa siap membuat kita kecewa.
Kaum Stoa mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kendalikan. Namun, bukan berarti harus menghindari hal-hal yang berada di luar kendali, justru sebaliknya, menghadapinya dengan menerapkan kebijakan.
Filsafat Stoa mengenai kebahagiaan juga mengajarkan individu untuk memilih respons atau tindakan seperti apa yang sebaiknya diambil. Dengan catatan, respons tersebut adalah hasil penggunaan nalar yang sebaik-baiknya dengan prinsip bijak, adil, menahan diri, dan berani. Dengan begitu, kita mampu menghilangkan emosi negatif melalui kendali pikiran kita sendiri.
Filsafat Stoa juga mengajarkan kita sebagai manusia untuk bisa melakukan regulasi emosi dalam setiap peristiwa yang terjadi, seperti kondisi pandemi saat ini. Emotion regulation bagian dari kecerdasan emosional yang harus dimiliki seseorang. Sebab hal ini akan menjadikan seseorang bisa bertindak manusiawi dalam menjalankan relasi antarsesama.
Dalam tradisi ilmu tasawuf, definisi bahagia, seperti yang disampaikan Imam al-Ghazali, dalam karyanya Ihya Ulumiddin, merupakan sebuah kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah SWT. Kebahagiaan itu adalah manifestasi berharga dari mengingat Allah.
Definisi kebahagian juga dicoba diuraikan oleh para pemikir muslim. Seperti Syed Muhammad Naquib Al-Attas, mendefinisikan kebahagiaan sebagai kesejahteraan yang bukan hanya lahiriah. Kebahagiaan tidak merujuk pada ketenangan pikiran. Ini adalah keyakinan diri akan hakikat segala yang ada.
Untuk memperoleh kebahagiaan seharusnya kita merujuk kepada diri kita sendiri untuk selalu mensyukuri segala anugerah Allah yang diberikan dalam kuantitas yang sedikit ataupun banyak. Sejatinya Allah Maha Mengetahui atas apa yang kita butuhkan. Jika kita sudah melatih diri untuk bersyukur, menerima segala pemberian Allah dengan melakukan berbagai usaha yang maksimal, mudah-mudahan kebahagiaan itu akan selalu mengiringi kita.
Category : filsafat
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Alam Pikiran Jawa-Islam: Filologi, Simbol, dan Struktur Babad Kraton
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan