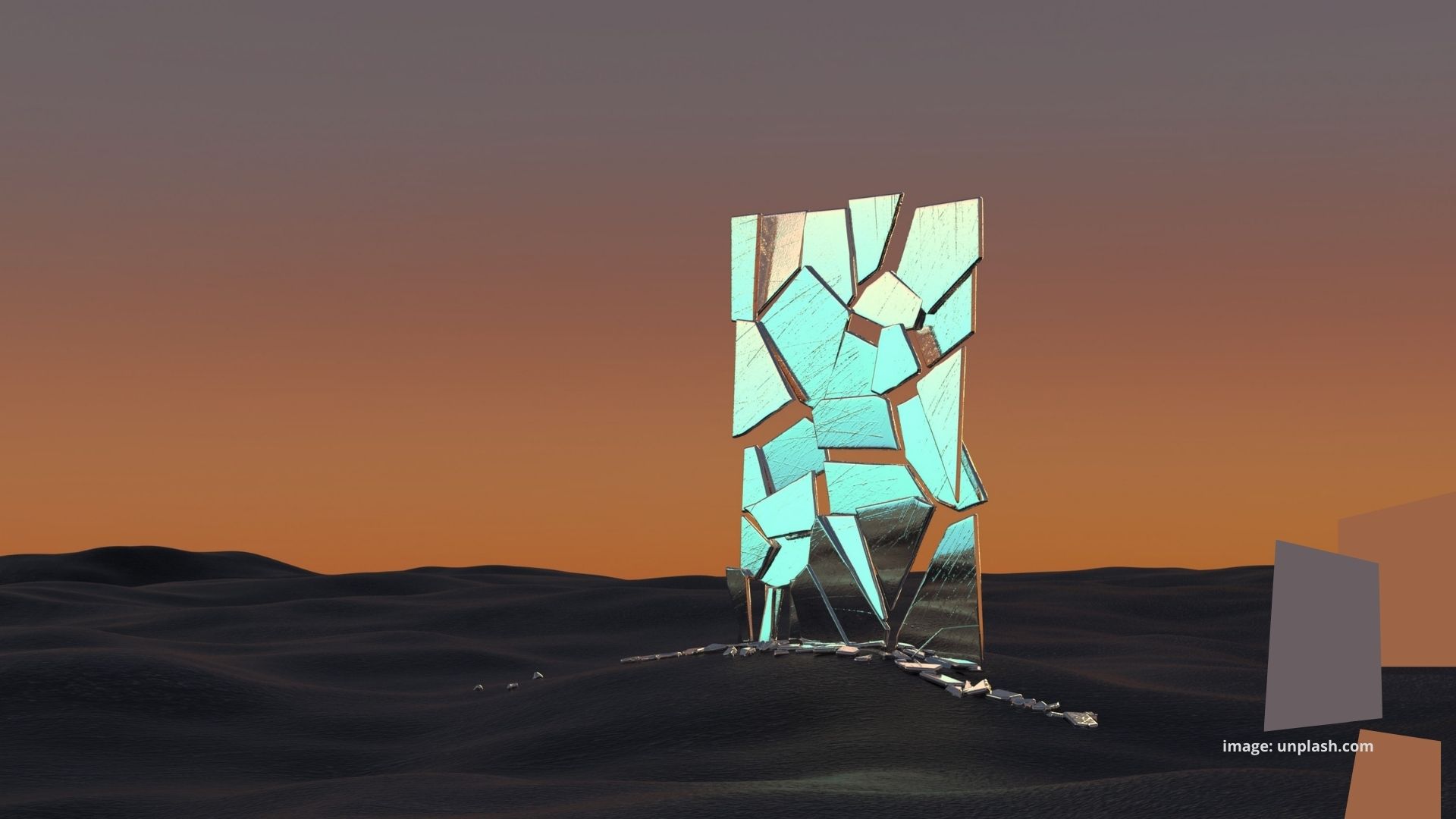Etis Sejak dalam Pikiran
Kehidupan menuntut kita untuk senantiasa memilih atau mengambil keputusan dari berbagai opsi yang tersedia. Sebagian tuntutan untuk memilih terlihat mudah, sebagian yang lainnya susah. Sebab hidup bukan saja menuntut pilihan yang rasional atau tidak, tetapi juga pilihan yang sesuai etika. Dari sanalah timbul masalah yang dinamakan dilema moral (bisa juga disebut dilema etis).
Dilema moral sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dilema moral adalah situasi yang menghadapkan seseorang pada dua pilihan atau lebih yang sulit. Kesulitan itu disebabkan pilihan yang satu akan melanggar suatu norma tertentu, sedangkan pilihan lain juga akan melanggar norma yang lain pula. Seperti buah simalakama, pilihan-pilihan yang tersedia kerap sama-sama membawa konsekuensi kerugian atau pelanggaran norma-moral tertentu.
Contohnya seperti yang kita hadapi di masa pandemi. Banyak dari kita, terutama yang profesinya tidak bisa dijalankan dari rumah, yang menghadapi dilema: menjaga kesehatan dengan isolasi di rumah, atau tetap bekerja mencari nafkah?
Jika kita memilih tetap bekerja di luar rumah demi mendapatkan rezeki, pilihan tersebut memperbesar kemungkinan kita terkena virus yang mengancam nyawa. Namun, jika memilih untuk berdiam diri di rumah, besar kemungkinan kita akan kehilangan pemasukan finansial, yang akhirnya juga dapat mengancam nyawa—karena kemiskinan dan kelaparan.
Apabila hanya menggunakan rasio, dari dua pilihan tersebut, apa pun yang kita pilih sama-sama masuk akal. Akan tetapi, jika kita menggunakan pendekatan etik, mana pilihan yang lebih etis? Itu kasus dilema moral pada ranah individual. Kalau kita sudah berkeluarga, tentu kasusnya akan lebih rumit lagi. Lebih-lebih apabila sudah berkaitan dengan masyarakat luas. Kasus dilema moral yang punya dampak kepada orang lain (ranah sosial) yang lebih pelik itu misalnya seperti ini:
Anggaplah ada seseorang (atau bisa juga kelompok) yang dilabeli berpaham radikal, sesat, atau apa pun yang bertendensi negatif. Lalu karena kekhawatiran kita terhadap aktivitasnya, kita pun memboikot atau melarang kegiatan-kegiatannya. Pada titik itulah muncul dilema moral.
Bukankah tindakan kita melarang seseorang atau kelompok tersebut berarti kita memberangus hak mereka untuk bersuara? Bagaimanapun, mencabut kebebasan berekspresi orang lain adalah tindakan yang tidak sesuai dengan hak asasi, dan karenanya bisa dinilai menyalahi moral. Namun, jika kita biarkan, sementara kita tahu (atau kita duga) ide-idenya berbahaya, bukankah kita sedang membahayakan keselamatan publik?
Atau contoh semisal lainnya ketika kita melihat pengemis atau pengamen di jalanan. Kita akan dihadapkan pada dua pilihan yang mengandung dilema. Pada satu sisi kita ingin memberi atau bersedekah, tetapi di sisi yang lain terdapat aturan pemerintah yang melarang memberikan uang kepada mereka. Mana yang harus dipilih: bermurah hati dengan bederma untuk menolong orang yang membutuhkan atau menaati pemerintah sebagai wujud ketaatan warga negara?
Karena itu, untuk menghadapi kasus-kasus dilema semacam contoh-contoh tersebut, kita perlu memiliki kemampuan penalaran atau berpikir etis (ethical thinking) supaya bisa melahirkan perbuatan yang sesuai dengan etika (ethical action). Mengetahui alasan mengapa kita melakukan suatu perbuatan sering kali lebih penting daripada perbuatan itu sendiri.
Dengan demikian, mengukur atau menilai tingkat moralitas seseorang tidak cukup hanya dengan melihat perilaku moral yang tampak saja (hasil), melainkan mesti pula diketahui penalaran-penalaran yang mendasari keputusan perilaku moral tersebut (proses).
Bagi diri kita pribadi, kecakapan berpikir etis menjadikan kita bisa berpikir lebih jernih, penuh pertimbangan, tidak hitam-putih, dan—tentu saja—akan menghindarkan kita dari rasa bersalah karena berbuat sesuatu yang tidak bermoral—meskipun perbuatan itu benar secara logis.
Dalam lingkup sosial, kecakapan berpikir etis membuat kita bisa menjadi lebih bijaksana, toleran, dan tidak mudah menuduh orang lain (atau perbuatannya) tidak bermoral, buruk, atau bahkan jahat. Pada contoh memboikot seseorang yang radikal di atas, kemampuan berpikir etis membuat kita lebih berhati-hati sebelum melabeli demikian.
Kita perlu menalar lebih jauh: apakah benar mereka radikal? Jangan-jangan kitalah yang salah paham atau belum memahami mereka sepenuhnya? Serta, bukankah ada kebenaran dan kebaikan yang bersifat subjektif? Sehingga kita tidak boleh memaksakan standar kebenaran pribadi kepada orang lain.
Lantas, bagaimana caranya mengolah kemampuan berpikir yang etis sehingga dapat melahirkan perbuatan yang bermoral?
Hal itu berkaitan dengan pendekatan atau mode berpikir yang kita pakai. Secara umum, pendekatan dalam berpikir etis itu antara lain: utilitarianistic, virtue, common good, justice/fairness, dan rights approach.
Utilitarianistic approach. Rumusnya sederhana: mengambil keputusan yang memberi manfaat (utilitas) paling besar kepada sebagian besar (orang) yang terlibat. Ketika kita dihadapkan pada kasus dilema moral, yang menjadi pertimbangan kita sebelum memilih adalah siapa saja yang terlibat atau akan terdampak oleh keputusan tersebut, dan kalkulasi keuntungan-kerugian yang akan diterima mereka yang terlibat.
Pendekatan ini mengisyaratkan “pengorbanan”. Entah “pengorbanan” kepentingan pribadi demi kepentingan publik, maupun “pengorbanan” kepentingan sekelompok kecil untuk membawa manfaat kepada kelompok yang lebih besar.
Contohnya kasus bekerja saat pandemi di atas. Apabila kita menggunakan pendekatan utilitarianistic, maka pilihan yang lebih etis adalah berdiam diri di rumah. Keputusan itu membawa lebih banyak manfaat kepada lebih banyak orang, yakni mencegah penyebaran virus. Perkara kemungkinan kita tidak memiliki pemasukan finansial, itu adalah tantangan yang mesti kita selesaikan—sekaligus “pengorbanan” demi menjaga kesehatan masyarakat luas.
Virtue approach. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan karakter. Karakter baik atau nilai kebajikan apa yang ingin kita miliki atau pertahankan, itulah yang akan menjadi patokan berpikir kita sebelum mengambil tindakan moral.
Misalnya, jika kita menginginkan menjadi seseorang yang jujur, kita akan senantiasa mengedepankan kejujuran atas setiap keputusan-tindakan kita. Sekalipun kejujuran itu membawa anasir-anasir yang kurang baik atau merugikan, hal itu tidak akan menggoyahkan prinsip kejujuran yang kita utamakan.
Common good approach. Pendekatan ini sesungguhnya mirip dengan pendekatan utilitaristis. Hanya saja, pendekatan ini menekankan keputusan yang lebih moderat. Dengan kata lain, sebisa mungkin mengakomodasi kebaikan bersama (sebanyak-banyaknya orang/pihak) tanpa ada yang “dikorbankan”. Tujuan akhirnya adalah memberikan kepuasan kepada semua orang.
Justice/fairness approach. Sesuai namanya, pendekatan ini mengutamakan keadilan dari setiap keputusan moral yang diambil. Saat kita berhadapan dengan kasus dilema moral, hal yang meski kita pikirkan adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan pihak yang terlibat.
Contohnya, bayangkan kita sedang duduk di angkutan umum. Di sana ada orang tua dan ibu yang membawa bayi yang tidak mendapatkan tempat duduk. Lantas kita ingin memberikan tempat duduk kita kepada salah satu dari mereka. Kepada siapa mesti kita berikan?
Dengan justice approach, kita mesti mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan di antara mereka. Seperti siapa di antara mereka yang sudah lebih lama berdiri dan siapa yang lebih jauh tempat tujuannya. Dengan begitu, kita bisa mengukur pengaruh dari keputusan moral yang akan kita ambil, seadil-adilnya.
Rights approach. Pendekatan ini membebaskan kita untuk mengambil keputusan apa pun, dengan syarat tidak melanggar atau mengurangi hak yang dimiliki setiap orang. Artinya, pendekatan ini mensyaratkan kesadaran akan hak diri kita pribadi dan orang lain atau siapa pun yang terlibat dalam kasus dilema moral yang dihadapi.
Contoh yang diberikan Pak Faiz dalam sesi Ngaji Filsafat-318 edisi Berpikir Etis adalah terkait Ngaji Filsafat itu sendiri. Jikalau Pak Faiz, sebagai pengampu Ngaji Filsafat, membuat keputusan untuk mewajibkan santri-santrinya mengikuti setiap sesi secara full time, hal tersebut merupakan keputusan yang tidak etis. Sebab setiap santri punya hak pribadi, seperti hak untuk istirahat, untuk belajar, atau untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lainnya.
Demikianlah. Semua perilaku kita dipengaruhi betul oleh apa yang ada dalam kepala kita. Perbuatan baik lahir dari pikiran baik. Mereka yang bermoral dalam perbuatan adalah mereka yang mampu etis sejak dalam pikiran.
Category : buletin
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan
- Buku Ngaji Pascakolonial