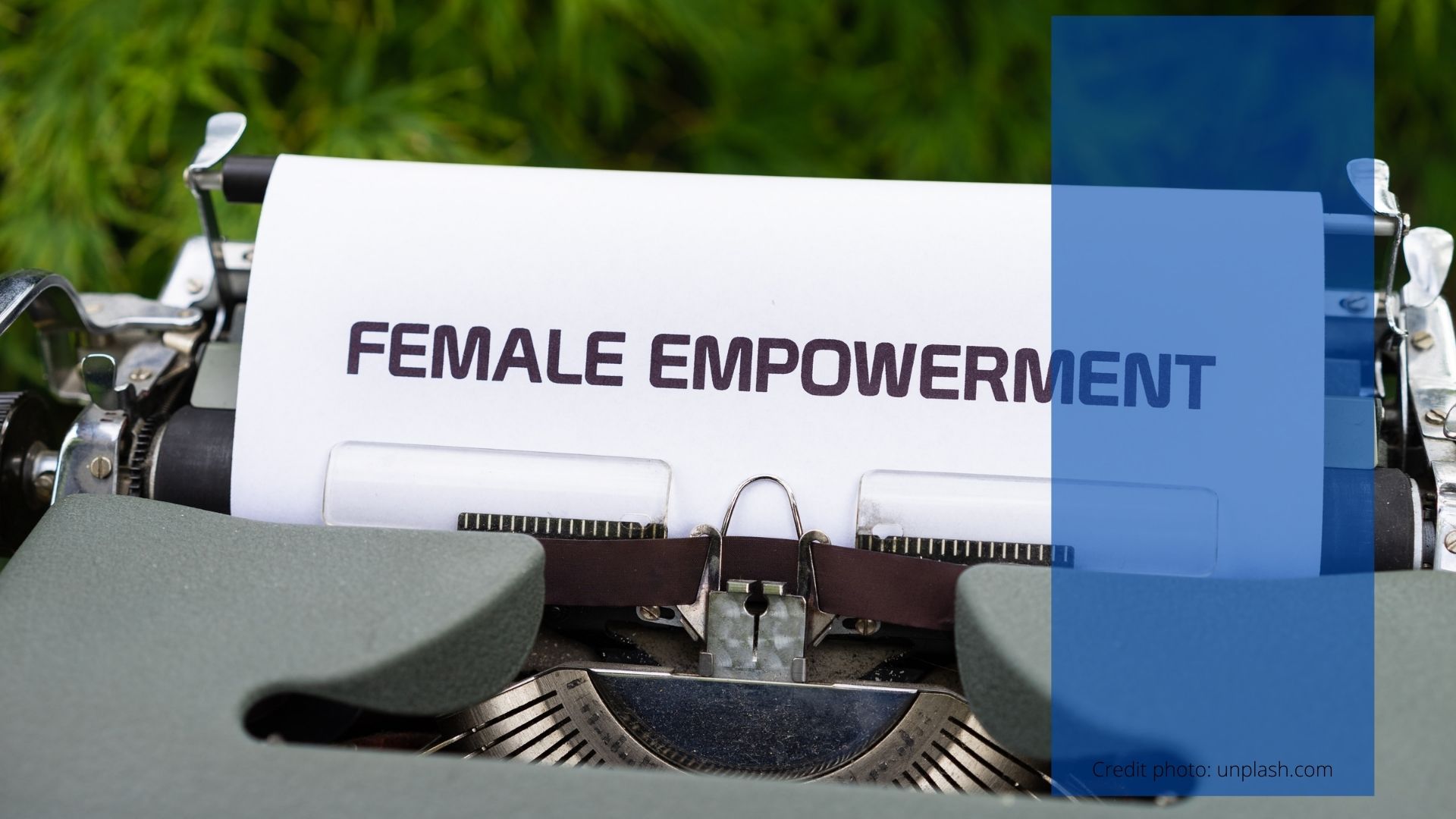Diskursus Feminisme Pascakolonial
Feminisme pascakolonial dikategorikan sebagai pemikiran dan gerakan gelombang ketiga dalam arus besar feminisme. Dalam bacaan saya, ada tiga hal yang memengaruhi kemunculan feminisme pascakolonial tersebut, yaitu: 1). Berkembangnya diskursus pascastrukturalisme maupun pascakolonialisme yang membuka jalan bagi kemunculan feminisme pascakolonial; 2). Pengalaman dikolonisasi yang menimpa Dunia Ketiga; 3). Reaksi kritis atas perkembangan feminisme mainstream (feminis Barat). Ketiga hal tersebut tentu mempunyai keterhubungan antara yang satu dengan yang lain.
Pertama, dalam diskursus pascakolonialisme muncul anggapan sebagaimana yang dijelaskan oleh Ania Loomba dalam buku Kolonialisme/Pascakolonialisme (2015) bahwa, negara-negara yang baru meraih kemerdekaan tidak secara otomatis dapat menghadirkan kesejahteraan atau keadilan. Dengan kata lain, masih ada permasalahan dalam distribusi keadilan, dan dengan demikian ada subjek-subjek yang tertindas. Diskursus pascakolonialisme menyoroti ketimpangan tersebut dan menaruh perhatian kepada subjek-subjek yang tertindas, termasuk kaum perempuan.
Keduanya, dalam konteks feminisme pascakolonial, perempuan dianggap mengalami ketertindasan ganda; pertama yang bersumber dari budaya patriarki, keduanya dari praktik kolonialisme. Dua hal itu yang membuat perempuan kesulitan untuk mengaktualisasikan dan merepresentasikan dirinya sendiri.
Salah satu pemikir feminis pascakolonial ternama, yakni Gayatri Spivak menulis esai yang sangat berpengaruh, “Dapatkah Subaltern Berbicara?”. Dalam esainya itu, Spivak menyoroti tradisi Sati di India, ketika suara perempuan yang melakukan tradisi tersebut justru tidak terdengar. Sementara pada sisi yang lain, justru laki-laki kulit putih Inggris yang menganggap bahwa budaya tersebut tidak manusiawi, dan laki-laki India yang menganggap bahwa perempuan yang melakukan tradisi tersebut didorong oleh keikhlasan karena rasa cinta terhadap suaminya.
Dalam studi feminsme pascakolonial kemudian menaruh perhatian lebih terhadap kelompok subaltern ini, yang diartikan sebagai kelompok bisu. Meminjam pendapat Titiek Kartika dalam buku “Perempuan Lokal Vs Tambang Pasir Besi Global” (2014), kelompok bisu yaitu mereka yang berada di luar representasi sosial dan politik serta berada dalam posisi paling bawah dalam relasi kekuasaan global. Penjelasan singkat ini jelas menunjukkan adanya koherensi antara pascakolonialisme dan feminisme pascakolonial yang sama-sama menaruh perhatian lebih terhadap subjek-subjek yang tertindas.
Poin-poin yang diuraikan di atas menggambarkan secara singkat bagaimana pascakolonialisme yang menginspirasi perkembangan feminisme pascakolonial. Wacana yang dimainkan di dalamnya dipengaruhi juga oleh pengalaman dikolonisasi yang menimpa Dunia Ketiga. Hal penting dalam feminisme pascakolonial lainnya, yaitu kritik mereka terhadap warisan kolonialisme, seperti superioritas Barat atau kulit putih. Salah satunya, yakni sorotan tajam para pemikir feminis pascakolonial terhadap pemikiran dan gerakan feminisme Barat.
Para pemikir feminis pascakolonial mengkritik para feminis Barat (mainstream) yang dianggap kerap kali mendudukkan diri sebagai subjek yang lebih superior, dan mengandaikan perempuan di seluruh dunia menginginkan sebagaimana pencapaian para perempuan Barat. Singkat kata, feminis pascakolonial menolak klaim universalisme yang bersumber dari sikap Barat sentris atau Eurosentris. Hal yang ditekankan oleh feminis pascakolonial, yakni keberagaman atau pluralitas pengalaman perempuan yang tidak bisa disamakan begitu saja.
Adapun salah satu pemikir feminisme pascakolonial yang begitu keras mengkritik feminisme Barat karena dianggap kerap kali melihat perempuan Dunia Ketiga, yaitu Chandra Talpade Mohanty. Singkatnya, Mohanty dalam tulisannya “Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses” (2008) mengkritik kecenderungan pemikir feminis Barat yang kerap kali mengasumsikan bahwa, perempuan-perempuan di seluruh dunia harus mencapai sebagaimana pencapaian para perempuan Barat.
Logika dalam Penelitian Feminisme Pascakolonial
Dalam riset yang menggunakan paradigma feminis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lim Sing Meij dalam Ruang Sosial Perempuan Tionghia (2009), jelas memungkinkan perempuan berbicara untuk dirinya sendiri, mengisi celah sejarah, menolak stereotip, dan konstruksi identitas yang dipaksakan dari luar. Dengan demikian, mereka dapat mengungkap kesejarahan mereka melalui validasi tentang kehidupan mereka yang sesungguhnya.
Konsekuensi logis dari ungkapan di atas, yakni penolakan atas klaim bahwa peneliti harus netral atau bebas nilai, sebagaimana yang banyak diglorifikasi oleh pandangan positivis. Dalam konteks feminisme pascakolonial, penelitian pun bersifat subjektif. Adapun yang dimaksud subjektif di sini yakni, keberpihakan peneliti mengingat yang diteliti adalah mereka yang berada dalam posisi marjinal, yang bahkan di luar representasi sosial dan politik. Peneliti feminis pascakolonial harus terlibat aktif dalam melakukan kritik terhadap tatanan yang menindas. Inilah posisi yang diambil dalam riset feminis pascakolonial.
Karena itu, yang diandaikan dalam penelitian feminisme pascakolonial yakni, mengungkap suara-suara mereka yang selama ini mengalami marjinalisasi dan ketertindasan. Selain itu, yang diandaikan dalam riset feminis pascakolonial adalah mengungkapkan agensi perempuan yang selama ini tersembunyi. Dari sini, hubungan yang dibangun antara peneliti dan subjek yang diteliti diandaikan pada logika intersubjektif. Dengan demikian, pengetahuan yang dihasilkan juga bersifat praksis.
Dalam dunia akademik, peneliti yang menggunakan paradigma pascakolonial jelas saja mendapat tantangannya sendiri, salah satunya karena masih cukup kuatnya pengaruh positivisme. Akan ada akademisi lain yang mempertanyakan keilmiahan riset feminisme pascakolonial karena dianggap tidak netral. Akan tetapi, para akademisi feminisme pascakolonial tidak akan mempermasalahkan anggapan ketika penelitian mereka tidak netral, karena feminisme pascakolonial yang tergolong pendekatan kritis ini, sejak awal memang menolak klaim netralitas pengetahuan.
Bagi saya sendiri justru menjadi hal yang irrelevan, ketika suatu penelitian menggunakan paradigma feminisme pascakolonial, tetapi “dipaksakan” untuk mengikuti logika netralitas sebagaimana yang diglorifikasi oleh positivisme. Bukankah salah satu prasyarat ilmiah sendiri memestikan adanya konsistensi dalam melakukannya (misalnya antara pendekatan yang digunakan dengan cara kerja penelitian)?
Poin keduanya, klaim netralitas pengetahuan sendiri sudah dibongkar oleh Habermas yang menyebut bahwa pengetahuan selalu terkait dengan kepentingan. Dan bagi saya, sebagaimana pandangan Habermas, tugas ilmu-ilmu sosial adalah untuk kepentingan emansipatoris, yakni pembebasan dari ketertindasan dan turut mengupayakan keadilan. Demikian.
Category : filsafat
SHARE THIS POST
Lapak MJS
- Sekar Macapat dalam Wacana dan Praktik
- Nisan Hamengkubuwanan: Artefak Makam Islam Abad XVIII-XIX di Yogyakarta dan Sekitarnya
- Lima Puluh Tahun: Meniti Jalan Kembali
- Buletin Bulanan MJS Edisi ke-9 Maret 2025 M
- Buku Terjemah Rasa II: Tentang Hidup, Kebersamaan, dan Kerinduan
- Buku Ngaji Pascakolonial