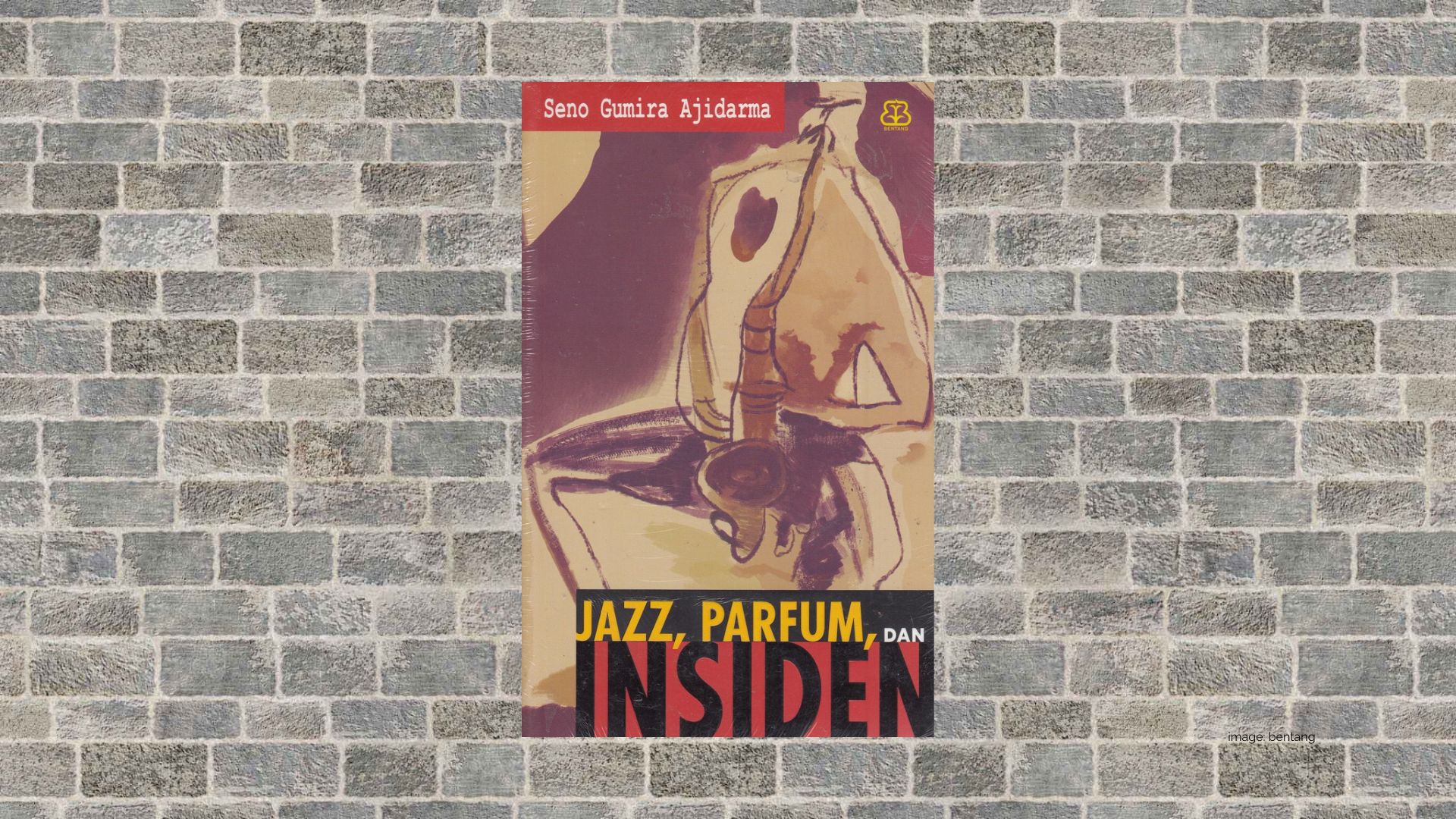Judul: Jazz, Parfum, dan Insiden ǀ Penulis: Seno Gumira Ajidarma ǀ Penerbit: Bentang ǀ Cetakan: 2017 ǀ Tebal: viii + 188 halaman ǀ ISBN: 978-602-291-307-8
“Ketika jurnalisme dibungkam, sastra harus bicara. Karena bila jurnalisme bicara dengan fakta, sastra bicara dengan kebenaran. Fakta-fakta bisa diembargo, dimanipulasi, atau ditutup dengan tinta hitam, tapi kebenaran muncul dengan sendirinya, seperti kenyataan. Jurnalisme terikat oleh seribu satu kendala, dari bisnis sampai politik, untuk menghadirkan dirinya, namun kendala sastra hanyalah kejujurannya sendiri. Buku sastra bisa diberedel, tetapi kebenaran dan kesusastraan menyatu bersama udara, tak tergugat dan tak tertahankan. Menutupi fakta adalah tindakan politik, menutupi kebenaran adalah perbuatan paling bodoh yang bisa dilakukan manusia di muka bumi (Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara, Bentang Budaya, 1997).
Rezim Orde Baru menghadirkan banyak catatan kelam, termasuk terkait dunia jurnalisme. Seno Gumira Ajidarma tahu betul hal itu. Ia merasakannya sendiri ketika majalah Jakarta Jakarta, tempatnya bekerja, diberangus dan ia dipindahtugaskan karena pemberitaan mengenai Insiden Dili.
Pengalaman dan semangatnya mengungkap kebenaran itulah yang membuatnya menulis Trilogi Insiden—kumpulan cerita pendek Saksi Mata (1994), novel Jazz, Parfum, dan Insiden (1996), dan kumpulan esai Ketika Jurnalisme Dibungkam Sastra Harus Bicara (1997). Semuanya dengan berani berbicara tentang peristiwa berdarah di Timor Timur itu.
Seno memang sudah sering menulis tentang tema-tema yang tabu selama rezim Orde Baru berkuasa, seperti hilangnya orang-orang bertato dan fenomena penembak misterius lewat karya sastranya. Namun, Trilogi Insiden punya peran besar untuk membuka mata banyak orang terkait kekerasan. Betapa kekerasan, dengan segala bentuknya, adalah hal yang harus dihentikan.
Melalui novel Jazz, Parfum, dan Insiden Seno lebih leluasa menyuguhkan horor dari usaha aneksasi yang dilakukan militer Indonesia di Timor Timur—ketimbang dua buku lain dari triloginya. Dalam novel ini, peristiwa berdarah di Timor Timur, khususnya Insiden Dili pada November 1991, ditampilkan lewat subbab utama “Insiden” yang dimulai dari “Laporan Insiden 1” sampai “Laporan Insiden 8”.
Diceritakan bahwa tokoh Aku adalah seorang jurnalis—yang dapat ditafsirkan sebagai cerminan Seno sendiri. Tokoh Aku sedang lembur di kantor untuk mengolah berita berdasarkan laporan-laporan jurnalistik yang masuk ke meja redaksi dari para wartawan di lapangan.
Laporan-laporan itu berupa kesaksian para narasumber yang sebagian besar adalah korban tragedi itu sendiri. Lewat pembacaan tokoh Aku terhadap laporan-laporan itu, kita—pembaca novel ini—diajak menyaksikan laku kejam pihak militer dan turut menyelami penderitaan para korban.
Kita disuguhkan laporan pembantaian para demonstran dengan berbagai cara yang untuk dibayangkan saja sudah membuat merinding. Dalam “Laporan Insiden 1” misalnya, seorang pemuda demonstran memberi kesaksian bahwa 3.500 orang ikut demonstrasi hari itu dan berkumpul di kuburan untuk prosesi tabur bunga. Mereka hanya membawa spanduk dan bendera tanpa ada senjata tajam.
Hingga tiga truk tentara datang dan memblokir jalan. Tahu-tahu tembakan pertama meletus dan bersambung dengan tembakan lainnya selama lima sampai sepuluh menit. Pemuda itu melihat semua orang yang berada di depannya berjatuhan. Seperti di film, katanya.
Mereka yang masih hidup dikumpulkan lalu ditelanjangi dan kemudian dipukuli dengan kayu yang ada paku di ujungnya, ditumbuk pakai batu, atau ditusuk kepalanya dengan pisau. Pemuda itu sendiri dipaksa merasakan bolpoin masuk ke organ genitalnya.
Hal yang lebih memprihatinkan lagi ketika, ternyata, berita-berita yang beredar terkait peristiwa pembunuhan massal di pemakaman Santa Cruz itu menyebutkan bahwa hanya 19 orang yang menjadi korban jiwa. Berapa jumlah korban sesungguhnya dalam peristiwa itu nampaknya menjadi salah satu poin yang ingin digugat dan dipertanyakan Seno.
Lewat kesaksian narasumber lainnya, berulang kali disampaikan bahwa mustahil korban jiwa hanya 19 orang. Mengingat betapa merawak rambang para tentara menembaki dan menusuk-nusukkan sangkurnya kepada para demonstran di lokasi kejadian. Tidak peduli tua atau muda, perempuan atau anak-anak sekalipun.
Pada Laporan Insiden seterusnya, kita akan membaca kekejaman dengan wujudnya yang lain. Tentang mereka yang dibawa ke penjara lalu disiksa berbagai rupa: dipukuli ramai-ramai, dipaksa meminum air bercampur darah bekas cucian korban yang luka dan mati, dipotong telinganya, dan sebagainya.
Kekejaman pihak militer, atau pemerintah, juga hadir dalam teror sehari-hari selama pendudukan. Semua orang yang dicap antipemerintah akan lenyap dibawa oleh orang-orang bertopeng. Sebagian besar isi novel ini berkisah tentang kengerian-kengerian itu.
Namun, kepiawaian Seno dalam menulis cerita tidak hanya membuat kita merasakan ketegangan yang nyata. Ia juga menyajikan kisah romantik dalam subbab “Jazz” dan “Parfum” lengkap dengan penghayatannya. “Itulah uniknya jazz bagiku. Ia seperti hiburan, tapi hiburan yang pahit, sendu, mengungkit-ungkit rasa duka. Selalu ada luka dalam jazz, selalu ada keperihan.” (hlm, 15)
Akan ada banyak nama pemusik dan lagu jaz bermunculan. Begitu pula dengan merek parfum dan pemaknaan aromanya. “Barangkali maunya, aroma Eternity berhubungan dengan cinta yang agung, cinta yang setia, abadi, dan selamanya. Itulah yang kupikirkan ketika wanita dengan parfum Eternity ini muncul bagaikan peri, dari balik kegelapan dengan busana serbamerah yang dirancang Donna Karan.” (hlm, 48)
Pada akhirnya, novel Jazz, Parfum, dan Insiden bukan saja menyenangkan sebagai karya sastra, tetapi juga mencerahkan sebagai fakta sejarah. Sekalipun ketika membicarakan sejarah dan sastra secara bersama-sama, muncul pertanyaan: apakah ada fiksi di dalam sejarah dan apakah ada fakta di dalam sastra?
Sebab dalam kaitannya dengan peristiwa sejarah, Kuntowijoyo mendeskripsikan bahwa pada dasarnya objek karya sastra adalah realitas—apa pun yang dimaksud dengan realitas oleh pengarang.
Bila realitas tersebut berupa peristiwa sejarah, karya sastra akan dapat dimaknai sebagai: (1) usaha menerjemahkan peristiwa tersebut dengan maksud untuk bisa dipahami, (2) sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan tanggapan mengenai suatu peristiwa sejarah, (3) upaya penciptaan kembali sebuah peristiwa sejarah. (Budaya dan Masyarakat, 1987)
Namun, saya kira apapun jawabannya tidaklah begitu penting. Seperti yang Seno tulis di halaman awal buku ini, “Mau disebut fiksi boleh, mau dianggap fakta terserah—ini cuma sebuah roman metropolitan.”
Satu hal yang jelas, dalam novel ini, sastra dan sejarah dipadukan dengan memesona. Fakta dan fiksi berkelindan sedemikian rupa. Kengerian peristiwa di Timor Timur itu terasa hadir begitu dekat. Lewat tangan Seno novel sastra ini menjadi saksi sejarah—sejarah yang berusaha untuk ditutupi.
*Timor Timur berubah nama menjadi Timor Leste setelah resmi merdeka pada 20 Mei 2002.